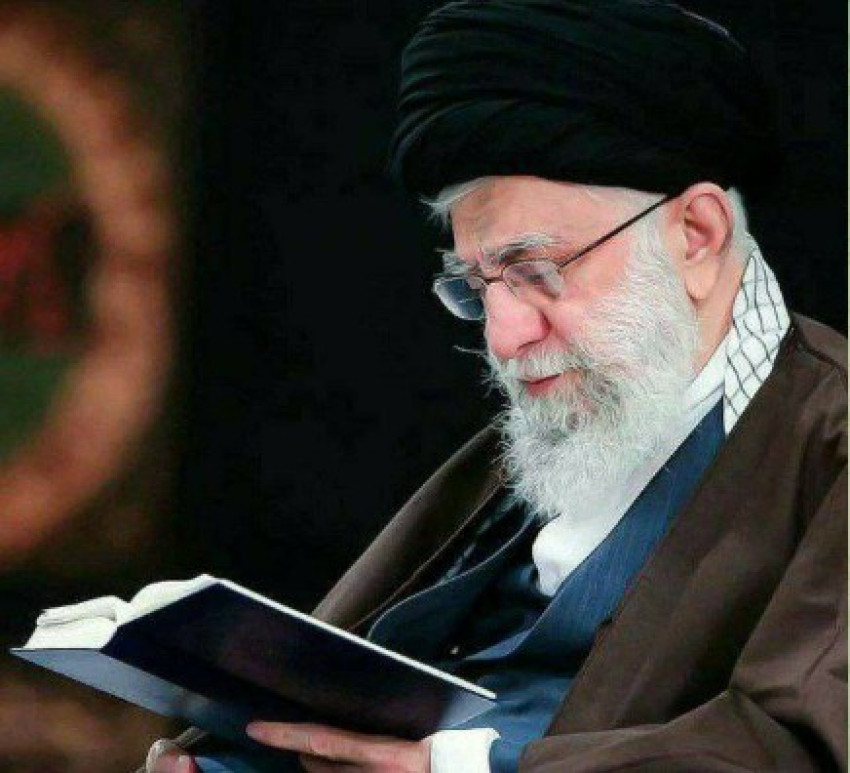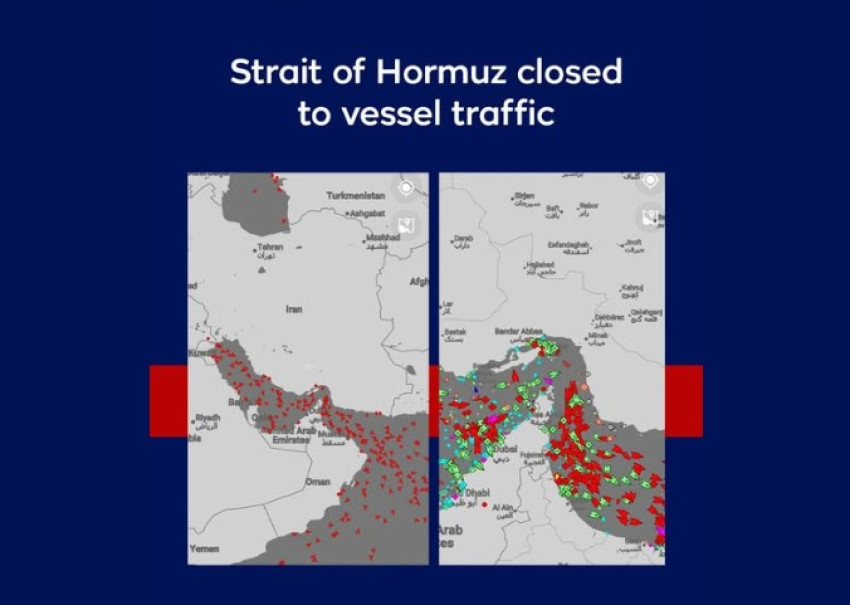Kanal Asmara di Tengah Parit Kebencian: Membaca SAKTI Sastri Bakry
Oleh Dikdik Sadikin*
ORBITINDONESIA.COM - Ada buku yang lahir seperti cahaya lilin di tengah malam panjang. Tidak besar, tapi cukup untuk menyingkap wajah-wajah yang resah dalam gelap. SAKTI, kumpulan puisi tiga bahasa karya Sastri Bakry, adalah lilin semacam itu. Ia menyala dengan sederhana, tapi suaranya menjangkau jauh: dari Padang ke Den Haag, dari Boven Digoel ke Sungai Gangga, dari Simeulue hingga Haneda.
Seorang filsuf Jerman, Friedrich Nietzsche, pernah menulis: “Kita memiliki seni agar kita tidak mati karena kebenaran.”
Barangkali itu pula yang dirasakan Sastri. Ia tahu kebenaran sejarah sering kali terlalu getir untuk ditanggung, maka ia menuliskannya dalam puisi, agar luka tidak membunuh, melainkan menyembuhkan.
Guruku Baik Sekali: Kenangan yang Menjadi Pohon
Puisi pembuka ini adalah sebuah elegi sederhana untuk guru. Tapi lebih dari itu, ia adalah peringatan bahwa pengetahuan bukan sekadar angka dalam rapor, melainkan akar yang menegakkan hidup.
Kata-kata guru dianalogikan sebagai bunga yang “berputik lalu mekar di kebun pemikiran.”
Di Finlandia, guru dipandang setara dengan dokter atau hakim, profesi dengan prestise tinggi.
Di Indonesia, guru lebih sering disebut “pahlawan tanpa tanda jasa”. Sastri merayakan mereka dengan cara yang lain: memberi mereka keabadian dalam bait-bait.
Ada paradoks manis di sini: mata guru tajam, tapi hatinya lembut “seperti pokpia di kantin sekolah.” Sebuah perbandingan yang nyaris banal, tetapi justru menghidupkan keintiman. Mengingatkan kita, kata Rabindranath Tagore, bahwa “Seorang guru sejati melindungi muridnya bukan dengan otoritas, tetapi dengan cinta.”
Kelam di Malam Kelam: Penantian yang Tak Kunjung Usai
Dalam puisi ini, kunang-kunang di hutan gelap menjadi simbol keresahan. “Rahim-rahim yang menunggu dalam kecemasan”. Bait itu seperti sebuah laporan dari dunia yang tercekam, dunia yang menanti kelahiran tapi juga bencana.
Di Bosnia pada 1990-an, orang-orang menunggu di bawah dentuman artileri; di Gaza hari ini, ibu-ibu menunggu dengan rahim penuh cemas. Sastri membawa penantian itu ke dalam bahasa, lalu menutupnya dengan sebuah pertanyaan eksistensial: “Sampai kapan kita menunggu?”
Pertanyaan yang sama mungkin bergema di Myanmar, di Ukraina, atau bahkan di ruang-ruang kelas Indonesia di mana anak-anak menunggu hadirnya keadilan.
Kunang-Kunang Malam: Cahaya yang Menjadi Tanda
Puisi ini seperti firasat. "Kunang-kunang membawa pesan khusus… adakah bencana yang akan datang?” Lalu kalimat yang menghentak: “Katamu kunang-kunang adalah kuku orang meninggal.” Imaji itu sederhana, tapi menyeramkan. Ia menempel di benak seperti bisik-bisik takhayul di malam hujan.
Namun di tengah bayangan maut, ada kilasan kosmopolitan: “17 negara bersapa ria dan saling bercerita.”
Betapa rapuh dunia kita: diplomasi bisa berdering riang di ruang konferensi, sementara di luar jendela, mayat mulai bergelimpangan.
Inilah ironi global: cahaya kecil dari serangga bisa dibaca sebagai pertanda bencana. Sementara lampu sorot panggung internasional kadang gagal melihat tubuh-tubuh yang terbaring di tanah.
Dalam Kedalaman Dalam: Elegi Laut yang Membisu
Ini adalah salah satu puncak emosional SAKTI. Elegi untuk 53 prajurit KRI Nanggala 402 yang tenggelam di Laut Bali. Mereka berbicara dari kedalaman: “Ampuni kami ya Allah… Kami persembahkan untukmu ibu pertiwi.”
Puisi ini tidak jatuh pada sentimentalitas. Ia berdiri tegar seperti doa seorang perwira yang sudah berdamai dengan ajal. Membaca ini, kita seakan mendengar gema sonar dari dasar laut: getir, tapi juga agung.
Ada resonansi global. Kita teringat tragedi kapal selam Kursk milik Rusia pada 2000, atau Titanic yang kini menjadi mitos modern. Laut, dalam semua peradaban, adalah altar pengorbanan. Dan seperti dikatakan Joseph Conrad: “The sea has never been friendly to man. At most it has been the accomplice of human restlessness.”
Kanal Asmara: Pertanyaan yang Menggugat Sejarah
Inilah inti dari seluruh buku. Sastri menulis: “Kenapa kita tidak membangun kanal asmara?” Sebuah pertanyaan lirih, tapi menggugat sejarah. Dunia membangun kanal kekuasaan, kanal propaganda, kanal militer—tapi melupakan kanal cinta.
Puisi ini bergaung lintas batas. Di Gaza, tentara Israel menyalakan ideologi yang menjadikan pembantaian seolah sah, dan penduduk Palestina—anak-anak, perempuan, orang tua—menjadi korban yang tak pernah berhenti berjatuhan. Di Kamboja, Pol Pot membangun “surga” yang berubah neraka. Di Eropa, Nazisme lahir dari luka perang, tapi justru menebarkan kebencian.
Sejarah mengajarkan bahwa kebencian bisa dijadikan proyek nasional. Maka pertanyaan Sastri menjadi penting: mengapa cinta harus dipertanyakan, sementara kebencian dirayakan?
Puisi Sebagai Jalan Sunyi
SAKTI bukan hanya sekadar antologi puisi. Ia adalah kesaksian zaman, jembatan diplomasi kebudayaan, dan doa yang ditulis dengan pena seorang perempuan dari Padang.
Ketika algoritma mereduksi cinta menjadi “like” dan “emoji”, Sastri memilih jalan sunyi: menulis puisi. Seperti kata Pablo Neruda, “Puisi lahir dari penderitaan, seperti bunga dari tanah yang gersang.”
Dan buku kumpulan puisi "SAKTI" ini tak berhenti sebagai teks yang diam di rak. Ia akan dibicarakan, diperdebatkan, diselami. Pada 10 September 2025, pukul 13.30 hingga 16.30 WIB, di PDS HB Jassin, Lt.4 Taman Ismail Marzuki, digelar diskusi buku SAKTI ini.
Dua pemikir lintas batas, Prof. Hashim Yaacob (Malaysia) dan Maman S. Mahayana (Indonesia), akan hadir sebagai pembicara. Beberapa nama akan membacakan puisi: Pipiet Senja, Fanny J. Pyok, Jose Rizal Manua, Armaidi Tanjung, Nuyang Jaimee, Aniek Juliarni. Saya sendiri, Dikdik Sadikin, dipercaya menjadi moderator dalam forum itu. Sebuah kehormatan untuk berada di antara kata-kata yang lahir dari luka sekaligus cinta.
Dan mungkin, inilah yang dimaksud dengan “SAKTI”: kemampuan puisi untuk membuat kita percaya pada sesuatu yang tampak mustahil.
Bahwa di tengah reruntuhan sejarah, masih ada ruang untuk cinta.
Bogor, 18 Agustus 2025
*Dikdik Sadikin adalah penulis dan akuntan. ***