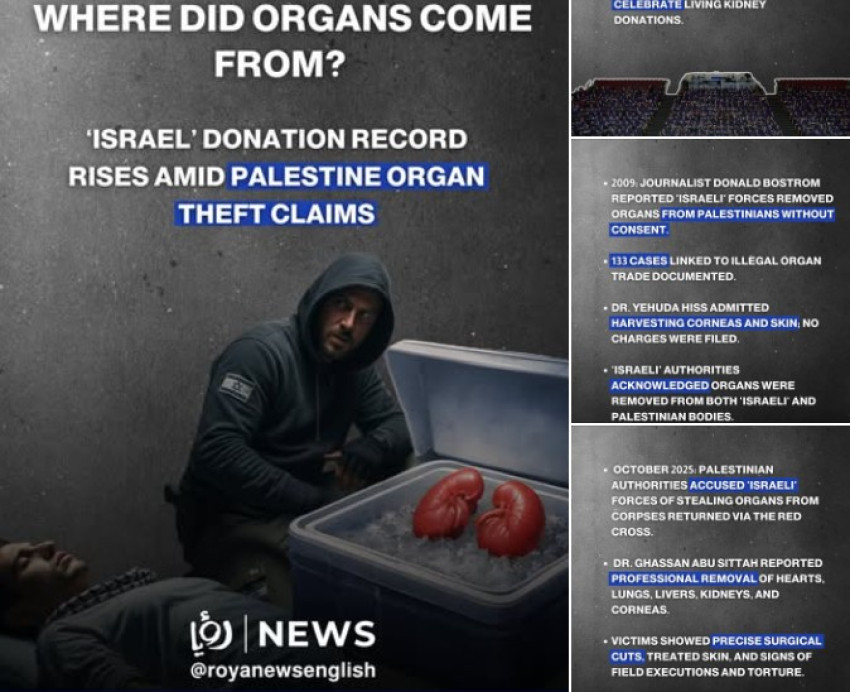Catatan Denny JA: Tiga Skenario Masa Depan PBNU
Oleh Denny JA
ORBITINDONESIA.COM - Pada hari-hari ini, publik menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah panjang Nahdlatul Ulama.
Dari pesan berantai di WhatsApp hingga meja makan selepas Subuh, dari serambi masjid hingga ruang redaksi media nasional, suara yang sama berbisik dengan kecemasan halus:
“Benarkah PBNU kini memiliki dua nakhoda?”
Satu pihak, KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PBNU sebelumnya, menilai pencopotannya cacat prosedur.
Pihak lain, KH Zulfa Mustofa, Penjabat Ketua Umum yang baru ditetapkan, meyakini bahwa pengangkatannya adalah kehendak sah rapat pleno Syuriyah.
Dua tokoh kharismatik. Dua legitimasi yang sama-sama merasa sah.
Di desa-desa, di kota-kota, di grup WhatsApp jamaah, satu kebingungan menggantung seperti kabut tipis yang mengubah rasa pagi:
“Siapa sesungguhnya yang memimpin PBNU hari ini?”
Ini bukan hanya kebingungan administratif. Ia adalah kegelisahan moral, karena NU bukan organisasi biasa.
Ia adalah urat nadi spiritual bangsa; rumah besar tempat puluhan juta jiwa menambatkan keyakinan, tradisi, dan harapan mereka.
Namun kini, rumah besar itu bergetar. Retaknya belum pecah, tetapi gema retaknya menyusup hingga ke hati-hati para santri yang mencari arah:
“Ke mana NU akan melangkah? Dan siapa yang akan menuntunnya?”
-000-
Konflik kepemimpinan bukan hal baru bagi NU. Tahun 1984, NU pernah dihadapkan pada ketegangan besar ketika Gus Dur membawa NU kembali ke Khittah 1926.
Perbedaan tajam merekah: sebagian ingin NU tetap menjadi kekuatan politik, sebagian lain menghendaki NU kembali pada ruh moral dan sosialnya.
Suasana memanas di Muktamar Situbondo, suara meninggi, aspirasi bersilang.
Sebagaimana dicatat Greg Fealy dalam Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967, setiap pergolakan besar di tubuh NU selalu memuat dua lapis drama sekaligus: perebutan posisi di permukaan, dan pencarian kompas moral di kedalaman.
Pada akhirnya, bukan sekadar hitungan suara yang menyelamatkan NU, melainkan kearifan kiai-kiai sepuh yang menjadi jangkar etika ketika ombak politik datang terlalu tinggi.
KH Ahmad Siddiq, KH Ali Maksum, KH As’ad Syamsul Arifin adalah para kiai sepuh yang dihormati, dan besar peranannya menyatukan NU kembali.
Dari situlah NU belajar bahwa konflik bukan kutukan.
Ia dapat menjadi pintu pembaruan, asal dibuka dengan keteduhan jiwa.
Pelajaran itu kini kembali dipanggil. Namun konflik kali ini membawa lapisan-lapisan baru yang lebih kompleks dan sensitif.
-000-
Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern NU, publik mendengar desas-desus tentang konsesi tambang yang dikaitkan dengan tokoh tertentu.
Isu ini belum terverifikasi sepenuhnya, dan banyak tokoh menolaknya dengan tegas.
Namun seperti asap tanpa api… isu itu tetap menyebar.
Ia hidup di ruang publik, menciptakan warna baru dalam konflik: nuansa ekonomi, sumber daya alam, dan kepentingan-kepentingan besar yang biasanya berada jauh dari gelanggang perdebatan jam’iyah.
Mengapa isu ini begitu mengguncang?
* Karena ia menyentuh akses kekayaan alam, sesuatu yang jauh lebih eksplosif dari sekadar perebutan posisi struktural.
* Karena jika NU terseret dalam pusaran tambang, maka kepercayaan moral umat ikut dipertaruhkan.
* Karena konflik ini bukan lagi sekadar siapa ketua umum yang sah, tetapi apa yang sesungguhnya diperebutkan di balik layar.
Kekuatan terbesar NU justru lahir ketika NU melepaskan diri dari cengkeraman politik praktis dan kepentingan material yang sempit.
Saat NU berdiri di atas Khittah, ia memegang “otoritas simbolik” yang membuatnya didengar bukan karena kekuasaan, tetapi karena kebijaksanaan.
Ketika otoritas simbolik itu terkikis oleh tarik-menarik sumber daya alam, yang terancam bukan hanya struktur, tetapi ruh jam’iyah.
Untuk itulah, konflik PBNU hari ini tak bisa hanya dibaca melalui AD/ART. Ia adalah ujian integritas moral di tengah menguatnya politik sumber daya alam di Indonesia.
-000-
Tiga Skenario PBNU ke Depan
Pertama: Rekonsiliasi, Islah
Bayangkan sebuah malam yang teduh. Para kiai sepuh berkumpul, memanggil dua tokoh: Gus Yahya dan Zulfa Mustofa. Ikut dipanggil pula dua tim besar di balik dua tokoh itu.
Keduanya duduk bukan sebagai rival, tetapi sebagai khadim, pelayan jam’iyah.
Dalam pertemuan itu, ego mereda. Kecurigaan mencair.
Dan keputusan bijak lahir:
NU menyegerakan Muktamar istimewa yang diterima semua pihak.
Ini adalah skenario yang menyembuhkan. NU bukan hanya selamat, ia bangkit lebih kuat.
Di jalan ini, NU kembali pada Khittah: menjadi mercusuar moral bangsa, bukan sekadar aktor di panggung kekuasaan.
Suara PBNU kembali bulat, wibawanya pulih, dan umat menemukan lagi satu titik rujukan ketika negeri ini bising oleh klaim-klaim kebenaran yang saling bertabrakan.
-000-
Kedua: Dualisme Sementara
Inilah skenario kabut yang membingungkan. Dua ketua umum. Dua legitimasi. Dua arah yang saling menyaingi, meski sama-sama mengatasnamakan jam’iyah.
Di desa, jamaah bertanya, “Harus ikut siapa?”
Di pesantren, santri ragu, “Nama ketua umum yang mana yang harus kami sebut di ceramah besok?” Di kota, pengurus cabang menunggu kepastian yang tak kunjung datang.
NU tetap berdiri, tetapi suaranya serak, wibawanya meredup, dan arahnya kabur.
Dalam skenario ini, dualisme dibiarkan menggantung dengan harapan “waktu akan menyelesaikan.”
Pada akhirnya, mungkin akan lahir kesepakatan baru, Muktamar baru, dan persatuan baru.
Namun harga yang dibayar adalah hilangnya momentum moral: nasihat PBNU tak lagi sekuat dulu, karena publik melihat organisasi yang tak selesai dengan dirinya sendiri.
-000-
Ketiga: Dualisme Permanen
Luka yang Menjadi Parut Abadi. Ini skenario paling gelap. Konflik tak mereda. Dua kubu mengeras.
Satu mengikuti Gus Yahya. Satu mengikuti Zulfa Mustofa. Seandainya pun pemerintah turut campur memutuskan NU mana yang sah, pengurus lain tetap membentuk sejenis NU tandingan, dengan sedikit mengubah nama.
Dua struktur, dua panggung, dua narasi yang saling menegasikan.
NU tetap disebut sebagai jam’iyah terbesar di dunia, tetapi ruh kebesarannya memudar.
Ia berdiri seperti pohon tua yang batangnya terbelah: rimbun, tetapi rapuh; tegak, tetapi tak lagi meneduhkan.
Dalam skenario ini, pelajaran sejarah yang digarisbawahi: setiap kali NU membiarkan perpecahan berlarut-larut, yang hilang bukan hanya kesatuan organisasi, tetapi juga kepercayaan publik yang dibangun puluhan tahun.
Jika NU retak, retak pula salah satu fondasi kedamaian sosial dan Islam moderat Indonesia.
-000-
Konflik PBNU hari ini bukan hanya tentang siapa ketua umum. Ia tentang wajah Islam Nusantara di mata umat dan bangsa.
Ia tentang keutuhan tradisi, tentang Khittah yang dulu diperjuangkan dengan air mata dan ijtihad; tentang moralitas sebuah jam’iyah yang selama ini menjadi jangkar bagi puluhan juta umat.
Sejarah telah mencatat berkali-kali: NU selalu mampu menemukan cahayanya kembali, bahkan di gelap yang paling pekat.
Tetapi itu hanya terjadi ketika para pemimpinnya memilih persatuan di atas ego, kedewasaan di atas ambisi, dan Khittah di atas manuver sesaat.
Ketegangan ini sejatinya cermin perjalanan bangsa mencari kebijaksanaan di tengah perebutan kekuasaan. Bila NU menemukan kedewasaannya, Indonesia pun akan menemukan kembali keseimbangan moralnya.
Publik menunggu. Bangsa menunggu. Jutaan santri, ibu-ibu tahlilan, para kiai kampung, semuanya menunggu.
Mereka menunggu NU yang satu, bukan dua. NU yang bulat, bukan terbelah. NU yang kembali menjadi pelita moral bangsa, bukan sekadar pemain di gelanggang kekuasaan.
Persatuan NU bukan hanya kebutuhan organisasi. Ia adalah kebutuhan Indonesia.
Dan ketika para pemimpin NU kelak menengok ke belakang, sejarah akan mengingat keputusan mereka: apakah mereka memilih menjadi generasi yang membiarkan rumah besar ini retak.
Atau generasi yang dengan jiwa besar menguatkan kembali dinding-dindingnya.
Semoga yang tercatat adalah yang kedua. Yaitu keputusan akan pentingnya NU yang satu, yang diputuskan dengan hati yang jernih, bukan dari kemarahan, melainkan dari kebijaksanaan.
Sebab NU, seperti mata air tua di tengah padang. Ia hanya dapat menghidupi bangsa bila ia tetap satu aliran. Ketika pecah menjadi dua, airnya tak lagi menghilangkan dahaga, hanya menyisakan retakan di tanah.*
Jakarta, 11 Desember 2025
REFERENSI
1. Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967, LKiS Pelangi Aksara, 2012.
2. Kacung Marijan, Quo Vadis NU: Setelah Kembali ke Khittah 1926, Erlangga / Gelora Aksara Pratama, 1992.
-000-
Ratusan esai Denny JA soal filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, politik demokrasi, sejarah, positive psychology, catatan perjalanan, review buku, film dan lagu, bisa dilihat di FaceBook Denny JA’s World
https://www.facebook.com/share/p/1D9oHKGYxK/?mibextid=wwXIfr