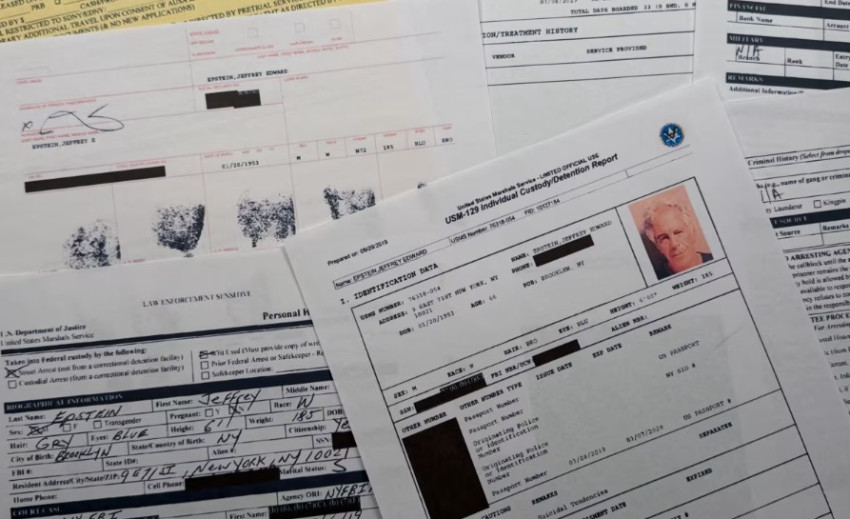Pius Lustrilanang: Banjir Sumatra dan Kejujuran Negara Membaca Kenyataan
Oleh Pius Lustrilanang, akademisi Unsoed
ORBITINDONESIA.COM - Setiap musim hujan tiba, sebagian wilayah Sumatera kembali tenggelam. Sungai meluap, sawah rusak, rumah terendam, jalur distribusi terputus, dan ribuan warga harus mengungsi. Polanya berulang dari tahun ke tahun, seolah banjir telah menjadi peristiwa rutin yang diterima sebagai nasib. Yang berubah hanyalah skalanya: dampaknya kian luas dan berat. Namun negara masih ragu menyebutnya apa adanya—bencana nasional.
Keraguan ini bukan sekadar soal istilah administratif, melainkan soal cara negara membaca realitas. Ketika sebuah bencana berdampak lintas kabupaten dan provinsi, berulang secara sistemik, serta melampaui kapasitas pemerintah daerah, maka secara substansi ia telah menjadi persoalan nasional. Menolak menyebutnya demikian berisiko menunda solusi yang lebih mendasar dan berjangka panjang.
Dalam Risk Society (1992), Ulrich Beck mengingatkan bahwa bencana modern jarang bersifat “alami” murni. Ia lahir dari pertemuan antara alam dan keputusan manusia: tata ruang yang keliru, eksploitasi sumber daya tanpa kendali, serta pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan.
Banjir di Sumatera menunjukkan ciri itu dengan jelas. Deforestasi di hulu, alih fungsi lahan, pelemahan perlindungan daerah resapan, dan sistem drainase perkotaan yang tertinggal telah membangun risiko jauh sebelum hujan turun.
Curah hujan ekstrem kerap dijadikan penjelasan utama. Padahal hujan hanyalah pemicu, bukan sebab. Akar masalahnya struktural, dan karena itu dampaknya pun meluas serta berulang.
Dalam kerangka tata kelola publik, risiko dikategorikan “nasional” bukan karena label, melainkan karena skala dampak dan kebutuhan respons. Christopher Hood, dalam The Art of the State (1998), menekankan bahwa ketika persoalan melampaui batas sektoral dan kewenangan lokal, negara wajib hadir melalui pendekatan whole-of-government.
Banjir Sumatra memenuhi kriteria itu. Ia terjadi di banyak wilayah, menimbulkan kerugian sosial-ekonomi signifikan, mengganggu ketahanan pangan dan logistik, serta menekan kelompok paling rentan. Selain kerugian material, banjir juga meninggalkan dampak sosial yang kerap luput dihitung: putusnya akses pendidikan, meningkatnya risiko kesehatan, serta hilangnya rasa aman masyarakat terhadap masa depan. Secara substansi, semua unsur bencana nasional telah terpenuhi.
Lalu mengapa status nasional kerap tidak disematkan? Jawabannya tidak sepenuhnya teknis. Penetapan bencana nasional membawa konsekuensi politik dan fiskal: kebutuhan anggaran besar, koordinasi lintas kementerian, serta pengakuan bahwa persoalan ini bukan kegagalan daerah semata, melainkan tanggung jawab bersama. Dalam praktik birokrasi, pengakuan sering kali lebih sulit daripada penanganan darurat yang bersifat sementara.
Akibatnya, respons yang muncul cenderung tambal-sulam. Bantuan logistik disalurkan, perbaikan darurat dilakukan, lalu perhatian bergeser hingga musim hujan berikutnya datang. Amartya Sen, dalam Development as Freedom (1999), mengingatkan bahwa kegagalan negara tidak hanya terjadi ketika ia tidak bertindak, tetapi juga ketika ia salah mendefinisikan masalah. Diagnosis yang keliru akan melahirkan kebijakan yang selalu tertinggal dari dinamika risiko yang dihadapi masyarakat.
Konsekuensi pendekatan ini nyata. Pemerintah daerah dipaksa memikul beban yang melampaui kapasitas fiskal dan teknisnya. Masyarakat hidup dalam siklus kerentanan yang tak pernah diputus. Sementara akar persoalan—tata ruang, penegakan hukum lingkungan, rehabilitasi hutan, dan adaptasi perubahan iklim—tetap berada di pinggir agenda nasional, seolah bukan prioritas bersama.
Menyebut banjir Sumatra sebagai bencana nasional bukan berarti meniadakan peran daerah. Justru sebaliknya, itu adalah prasyarat agar negara pusat mengambil tanggung jawab strategis. Negara harus hadir bukan hanya ketika air sudah merendam rumah warga, tetapi jauh sebelumnya: dalam kebijakan tata ruang yang tegas, pengendalian izin yang konsisten, rehabilitasi lingkungan yang berkelanjutan, serta integrasi pembangunan dengan risiko iklim.
James C. Scott, dalam Seeing Like a State (1998), mengingatkan bahaya ketika negara menyederhanakan realitas kompleks menjadi kategori administratif yang nyaman. Banjir Sumatra adalah contoh nyata. Ketika dampaknya nasional tetapi perlakuannya lokal, negara akan selalu tertinggal dari kenyataan di lapangan.
Pada akhirnya, menyebut banjir Sumatera sebagai bencana nasional bukan soal retorika atau sensasi. Ini soal keberanian negara bersikap jujur terhadap skala masalah yang dihadapi. Negara yang matang tidak takut pada pengakuan. Ia memahami bahwa mengakui kenyataan adalah langkah pertama untuk memperbaikinya.
Jika tidak, banjir akan terus datang, korban akan terus berjatuhan, dan setiap tahun kita akan mengulang pertanyaan yang sama—padahal jawabannya sudah lama ada di depan mata.***


.jpeg)