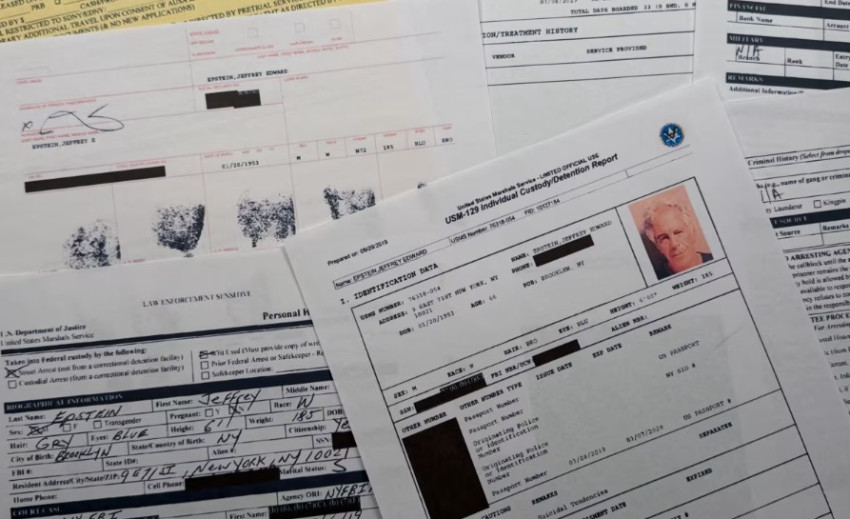Hari Pantun Nasional: Refleksi Akademik atas Pelestarian Sastra Lisan dan Identitas Bangsa
Oleh Ahmad Gusairi, penulis dan penyair
ORBITINDONESIA.COM - Penetapan Hari Pantun Nasional setiap tanggal 17 Desember melalui Keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 163/M/2025 merupakan tonggak penting dalam kebijakan pelestarian kebudayaan nasional. Kebijakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan pengakuan UNESCO pada 17 Desember 2020 yang menetapkan pantun sebagai Warisan Budaya Tak Benda Kemanusiaan.
Dalam perspektif kebudayaan, pengakuan internasional tersebut menegaskan bahwa pantun bukan hanya milik komunitas lokal, tetapi juga memiliki nilai universal yang relevan bagi peradaban manusia.
Secara konseptual, pantun dapat dipahami sebagai bagian dari sastra lisan yang, menurut pemikiran Walter J. Ong, hidup dalam tradisi masyarakat yang mengandalkan ingatan, pengulangan, dan performativitas. Sastra lisan tidak hanya menyimpan teks, tetapi juga konteks sosial, nilai moral, dan cara berpikir kolektif masyarakat pendukungnya. Dengan demikian, pantun bukan sekadar produk estetika bahasa, melainkan praktik budaya yang merekam cara masyarakat Nusantara memahami kehidupan.
Struktur pantun yang terdiri atas sampiran dan isi mencerminkan pola pikir yang sistematis dan simbolik. Dalam kajian struktural sastra, keteraturan rima dan irama pantun menunjukkan adanya kesadaran akan harmoni dan keseimbangan. Sampiran berfungsi sebagai jembatan imajinatif yang mengantar pembaca atau pendengar menuju isi. Pola ini sejalan dengan pandangan Claude Lévi-Strauss tentang cara berpikir simbolik masyarakat tradisional yang menyampaikan makna melalui hubungan tidak langsung, metafora, dan asosiasi.
Dari sudut pandang pendidikan, pantun memiliki relevansi yang kuat dengan konsep pendidikan karakter. Nilai-nilai yang terkandung dalam pantun—seperti kesantunan berbahasa, kebijaksanaan dalam bertindak, serta kehati-hatian dalam menyampaikan pendapat—selaras dengan gagasan pendidikan holistik yang dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara. Pendidikan, menurutnya, tidak hanya mencerdaskan akal, tetapi juga membentuk budi pekerti. Pantun, dengan bahasa yang halus dan pesan yang mendalam, menjadi media yang efektif untuk tujuan tersebut.
Namun, dalam konteks modern, pantun menghadapi tantangan yang tidak ringan. Globalisasi dan digitalisasi telah mengubah lanskap komunikasi dan budaya. Menurut teori globalisasi budaya, arus informasi yang cepat cenderung mendorong homogenisasi budaya dan melemahkan tradisi lokal. Dalam situasi ini, penetapan Hari Pantun Nasional dapat dipandang sebagai bentuk counter discourse, yakni upaya sadar negara untuk mempertahankan keberagaman budaya dan melindungi warisan lokal dari marginalisasi.
Pelestarian pantun, sebagaimana ditegaskan dalam kajian warisan budaya tak benda UNESCO, harus bersifat living heritage—warisan yang hidup. Artinya, pantun tidak cukup hanya didokumentasikan, tetapi perlu terus dipraktikkan, ditransmisikan, dan dikontekstualisasikan. Tanpa proses pewarisan aktif, pantun berisiko menjadi artefak budaya yang kehilangan fungsi sosialnya. Oleh karena itu, Hari Pantun Nasional seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat praktik pantun dalam kehidupan sehari-hari.
Konsep kearifan lokal juga menjadi landasan penting dalam memahami makna pantun. Kearifan lokal, menurut para ahli antropologi budaya, adalah hasil akumulasi pengalaman kolektif masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial dan alam. Pantun merekam kearifan tersebut dalam bentuk bahasa yang padat dan bermakna. Nilai kesantunan, musyawarah, dan keseimbangan hidup yang terkandung dalam pantun sangat relevan untuk menjawab krisis etika komunikasi di era digital.
Lebih jauh, pantun memiliki peran strategis dalam pembentukan identitas dan jati diri bangsa. Benedict Anderson menyebut bangsa sebagai “komunitas terbayang” yang dibangun melalui simbol, bahasa, dan narasi bersama. Pantun dapat berfungsi sebagai salah satu simbol kultural yang memperkuat rasa kebangsaan. Dengan menjadikan pantun sebagai produk budaya unggulan, Indonesia menegaskan identitasnya di tengah pergaulan global tanpa kehilangan akar tradisinya.
Peringatan Hari Pantun Nasional yang diisi dengan lokakarya, lomba cipta pantun, kampanye literasi, dan pertunjukan budaya memiliki nilai edukatif yang signifikan. Namun, secara akademik, peringatan ini perlu diikuti oleh kebijakan berkelanjutan, seperti integrasi pantun dalam kurikulum, penguatan kompetensi guru, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai medium kreatif. Pendekatan ini sejalan dengan teori cultural sustainability, yang menekankan pentingnya adaptasi budaya agar tetap relevan lintas generasi.
Dalam konteks pendidikan formal, guru memegang peran strategis sebagai agen transmisi budaya. Guru tidak hanya menyampaikan teks pantun sebagai materi pelajaran, tetapi juga menghidupkan nilai-nilainya melalui pembelajaran kontekstual. Dengan demikian, pantun tidak diposisikan sebagai peninggalan masa lalu, melainkan sebagai sumber pembelajaran yang hidup dan bermakna.
Pada akhirnya, Hari Pantun Nasional merupakan ruang refleksi kolektif. Ia mengingatkan bahwa bahasa dan sastra bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga penopang peradaban. Pantun mengajarkan kehati-hatian dalam berkata, kedalaman dalam berpikir, dan kebijaksanaan dalam bersikap. Dengan merawat pantun, bangsa Indonesia tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga merawat nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi fondasi kehidupan bersama.
Melalui peringatan setiap 17 Desember, pantun diharapkan terus tumbuh sebagai warisan budaya yang dinamis—hidup dalam tutur, pendidikan, dan praktik sosial—serta mampu menjembatani masa lalu, masa kini, dan masa depan bangsa.***


.jpeg)