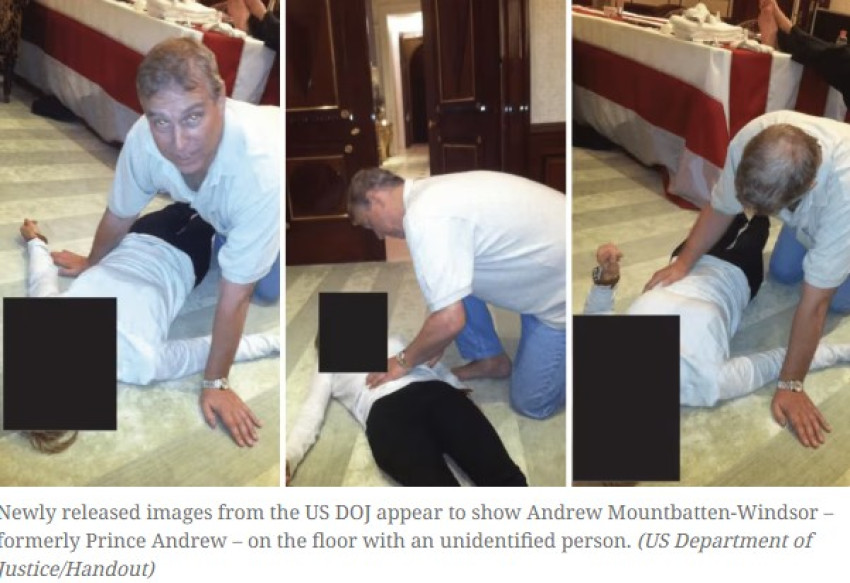Goenawan Mohamad: Surat Terbuka untuk Nadiem Makarim
Oleh Goenawan Mohamad
ORBITINDONESIA.COM - Saya harap surat ini tidak terlalu murung. Tapi jika ada yang terasa tak riang di sini, maafkan, bukan niat saya membebanimu dengan sesuatu yang gelap. Saya memang tak bisa membersihkan diri dari rasa kecewa, bahkan marah, pada keadaan, mengetahui kamu ada dalam tahanan seperti sekarang. Dengan tuduhan "korupsi" pula.
Tapi saya percaya, keadaan ini tak akan menciderai kepercayaan orang banyak kepadamu -- tak akan merusak nama baikmu. Dalam pepatah Jawa ada frase, "becik ketitk, ala ketara". Orang yang bersih dan baik akan tetap kelihatan nilainya, yang jahat demikian juga.
Saya ingat, selalu ingat, ketika suatu senja kamu menemui saya, di tempat minum kopi di hotel yang dulu disebut Hyatt Hotel di Senayan. Kamu baru lulus dari Harvard dan sedang mencari cara untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi Indonesia -- bukan untuk karirmu.
Kamu mengajak saya bertukar fikiran. Saya tak merasa heran bahwa itulah yang kamu fikirkan. Saya mengenalmu sejak sekolah dasar -- dan sangat mengenal orang-orang yang membentuk sikap hidupmu.
Orang-orang itu juga bagian dari proses saya membentuk diri, memilih nilai-nilai dalam hidup. Bapakmu adalah teman dekat saya sejak 1963. Kami -- juga Arief Budiman, Marsillam Simanjuntak, Ismid Hadad, Fikri Jufri, Aristides Katoppo, Rahman Tolleng, Soe Hok Gie -- adalah satu kumpulan.Kami tak selamanya satu ide.
Tapi kami saling percaya, melalui bertahun-tahun "saling asah, saling asih, saling asuh". Juga melalui perlbagai gejolak sejarah, pra-dan-pasca-1965. Kami tak berpartai, tapi kami selalu memihak -- memihak untuk menegakkan Indonesia yang adil, merdeka, cerdas, bersih, kreatif.
Di awal 1960-an, di kamar Bapakmu di Jalan Cikini Raya kami sering bertemu. Malam hari kami ngopi di sebuah kedai Gang Ampiun, berdiskusi, bertukar bacaan. Ketika Bapakmu, Nono Anwar Makarim, menjadi pemimpin redaksi Harian Kami di tahun 1966 (dan dua tahun kemudian, seusai bersekolah di Eropa, saya bergabung)-- kami makin lebih sering bersama. Kami dan sejumlah kawan menjadi penullis dan wartawan. Tapi juga sebagai aktivis, atau dalam istilah yang keren waktu itu, penulis-penulis yang engagé, yang terlibat dalam politik perubahan.
Itu bagian dalam dari komitmen -- kata lain dari rasa cinta -- kami kepada Indonesia -- satu-satunya negeri yang entah bagaimana merasuk ke dalam diri kami sampai dalam (dan tak hanya pada kami).
Persoalan hak asasi dan demokratisasi sangat hangat, genting, dan urgen masa itu. Militer berkuasa hampir di mana-mana, ribuan orang dibunuh atau disingjkirkan atau ditahan, sering hanya karena dugaan, dan pers dikekang. Di masa itu kami praktis berlatih untuk mampu menyintas, mempertahankan dan juga menumbuhkan kemerdekaan besuara, menerobos kekangan itu dengan pelbagai siasat, Di Harian Kami kami memberitakan tindakan-tindalkan yang menindas hak asasi -- misalnya kekerasan, terhadap mereka yang dituduh "terlibat" PKI, Di hari-hari itu Nono berteman dekat sekali dengan H.J.C. Princen dan Adnan Buyung Nasution, pejuang-pejiuag penegak hak asasi. Mereka saling membantu.
Juga dalam menyuarakan antikorupsi. Nono bukan tipe orang yang turun-ke-jalan, tapi melalui tulisan-tulisannya ia membantu perlawanan terhadap kekuasaan permalingan dengan menyoroti penyakit laten Indonesia ini. Dalam sebuah esei di Majalah Kebudayaan Budaya Jaya, yang dikelola Penyair Ramadhan KH, Nono (yang di sana menulis kolom reguler "Kalaeidoskop"), memperkenalkan istilah "kleptokrasi", pemerintahan dan kebijakanaan yang menopang dan menjumbuhkan "pencurian" [harta publik].
Ibu kamu, Atika Makarim, lebih merupakan seorang aktivis: dia membentuk dan terjun secara aktif dalam Yayasan Bung Hatta, lembaga yang didirikan teman-teman yang sepikiran, yang telah beberapa kali memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang diketahui bersih. Di tahun 2013 misalnya, Yayasan ini memberi Hatta Anticorruption Award kepada Ahok.
Bukan sesuatu yang kebetulan, juga bukan sesuatu yang baru, jika ayah ibumu bergabung dengan teman-teman yang prihatin dengan kleptokrasi di Indonesia.
Di akhir tahun 1970-an saya sering mampir dan ikut makan di Jalan Tosari, Jakarta, di rumah Oom Hamid Algadri, kakekmu, ayahanda Ibumu, seorang tokoh Partai Sosialis Indonesia di bawah pimpinan Syahrir. Sebagaimana Soedjatmoko, teman baiknya, Oom Hamid senang berdiskusi dengan generasi yang lebih muda tentang keadaan tanah air.
Dalam salah satu percakapan di meja makan, ia mengutarakan pendapatnya yang tak saya lupakan: di Indonesia kini, dalam bertindak jujur, kata Oom Hamid, mungkin saja kita tak punya patokan hukum. Tapi ada sesuatu yang lebih primordial ketimbang hukum, yakni panggilan ethis. Panggilan ethis inilah yang membuat masyarakat menegakkan dan merawat nilai-nilai. Panggilan ethis, kita tahu, lahir dari pengalaman panjang, bukan hanya sebagai ajaran. Ia tumbuh dari empati kepada orang (terutama yang sebangsa dan setanahair) yang menanggungkan rasa sakit oleh ketidak-adilan.
Dalam sejarah, tak selamanya hukum bertaut dengan panggilan ethis. Bahkan bisa bertentangan. Kapanpun dan di manapun, keadilan tak bisa dialami penuh. Yang kita alami adalah keadilan yang tumbuh, keadilan yang terjadi dari perjuangan bersama.
Dalam hukum -- yang lahir dari proses legislasi -- sering terbuka kemungkinan sengketa, selisih, dengan keadilan. Dalam sejarah Indonesia -- dalam sejarah hukum Indonesia -- sengketa itu berkali-kali terjadi.
Apa yang Nadiem alami sekarang adalah contohnya.
Tak berarti kita menyerahkan diri pada keadaan yang salah ini. Sejarah keadilan adalah cerita Sisiphus: perjuangan yang tak kunjung berhenti, naik turun, jatuh bangun -- tapi yang tak membuat kita putus asa, karena putus asa dalam hal ini akan berarti keruntuhan sosial. Perjuangan itulah yang justru memperkukuh kita sebagai makhluk sosial.
Dan kamu dibentuk, sejak kecil, oleh sekelilingmu, dengan semangat Sisiphus itu.
Jika nanti kamu lepas dari keadaan ini, saya yakin kamu akan memperoleh sebuah tambahan kekayaan batin -- kekayaan yang datang dari kesadaran akan ketidak-adilan dan doorongan kuat ke arah keadilan. Dalam proses itu, tak akan ada yang membuatmu cemar.
Sampai ketemu, Nadiem. Hari-hari ini cuaca buruk. Banyak sekali dari keluarga bangsa kita yang terkena bencana. Tapi itu juga tanda, Indonesia selalu memanggil -- melawan kerusakan alam, melawan bencana rusaknya keadilan.
(Goenawan Mohamad) ***