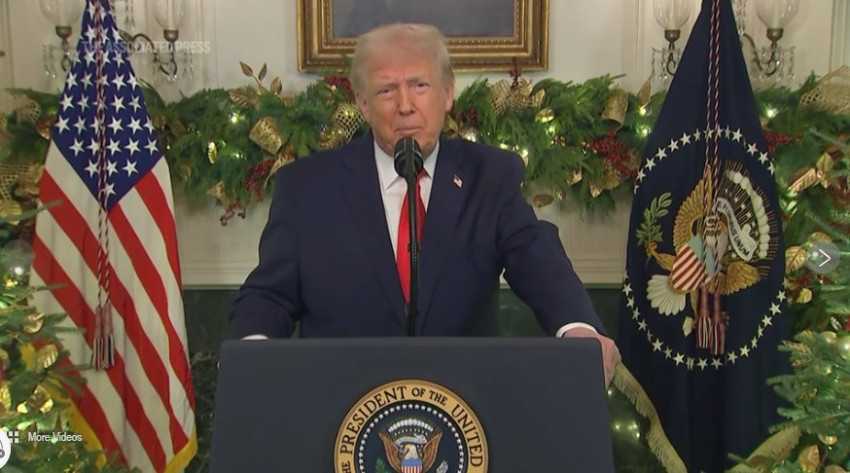Rusaknya Lingkungan Hidup dan Luka Lain
Pengantar dari Denny JA untuk Antologi Buku Puisi Esai “Luka Sejarah Bunga Bangsa”
ORBITINDONESIA.COM - Ada sebuah kisah yang lahir dari laut Maluku Utara. Di Pulau Obi, hujan tak lagi hanya menurunkan air, melainkan darah besi yang meluap dari dinding bukit.
Pada Juni 2025, kolam sedimen tambang nikel pecah, mengalirkan lumpur berwarna merah yang menyapu desa Kawasi, Soligi, dan Wayaloar.
Satu nyawa hilang, puluhan rumah rusak, dan ribuan hidup diselubungi rasa getir dari racun yang tak terlihat.
Puisi “Merah di Pulau Obi” karya Fathan Tibyan Rahman mengabadikan peristiwa itu. Dengan metafora yang menghunjam, ia menulis:
“Para pejabat bicara tentang kemajuan,
Tentang dunia yang butuh nikel untuk baterai.
Lalu siapa yang menghitung harga dari satu rumah yang tenggelam?
Dari satu kehidupan yang hilang?”
Kutipan ini mengguncang kesadaran kita. Logam yang menyilaukan layar ponsel dan mesin mobil listrik, di desa-desa itu berubah menjadi racun di lidah anak-anak.
Di situlah ironi paling telanjang: dunia menyalakan masa depan dengan listrik hijau. Sementara di halaman rakyat kecil masa depan mereka padam dilumat lumpur merah.
-000-
Kerusakan lingkungan bukan sekadar catatan ilmiah. Ia adalah cerita tentang keluarga yang kehilangan sawah.
Ia juga tentang nelayan yang pulang dengan jaring kosong, tentang ibu-ibu yang mendekap anak sakit karena air minum terkontaminasi.
Alam yang seharusnya menjadi ibu, kini dijadikan mesin produksi yang diperas habis.
Tiga luka paling parah dari penambangan nikel adalah:
1. Ekologis permanen: hutan hilang, tanah tandus, sungai beracun.
2. Sosial: masyarakat adat terusir, anak-anak tumbuh dalam trauma.
3. Spiritual: relasi sakral manusia dengan alam berubah jadi relasi transaksional.
Dan mengapa penambang tetap tak peduli? Karena keuntungan dianggap lebih nyata ketimbang penderitaan.
Karena regulasi longgar, pengawasan lemah, dan suara rakyat kalah nyaring dibandingkan narasi “kemajuan”.
Karena dunia seolah menerima logika palsu: bahwa menghancurkan satu desa dibenarkan demi menyelamatkan jutaan mobil listrik.
-000-
Pulau Obi di Maluku Utara hanyalah satu bab dalam kitab luka global. Di pulau lain, Sulawesi, laut Morowali kini keruh dan padang lamun musnah.
Di Ambatovy, Madagaskar, tambang nikel mencabik hutan hujan tropis dan meracuni sungai.
Di Surigao del Norte, Filipina, tanah berubah merah oleh danau asam, sawah terbenam lumpur, dan masyarakat kehilangan air bersih.
Inilah paradoks zaman: transisi energi hijau ditulis dengan tinta merah darah dan lumpur.
Sejarah sastra dunia pun menyimpan jeritan yang sama.
Sejak 200 tahun lalu, para penyair sudah mengekspresikan kegelisahanmya atas keagungan alam yang dirusak oleh bisnis.
Sejak abad ke-19, William Wordsworth sudah menuliskan jeritan bumi lewat puisinya “The World Is Too Much With Us.” Ia melihat manusia kian sibuk mengejar materi hingga kehilangan hubungan sakral dengan alam.
“Kita hanya sibuk mengeruk alam dan menghancurkannya.
Sedikit sekali yang kita lihat dari Alam sebagai ibu kita;
kita telah menyerahkan hati kita, sebuah anugerah yang tercemar.”
Bait itu lahir dari keresahan seorang penyair Romantik di Inggris: industrialisasi memisahkan manusia dari tanah yang memberinya hidup.
Luka yang digambarkan Wordsworth adalah luka spiritual—alienasi, keterasingan, kehilangan rasa suci terhadap bumi.
Dua abad kemudian, jeritan itu menemukan gaungnya di Maluku Utara. Fathan Tibyan Rahman menulis “Merah di Pulau Obi”, sebuah puisi esai yang lahir dari tragedi nyata: kolam limbah tambang nikel meluap, merendam desa-desa dengan air merah bercampur racun.
“Para pejabat bicara tentang kemajuan,
tentang dunia yang butuh nikel untuk baterai.
Lalu siapa yang menghitung harga dari satu rumah yang tenggelam?
Dari satu kehidupan yang hilang?”
Jika Wordsworth bicara kehilangan spiritual, Rahman menghadirkan luka fisik: rumah tenggelam, tanah mati, nyawa hilang.
Namun keduanya menyuarakan satu pesan: kemajuan yang mengabaikan alam hanyalah ilusi.
Wordsworth menulis ketika mesin pabrik baru berdengung. Rahman menulis ketika dunia memuja energi hijau, tetapi menutup mata pada desa-desa yang dikubur lumpur merah.
Keduanya adalah dua wajah dari satu kebenaran: bila manusia lupa menjaga bumi, maka bumi akan menagih. Dan harga itu, entah dalam bentuk keterasingan batin atau banjir racun, selalu lebih mahal daripada yang kita bayangkan.
-000-
Puisi di atas hanya salah satu saja dari kumpulan puisi esai. Tapi buku ini bukan sekadar kumpulan puisi. Ia adalah peta luka bangsa yang dijahit dengan kata-kata.
Lebih dari 20 penulis ikut menyumbangkan suara: ada penyair, guru, akademisi, hingga mahasiswa.
Mereka menulis tentang luka politik 1965, tentang perempuan yang diperkosa perang, tentang kolonialisme yang masih membekas, tentang anak-anak yang menjadi korban intoleransi, dan tentang bumi yang dikoyak tambang.
Lima tema besar menjahit keseluruhan buku:
1. Luka politik dan kekerasan negara.
2. Warisan kolonialisme.
3. Kerusakan lingkungan.
4. Perempuan dan perlawanan.
5. Identitas dan kebangsaan.
Kekuatan buku ini ada pada bentuk puisi esai—mengawinkan lirisisme puisi dengan analisis esai, menghadirkan karya yang indah sekaligus informatif.
Ia juga kaya perspektif, sebab tiap penulis membawa pengalaman berbeda. Lebih jauh, buku ini berfungsi sebagai dokumen kultural: arsip luka kolektif yang jarang diangkat oleh catatan resmi.
-000-
Membaca buku ini ibarat memasuki taman yang aneh: bunganya mekar, tapi tumbuh dari tanah yang berdarah.
Namun justru di situlah letak keindahannya. Luka yang ditulis di sini bukan untuk meratapi semata, melainkan untuk mengingatkan.
Bangsa hanya bisa tumbuh dewasa bila berani melihat lukanya sendiri. Alam hanya bisa dipulihkan bila manusia jujur pada kerusakan yang ia timbulkan. Puisi hanya bisa menjadi cahaya bila ia berani menyingkap gelap.
Luka Sejarah Bunga Bangsa adalah ajakan: jangan biarkan luka-luka ini dilupakan. Jadikan ia bunga—rapuh tapi indah—yang mekar dari penderitaan.
Karena bangsa tanpa ingatan hanyalah rumah tanpa pondasi, dan dunia tanpa keadilan lingkungan hanyalah peradaban yang berjalan menuju runtuh.***
Jakarta, 19 Agustus 2025
Referensi
Rob Nixon. Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. Harvard University Press, 2011.
-000-
Ratusan esai Denny JA soal filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, politik demokrasi, sejarah, positive psychology, catatan perjalanan, review buku, film dan lagu, bisa dilihat di FaceBook Denny JA’s World
https://www.facebook.com/share/p/1AzyWj5szE/?mibextid=wwXIfr