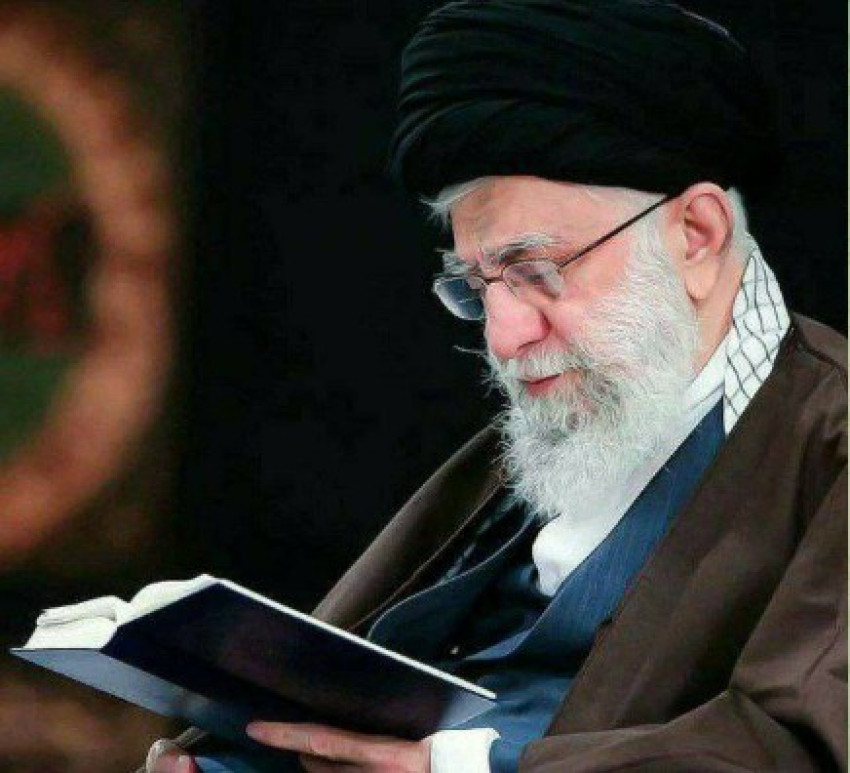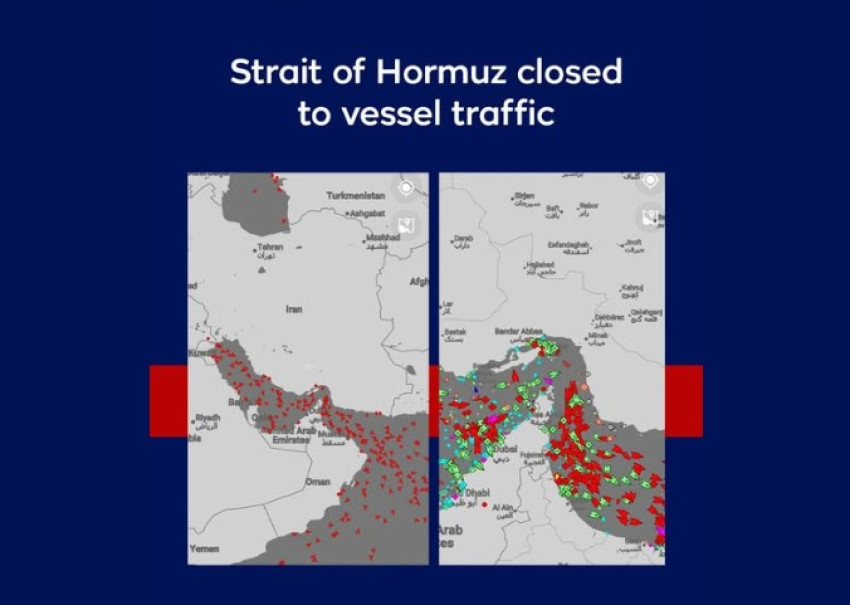Catatan Denny JA: Mendengar 9 Points Rektor UGM dan Kisah Politik Ijazah Jokowi
Oleh Denny JA
ORBITINDONESIA.COM - Perdebatan ijazah Jokowi bukan tentang ijazah. Ini tentang kita: tentang siapa yang kita percaya, bagaimana kita cemas, dan betapa mudahnya rumor mengalahkan bukti
Ada perdebatan yang lahir dari kebijakan publik. Ada perdebatan yang berangkat dari perbedaan ideologis.
Tetapi ada pula perdebatan yang lahir dari sesuatu yang jauh lebih sunyi: sebuah keraguan yang dibiarkan tumbuh terlalu lama.
Selama beberapa tahun terakhir, isu ijazah Presiden Joko Widodo telah membelah obrolan masyarakat seperti belahan kayu yang tak selesai ditebang.
Di teras rumah, di ruang rapat kantor, di layar ponsel yang tidak pernah tidur, nama Jokowi bersanding dengan kata “ijazah” seperti bayang-bayang yang menolak pergi.
Di satu sisi, ada yang merasa persoalan ini hanyalah riak kecil yang dibesar-besarkan.
Di sisi lain, ada pula yang menuntut bukti meyakinkan, seolah sebuah kebenaran baru sah jika datang dalam kemasan yang spektakuler.
Dalam kebisingan itu, sebuah suara akademik hadir.
Ini bukan teriakan, bukan klaim partisan, bukan propaganda.
Ini adalah suara seorang rektor yang berbicara atas nama institusi yang mengeluarkan ijazah itu sendiri: Universitas Gadjah Mada.
Rektor UGM, Ova Emilia, menyampaikan sembilan poin klarifikasi. Saya mendengarkannya penuh di Kompas TV, 28 November 2025.
Saya menyimak poin-poin itu bukan hanya sebagai dokumen administrasi, tetapi sebagai upaya sebuah universitas untuk mengembalikan percakapan kepada akarnya: bukti dan nalar.
-000-
Berikut saya kutip dan ringkas sembilan poin tersebut apa adanya, lalu saya berikan renungan manusiawinya.
1. “UGM menerima mahasiswa yang bernama Joko Widodo dan terdaftar pertama kali tanggal 28 Juli 1980… Pengumuman tersebut dapat dilihat di koran Kedaulatan Rakyat 18 Juli 1980.”
2. “Joko Widodo menjalani proses registrasi sebagaimana seharusnya… Data didokumentasikan dalam buku induk angkatan 1980.”
3. “Joko Widodo menjalani kuliah di Fakultas Kehutanan… dengan dosen pembimbing Bapak Kasmujo.”
4. “Pada tahun 1983 Joko Widodo menyelesaikan evaluasi program sarjana muda… yang kemudian disatukan menjadi program sarjana.”
5. “Joko Widodo menyelesaikan skripsi di bawah bimbingan Bapak Ahmad Sumitro… Ejaan Soemitro dan Sumitro keduanya sah.”
6. “Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5.”
7. “Joko Widodo telah menerima ijazah asli… Keputusan menunjukkan kepada publik atau tidak menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.”
8. “Yang dilarang pada masa itu adalah foto dengan kacamata hitam… UGM memiliki arsip ijazah lain dengan foto berkacamata.”
9. “Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggung jawab UGM dan tidak untuk membela satu pihak pun secara tidak proporsional.”
-000-
Pada akhirnya, sembilan poin dari Rektor UGM ini bukan sekadar daftar klarifikasi.
Ia adalah pernyataan resmi dari satu-satunya institusi yang berwenang mengesahkan ijazah itu.
Dalam dunia akademik, suara universitas adalah saksi paling sahih. Seandainya hidup berjalan sepenuhnya dengan nalar, perdebatan berhenti di sini.
Namun manusia tidak hidup hanya dari nalar, melainkan juga dari prasangka, kecemasan, dan identitas kelompok.
Di titik inilah pertanyaan yang lebih dalam muncul. Mengapa pro dan kontra keaslian ijazah Jokowi begitu marak, seolah menjadi ritual politik yang tidak pernah benar-benar usai?
Jawabannya tidak sesederhana dokumen akademik. Ini adalah kisah tentang psikologi sosial, krisis kepercayaan, dinamika identitas, dan budaya rumor yang berkembang dalam ekosistem digital kita.
Setidaknya ada empat hal yang dapat terbaca dari hiruk-pikuk ini.
-000-
Pertama. Rendahnya kepercayaan sebagian publik terhadap institusi, bahkan yang setua dan sekuat UGM.
Di balik keraguan itu, terdapat sejarah panjang kekecewaan terhadap institusi negara, partai politik, media, dan lembaga-lembaga formal lainnya. Rasa kecewa itu kemudian merembet ke universitas.
Sebagian publik berkata dalam hati: “Jika lembaga lain dapat dipengaruhi kekuasaan, mengapa universitas tidak?”
Dalam suasana psikologis seperti ini, klarifikasi institusi bukan lagi pembawa terang, tetapi justru memantik curiga.
Suara rektor tidak lagi berdiri sebagai suara ilmu, tetapi dibaca sebagai suara kekuasaan.
Padahal dalam logika akademik, arsip dan buku induk jauh lebih jujur daripada rumor.
Namun ketika kepercayaan publik telah terkikis, bahkan kebenaran yang paling sederhana pun harus berjuang keras menembus kabut prasangka.
Sebagaimana dijelaskan Francis Fukuyama, masyarakat hanya bisa bekerja dengan sehat jika kepercayaan menjadi jaring halus yang menyatukan warganya.
Ketika trust runtuh, masyarakat memasuki fase “low-trust equilibrium” di mana klarifikasi apa pun dianggap mencurigakan.
Di ruang seperti itu, kebenaran tidak lagi ditentukan oleh bukti, tetapi oleh siapa yang dipercaya. Fenomena ini sangat terasa dalam polemik ijazah Jokowi.
Di titik ini, tugas warga negara bukan hanya memelototi dokumen, tetapi juga merawat ekosistem kepercayaan: menguji klaim dengan skeptis, namun tetap mengakui otoritas pengetahuan yang bekerja dengan standar verifikasi.
-000-
Kedua. Sikap Jokowi yang memilih tidak menunjukkan ijazahnya dalam panggung publik melahirkan ruang untuk spekulasi.
Sebagian orang menilai Jokowi sekadar menjaga hak privasinya. Tidak semua yang diminta publik harus ditaruh di meja.
Namun bagi sebagian lainnya, diam terbaca sebagai tanda bahwa ada yang disembunyikan.
Dalam politik modern, diam dapat berubah menjadi narasi.
Ketika tokoh publik memilih tidak menari dalam irama tuduhan, ruang kosong itu segera diisi oleh tafsir dan rumor.
Nama Jokowi terus bergema.
Dipuji, dikritik, diserang, dibela, dijadikan simbol harapan, dijadikan simbol kekecewaan.
Apakah ia memanfaatkan kebisingan itu?
Atau justru lelah meladeni?
Sejarah yang kelak menilai.
Yang jelas, sikap yang tidak meladeni membuat isu ini bertahan lebih lama daripada yang seharusnya.
-000-
Ketiga. Bagi sebagian kelompok kontra, isu ijazah menjadi identitas, bukan sekadar isu administratif.
Bagi mereka, memeriksa ijazah adalah “hak publik.”
Pada dasarnya itu benar.
Tetapi dalam praktiknya, isu ini telah berubah menjadi bendera kelompok.
Menjadi bagian dari gerakan “pembongkar ijazah” berarti merasa lebih kritis, lebih waspada, lebih moral dibanding kelompok lain.
Pada titik ini, klarifikasi UGM bukan lagi informasi, tetapi ancaman bagi narasi kelompok.
Karena menerima pernyataan UGM berarti membongkar identitas yang telah lama dipegang.
Betapa pun lengkapnya bukti, sebagian akan tetap bertahan.
Bukan karena bukti kurang, tetapi karena narasi ijazah palsu sudah menjadi rumah batin.
-000-
Keempat. Narasi bahwa ijazah Jokowi asli tetapi “hilang”, sementara yang beredar adalah salinan yang cacat secara teknis.
Narasi ini tumbuh subur di era digital. Perbedaan kecil dalam kualitas scan, tanda tangan, atau format dianggap bukti adanya kejanggalan.
Padahal secara administratif, dokumen publik sering kali adalah salinan yang melewati banyak tahap.
Namun di ruang digital, celah sekecil apa pun dapat menjadi pintu bagi imajinasi liar.
Cass Sunstein menjelaskan bahwa rumor tumbuh bukan karena bukti, tetapi karena kebutuhan psikologis untuk menemukan pola.
Dalam masyarakat yang terpolarisasi, rumor memenuhi ruang kosong yang ditinggalkan oleh ketidakpastian.
Semakin kabur dokumennya, semakin mudah rumor menempel. Dan semakin kuat identitas kelompok, semakin sulit rumor itu dipatahkan bahan dengan data sahih sekalipun.
-000-
Lalu bagaimana isu ini terbaca di mata publik yang lebih luas?
Survei opini publik menunjukkan pola yang menarik. Di tingkat akar rumput, mayoritas warga tidak percaya bahwa ijazah Jokowi palsu.
Popularitasnya sebagai mantan presiden tetap tinggi.
Ia masih menempati posisi teratas di antara para pemimpin yang pernah memimpin republik ini.
Artinya ada kesenjangan besar antara dua dunia.
Pertama, dunia aktivis dan kelompok kontra yang sangat berisik di ruang digital.
Kedua, dunia mayoritas diam yang melihat isu ini dengan kejenuhan, bukan amarah.
Pro dan kontra ijazah Jokowi menjadi cermin wajah kita hari ini.
Cermin tentang bagaimana kita memperlakukan bukti.
Cermin tentang bagaimana kita memercayai atau mencurigai institusi.
Cermin tentang bagaimana politik berubah menjadi identitas.
Skeptisisme tetap perlu, tetapi keberatan yang sah selalu berdiri di atas bukti, bukan gema kecurigaan yang diulang-ulang.
Kebenaran tidak mati.
Kadang ia hanya tertutup oleh bisingnya opini.
Pada akhirnya, sejarah berpihak pada mereka yang menyimpan dokumentasi,
dan pada masyarakat yang berani berpihak pada bukti,
bahkan ketika bukti itu tidak selaras dengan prasangka mereka sendiri.
Ijazah Jokowi pun, pada titik tertentu, berhenti menjadi dokumen akademik. Ia berubah menjadi ujian kedewasaan budaya kewargaan.
Sejauh mana publik sanggup menempatkan bukti di atas agitasi dan permainan politik.*
Jakarta, 29 November 2025
Referensi
1. Francis Fukuyama, Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity (1995).
2. Cass R. Sunstein, On Rumors: How Falsehoods Spread, Why We Believe Them, and What Can Be Done (2009).
-000–
Ratusan esai Denny JA soal filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, politik demokrasi, sejarah, positive psychology, catatan perjalanan, review buku, film dan lagu, bisa dilihat di FaceBook Denny JA’s World
https://www.facebook.com/share/p/17oGdKvAu2/?mibextid=wwXIfr