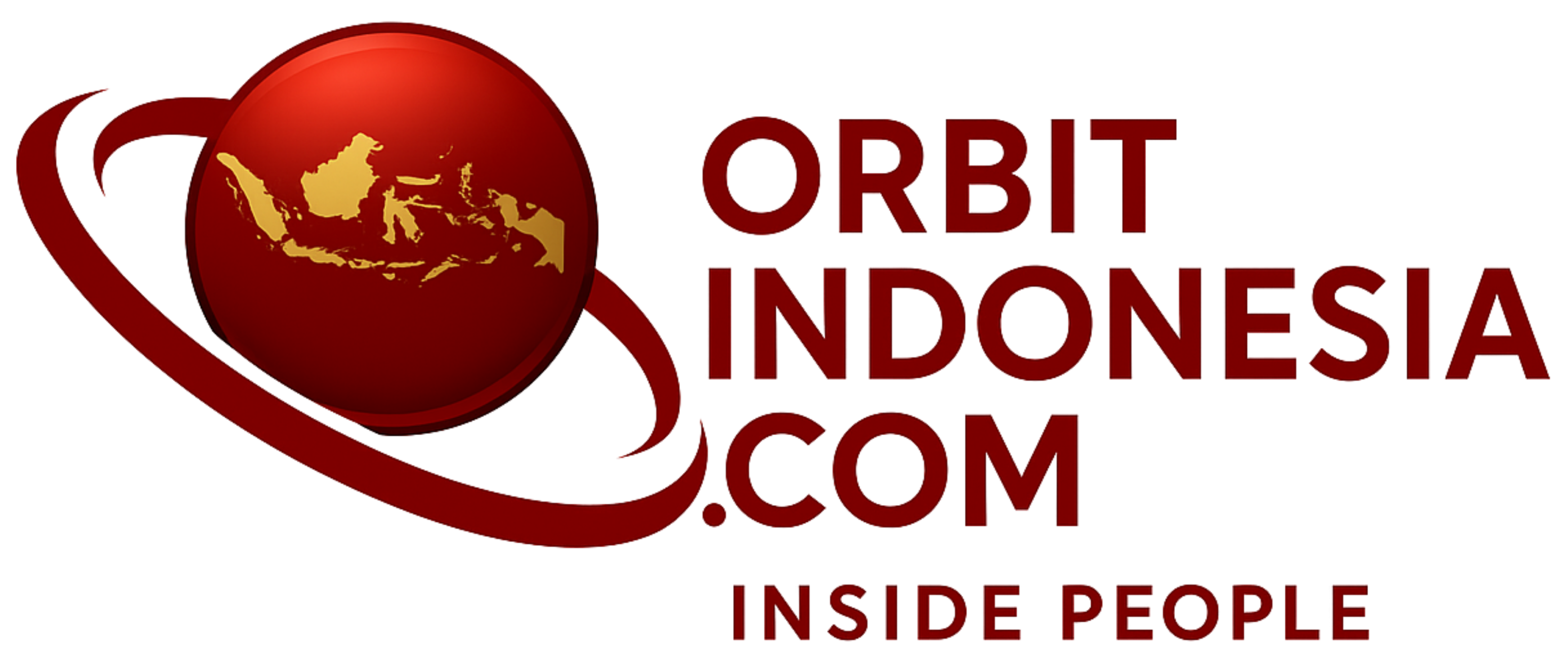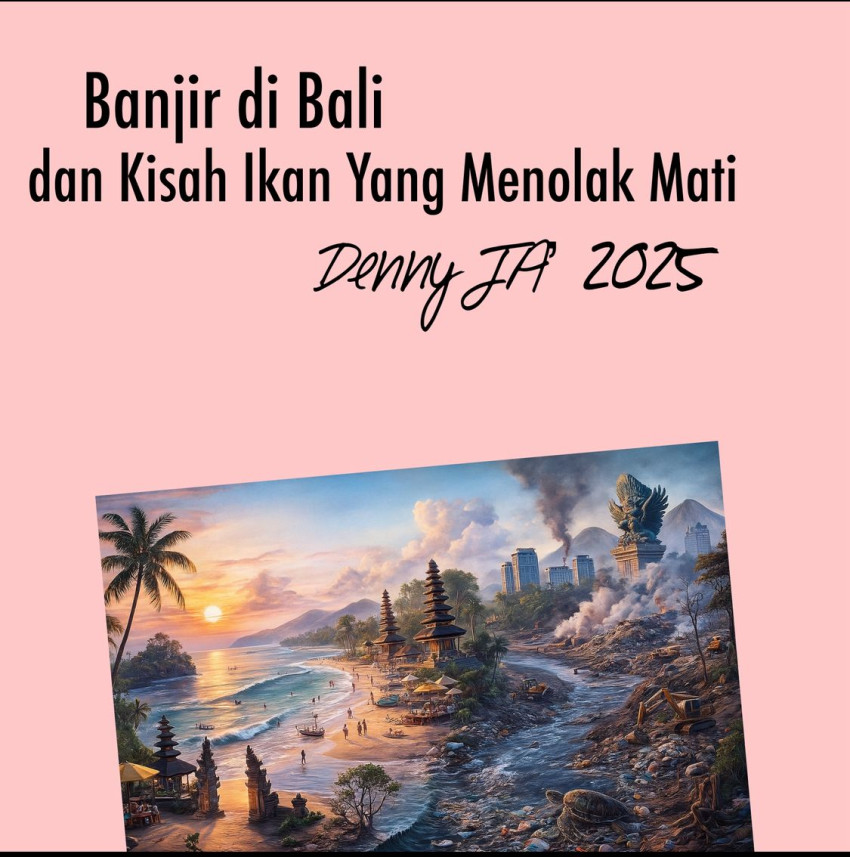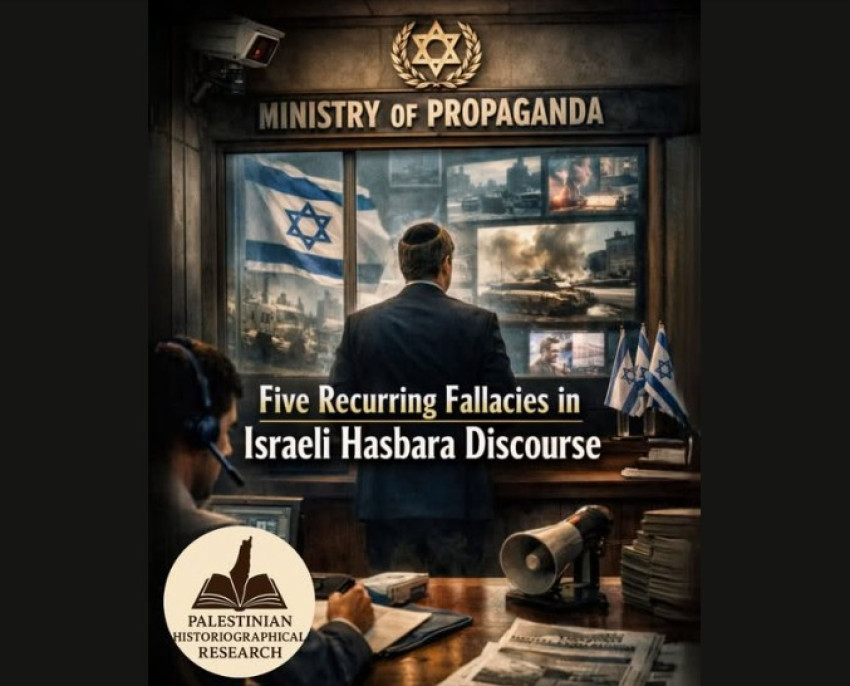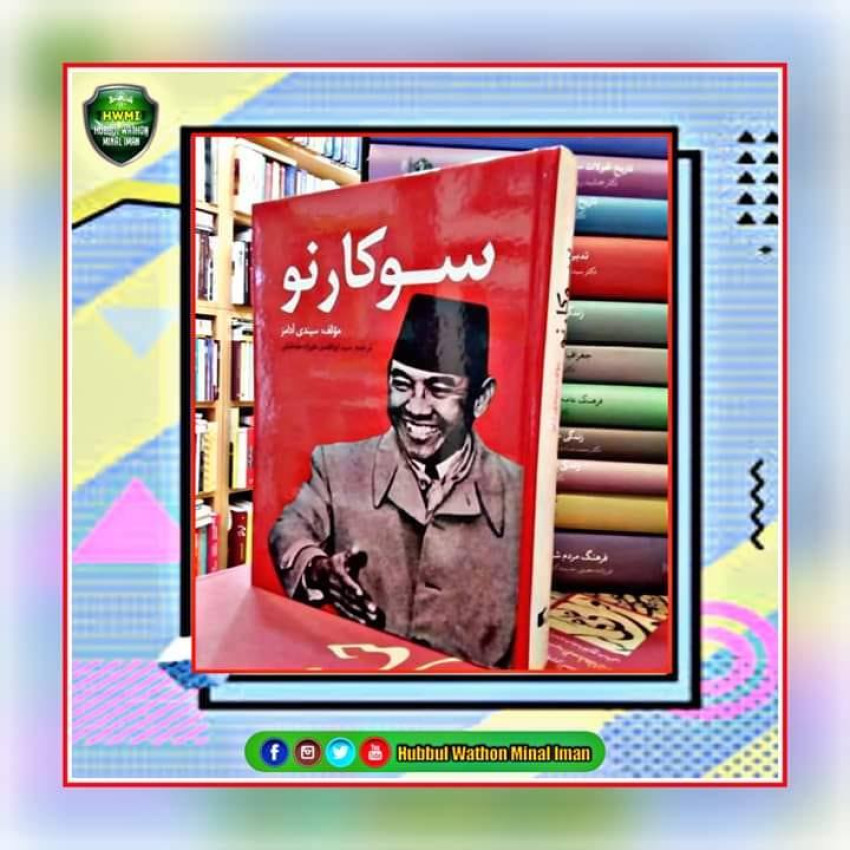Catatan Denny JA: Banjir di Bali dan Kisah Seekor Ikan yang Menolak Mati
- Pengantar untuk Buku Banjir Pagerwesi karya Wayan Suyadnya
Oleh Denny JA
ORBITINDONESIA.COM - Ikan itu ditemukan pada hari keenam. Lumpur banjir mulai mengering dan rumah masih seperti luka yang menganga.
Seekor gabus kecil, hitam, legam, nyaris tak bersuara, meloncat dari gumpalan tanah yang retak.
Enam hari ia terperangkap. Enam hari tanpa air. Enam hari tanpa makanan. Enam hari tanpa cahaya. Namun ia hidup.
Anak-anak bersorak. Penulisnya tertegun. Dan saya, ketika membaca kisah itu, merasakan sesuatu yang metaforis: betapa sebuah makhluk kecil dapat menjadi guru besar.
Ikan itu mestinya sudah mati.
Jika masih hidup, ia hidup untuk menjadi tanda.
Ketika satu wilayah di Bali tenggelam, kehidupan kecil yang berserah kepada alam justru menolak mati.
Ikan itu adalah lambang Bali sendiri. Pulau ini berulang kali disakiti oleh pembangunan yang tak terkendali, oleh banjir yang datang seperti amarah, oleh manusia yang lupa pada akar spiritualnya.
Namun Bali, seperti gabus itu, masih hidup, meski tubuhnya remuk, meski alamnya menjerit, meski ekosistemnya menipis.
Ikan yang menolak mati itu adalah simbol keteguhan; pesan kecil dari semesta. Bahwa hidup selalu mencari caranya sendiri untuk bertahan.
Harapan, betapapun kecil, selalu mampu melompat dari lumpur.
-000-
Buku Banjir Pagerwesi membentangkan cermin yang tak nyaman: Bali yang sering disebut surga dunia sedang runtuh dari dalam.
Secara ekologis, penulis buku ini menggambarkan betapa hutan resapan Tukad Ayung kini tinggal 3% saja.
Itu sebuah data yang disebut berulang di berbagainhalaman buku ini. Sungai yang dulu jernih kini menjadi saluran sampah. Hutan ditebang untuk vila. Gunung digali demi properti. Mangrove disertifikatkan.
Secara spiritual, Bali jatuh dalam paradoks: upacara sakral semakin sering, tetapi relasi manusia dengan alam semakin dangkal.
Tri Hita Karana dipasang di dinding hotel, tetapi tidak lagi hidup dalam tindakan. Tat Twam Asi dilisankan, namun alam yang “engkau” itu dikhianati.
Secara pariwisata, pulau kecil ini memikul beban global: pariwisata berlimpah, anggaran pemerintah daerah naik, namun tanah hilang, budaya tergerus, dan orang Bali semakin tersingkir dari pulau yang mereka sucikan.
Hal-hal ini diperlihatkan dengan jelas dalam bab “Politik Ruang dan Raja-Raja Kecil” dan bab “Pariwisata dan Kehilangan Identitas Bali” dalam buku ini.
Penulis buku, Wayan Suyadnya adalah jurnalis senior Bali. Ia Koordinator Satupena Bali–NTB–NTT, dan Komisioner KPID Bali.
Latar belakangnya membuat buku ini tidak hanya emosional, tetapi juga investigatif, faktual, dan penuh keberanian.
Intisari buku ini sederhana namun menyayat: Bali dipuji sebagai surga, tetapi diperlakukan sebagai pasar.
Alamnya disembah dalam ritual, tetapi dijarah dalam kebijakan.
-000-
Bali bukan satu-satunya tempat indah yang mengusung paradoks antara kemegahan pariwisata dan keruntuhan ekologis.
Lihatlah Venesia, Italia. Kota terapung yang kini tenggelam perlahan. Tidak hanya sesekali, tetapi setiap tahun—terutama ketika fenomena acqua alta (air laut pasang) menenggelamkan Piazza San Marco.
Dalam 20–30 tahun terakhir, Venesia telah ditinggalkan ribuan penduduk, dan UNESCO bahkan pernah mempertimbangkan memasukkannya ke daftar situs warisan dunia yang “terancam punah”.
Penyebabnya serupa dengan Bali:
• wisata massal,
• kenaikan permukaan laut,
• hilangnya ruang-ruang resapan air,
• pembangunan yang mengabaikan daya dukung ekosistem.
Seperti Bali, Venesia adalah keajaiban dunia; cantik di permukaan, rapuh di fondasi. Dan jika Venesia adalah contoh masa depan, maka Bali sedang berjalan ke arah yang sama—kecuali jika kita belajar dari kota yang perlahan ditelan air itu.
-000-
Mengapa Buku Ini Penting? Tiga Hal Pokok
1. Ia menjahit ekologi dan spiritualitas dalam satu napas.
Penulis tidak hanya bicara drainase atau alih fungsi lahan. Ia menafsirkan banjir sebagai bahasa Tuhan.
Ia membaca air sebagai aksara, pohon sebagai kitab, dan bencana sebagai pesan semesta. Ini perspektif yang langka dan berharga dalam diskursus lingkungan Indonesia.
2. Buku ini mengembalikan Bali ke akarnya: Tri Hita Karana, Tat Twam Asi, dan Bhisama Batur Kalawasan.
Ia mengajak pembaca kembali pada ajaran leluhur—bukan dengan cara mistik, tetapi dengan bahasa ekologis:
Jika alam adalah tubuh Bali, maka melukai alam adalah melukai diri sendiri.
3. Ia menawarkan arah kebijakan masa depan: One Island, One Management.
Gagasan besar ini muncul berulang kali di buku. Tanpa tata kelola satu pulau, Bali akan terus dikuasai “raja-raja kecil”—kabupaten yang tarik-menarik kepentingan.
Sementara sungai mengalir bebas tanpa peduli garis administrasi.
Inilah buku yang bukan sekadar duka seorang penyintas banjir.
Ini adalah manifesto ekologis–spiritual untuk Bali seratus tahun ke depan.
-000-
Kembali pada kisah ikan gabus kecil itu, ikan yang menolak mati di awal pengantar ini.
Ikan itu tidak memiliki kekuatan politik, tidak memiliki suara, tidak memiliki proyek, tidak memiliki ritual. Ia hanya memiliki insting untuk hidup, dan ketundukan total pada hukum alam.
Bali pun bisa begitu.
Jika ia kembali pada ajaran leluhur, kembali pada kesadaran, kembali pada hormat kepada air dan tanah, maka Bali akan menolak mati.
Ini terjadi meskipun dunia menekan Bali, meskipun pariwisata mencekiknya, meskipun banjir berulang-ulang mencoba menenggelamkannya.
Sebab yang membuat sebuah pulau bertahan bukan anggaran daerah, bukan vila mewah, bukan branding global.
Yang membuat sebuah pulau bertahan adalah:
Kesadaran ekologis.
Kesetiaan pada leluhur.
Cinta pada bumi tempat ia dilahirkan.
Semoga buku ini menjadi cahaya kecil yang menyala di tengah gelapnya ketidakpedulian banyak orang.
Semoga ia menjadi panggilan untuk kembali eling, ingat, bahwa hidup bukan hanya untuk diisi, tetapi untuk dijaga.
Dan semoga Bali, seperti gabus kecil itu, akan terus memilih untuk hidup.
Agar pulau ini tidak hanya indah hari ini, tetapi tetap suci seratus tahun dari sekarang. *
Jakarta, 22 November 2025
Referensi
1. Amitav Ghosh, The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable, University of Chicago Press, 2016.
2. Bill McKibben, The End of Nature, Random House, 1989.
-000-
Ratusan esai Denny JA soal filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, politik demokrasi, sejarah, positive psychology, catatan perjalanan, review buku, film dan lagu, bisa dilihat di FaceBook Denny JA’s World
https://www.facebook.com/share/p/1GJJCfwh5c/?mibextid=wwXIfr