Satrio Arismunandar: Amerika Serikat dan Imperialisme Gaya Baru Abad ke-21
Oleh Satrio Arismunandar
ORBITINDONESIA.COM - Bayangkan sebuah dunia di mana seorang presiden negara berdaulat bisa “ditangkap” dan diterbangkan keluar negerinya sendiri oleh kekuatan asing—tanpa perang, tanpa mandat internasional, tanpa pengadilan global. Dunia itu terdengar seperti kisah fiksi politik. Namun justru di situlah kegelisahan abad ini bermula.
Belakangan, beredar berita di media internasional tentang Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington telah menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro setelah operasi besar-besaran di negara Amerika Selatan tersebut.
Hal ini membuka pertanyaan yang jauh lebih besar dan relevan: Apakah tindakan militer AS ini layak disebut imperialisme? Jawabannya, bagi banyak pengamat politik global, nyaris tak terbantahkan: ya.
Imperialisme Tak Harus Menduduki Wilayah
Imperialisme abad ke-21 tidak lagi selalu hadir dengan pendudukan wilayah, seperti yang dilakukan kekuatan kolonial Eropa ratusan tahun lalu. Hari ini, imperialisme sering tampil lebih halus—namun dampaknya sama dalam: mengendalikan arah politik negara lain.
Amerika Serikat, sebagai kekuatan global terbesar pasca-Perang Dingin, kerap dituding mempraktikkan imperialisme versi baru. Bukan lewat penjajahan formal, melainkan melalui sanksi ekonomi, tekanan diplomatik, intervensi politik, dan operasi keamanan lintas batas. Semua ini sering dibungkus dalam bahasa mulia: demokrasi, stabilitas, atau keamanan global.
Dalam konteks Venezuela, Washington selama bertahun-tahun menolak mengakui legitimasi Nicolás Maduro. Sanksi dijatuhkan, aset negara dibekukan, oposisi didukung secara terbuka. Venezuela, di bawah kepemimpinan sayap kiri sejak era Hugo Chávez, telah lama menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi AS di Amerika Latin.
Menculik Presiden Negara Lain: Garis Merah Kedaulatan
Jika sebuah negara benar-benar menculik kepala negara lain tanpa deklarasi perang dan tanpa keputusan pengadilan internasional, itu bukan lagi sekadar intervensi—melainkan penghancuran total atas prinsip kedaulatan.
Dalam hukum internasional, presiden bukan sekadar individu. Ia adalah simbol negara. Menyentuhnya dengan kekuatan militer asing berarti menyentuh fondasi tatanan global yang dibangun pasca-Perang Dunia II: bahwa semua negara, besar atau kecil, setara secara hukum.
Alasan apa pun—narkotika, terorisme, atau demokrasi—tidak menghapus fakta bahwa tindakan semacam itu akan menjadikan hukum internasional tunduk pada kekuatan senjata. Inilah esensi imperialisme: hak sepihak untuk menentukan nasib bangsa lain.
Trumpisme dan Kekuasaan yang Terang-Terangan
Donald Trump dikenal dengan pendekatan “America First” yang menempatkan kepentingan AS di atas aturan global. Dalam logika ini, institusi internasional sering dianggap penghambat, bukan penjaga keseimbangan dunia.
Berbeda dari era sebelumnya yang lebih berhati-hati secara diplomatik, Trumpisme menghadirkan wajah kekuasaan yang lebih terbuka, bahkan kasar. Dunia diperlakukan sebagai arena transaksi dan tekanan. Bagi banyak negara berkembang, pendekatan ini memunculkan kembali trauma lama: bahwa hukum hanya berlaku bagi yang lemah.
Jika penangkapan Maduro itu dianggap wajar, maka tidak ada lagi jaminan keamanan bagi negara mana pun.
Hari ini Venezuela. Besok bisa negara lain—selama dianggap mengganggu kepentingan kekuatan besar (baca: Amerika Serikat).
Di titik inilah perdebatan tentang imperialisme menjadi relevan kembali. Bukan sebagai konsep usang dari buku sejarah, melainkan sebagai realitas yang berubah bentuk. Imperialisme kini tidak selalu menancapkan bendera, tetapi menancapkan kehendak.
Hukum Internasional
Imperialisme abad ini tidak selalu datang dengan dentuman meriam. Ia bisa hadir dalam senyap: lewat tekanan ekonomi, delegitimasi politik, dan klaim moral sepihak. Namun ketika garis kedaulatan dilanggar—apalagi dengan menculik pemimpin negara lain—imperialisme itu tampil tanpa topeng.
Dunia kini dihadapkan pada pilihan mendasar: apakah hukum internasional masih menjadi pagar bersama, atau hanya hiasan yang bisa disingkirkan oleh mereka yang paling kuat?
Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan seperti apa wajah dunia di masa depan.
*Satrio Arismunandar, penulis buku, wartawan, Sekjen Perkumpulan Penulis Indonesia SATUPENA. ***





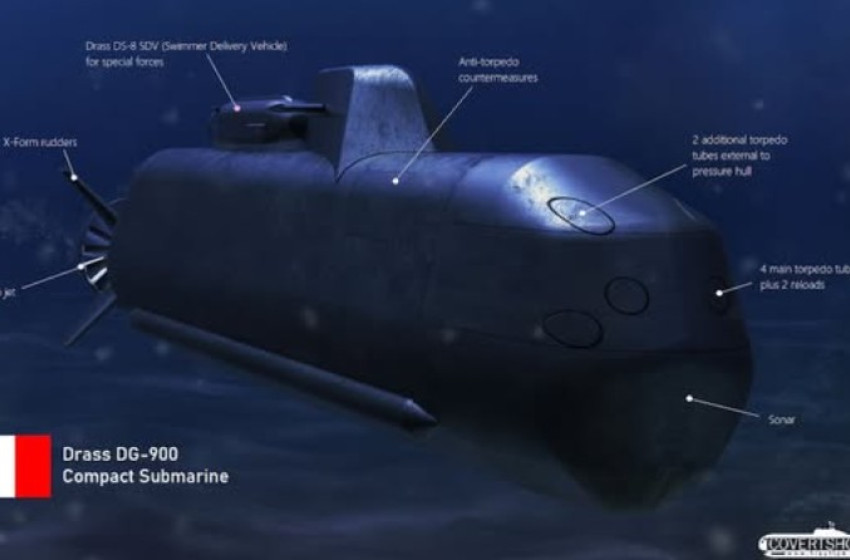



.jpeg)


