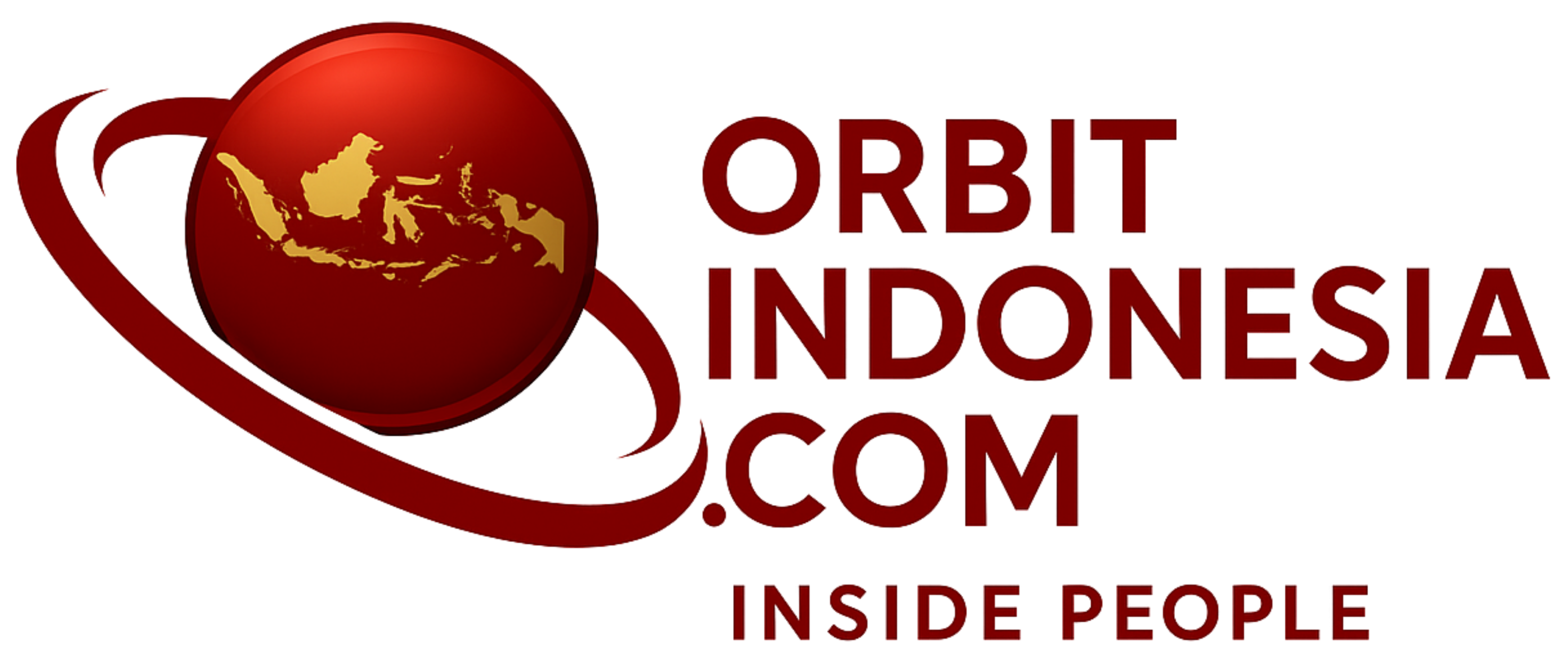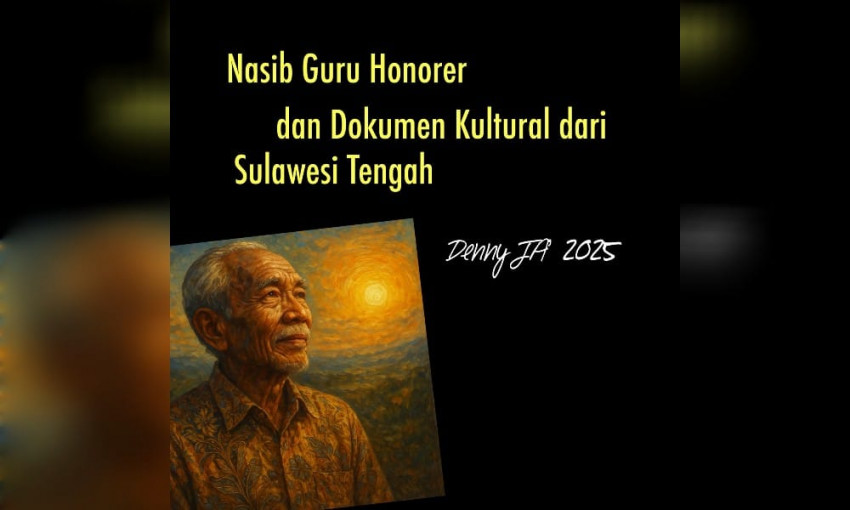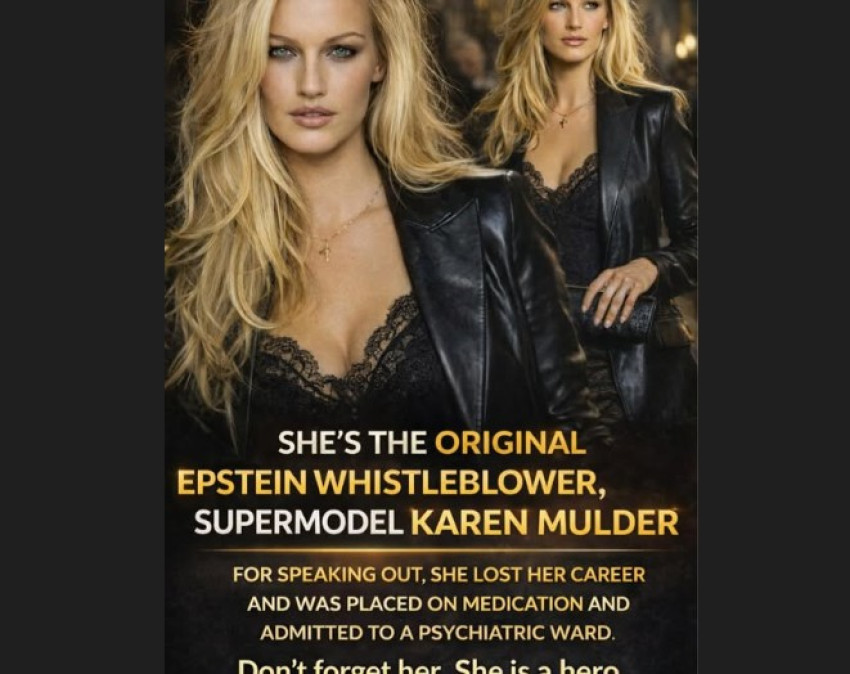Nasib Guru Honorer dan Dokumen Kultural dari Sulawesi Tengah
Pengantar dari Denny JA untuk Buku Antologi Puisi Satupena Sulawesi Tengah: Melukis Pelangi di Bumi Banggai
ORBITINDONESIA.COM - Di sebuah desa kecil di pedalaman Sulawesi Tengah. Lokasinya jauh dari gemerlap kota.
Berdirilah sebuah sekolah kayu yang nyaris roboh. Dindingnya retak, atapnya bocor, lantainya berderit bila diinjak.
Namun, di dalam ruangan sederhana itu, setiap pagi seorang lelaki renta datang dengan langkah pelan tapi teguh. Ia seorang guru honorer.
Tangannya gemetar ketika menuliskan huruf-huruf di papan tulis yang sudah kusam. Kapurnya sering habis.
Kadang ia hanya menulis di udara, seolah huruf-huruf itu hidup dalam imajinasi murid-muridnya.
Gajinya “setipis embun” yang hilang sebelum sempat membasahi tanah. Namun ia terus mengajar dengan mata yang bersinar.
Di matanya ada cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh lapar, gigil, atau janji yang tak pernah ditepati.
Puisi Rastono Sumardi yang berjudul Nasib Guru Honorer (Luwuk, 02/02/2025) merekam realitas itu dengan bahasa yang getir namun indah:
“Gajinya setipis embun di ujung daun,
jatuh sebelum sempat membasahi tanah,
tapi hatinya tetap mengakar,
setia mengajar meski perutnya berbincang dengan lapar.”
Di bait terakhir, sang guru digambarkan sebagai “sebatang lilin yang melawan malam, membakar diri agar dunia tetap terang.”
Di sinilah letak kedalaman puisi. Guru honorer tidak hanya sosok sosial, melainkan metafora eksistensial—api kecil yang menopang terang sebuah bangsa.
-000-
Membaca puisi Guru Honorer yang ditulis oleh Rastono Sumardi dalam buku bersama Satupena Sulawesi Tengah, saya duduk terdiam. Lama. Sedih tapi bangga. Bangga tapi sedih.
Langsung terbayang wajah banyak guru honorer di seluruh pelosok Indonesia. Juga terbayang wajah guru SD saya di Palembang, lebih dari 50 tahun lalu.
Lebih dari separuh guru di Indonesia masih berstatus honorer. Jumlahnya sekitar 2,06 juta orang, atau 56% dari total 4,21 juta guru nasional.
Ironisnya, mereka justru menjadi penopang utama pendidikan di desa-desa terpencil.
Namun gaji mereka kerap di bawah standar: antara Rp300.000 hingga Rp1.500.000 per bulan, bahkan masih banyak yang menerima lebih rendah dari itu.
Meski pemerintah berjanji menaikkan tunjangan profesi pada 2025, mayoritas tetap hidup dengan penghasilan minim, tanpa jaminan sosial, tanpa kepastian status.
Mereka mengajar bukan karena dijanjikan kesejahteraan, tetapi karena mencintai anak-anak yang menatap mereka dengan mata penuh harapan.
Di sini kita bertemu dengan paradoks besar: bangsa yang begitu bangga menyebut guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa.
Tetapi di balik retorika, guru honorer masih diperlakukan sebagai kelas pinggiran dalam birokrasi pendidikan.
Mengapa kondisi ini terus berulang? Ada tiga alasan utama:
1. Status yang tak jelas — puluhan tahun mengabdi, banyak guru tak kunjung diangkat jadi ASN.
2. Keterbatasan anggaran daerah — gaji mereka bergantung pada dana BOS yang makin tergerus.
3. Pandangan kultural — bahwa guru adalah profesi pengabdian, sehingga layak dibayar rendah.
Filosofi pahit ini melahirkan luka struktural: guru diminta membangun bangsa, tetapi kehidupannya sendiri tidak pernah dibangun dengan layak.
-000-
Dalam tradisi Nusantara, lilin bukan sekadar benda penerang, tetapi lambang pengorbanan. Ia menyala dengan cara menghabiskan dirinya sendiri.
Puisi Rastono menghidupkan kembali simbol itu—bahwa guru honorer adalah lilin peradaban. Mereka tidak menunggu tepuk tangan; mereka rela habis demi cahaya anak-anak bangsa.
Namun, apakah sebuah bangsa berhak membiarkan lilin-lilin itu padam dalam kesepian, tanpa minyak, tanpa perlindungan, tanpa ruang untuk tetap menyala?
Puisi ini, bila direnungkan dalam-dalam, adalah alarm moral. Ia menegur kita bahwa penghargaan sejati kepada guru bukanlah pujian atau peringatan Hari Guru, melainkan memberi mereka hak hidup yang layak.
Karena tanpa guru yang kuat, sebuah bangsa hanyalah rumah tanpa pondasi.
Nasib guru honorer sesungguhnya merefleksikan kontradiksi modernitas Indonesia: pembangunan fisik melaju cepat, tetapi pembangunan manusia sering tertinggal.
Membaca puisi ini berarti menuntut keadilan struktural, agar pendidikan tidak hanya menjadi slogan, melainkan fondasi konkret bagi masa depan bangsa.
-000-
Puisi soal Guru Honorer di atas hanya salah satu saja dari begitu banyak puisi dalam buku perkumpulan penulis Satupena Sulawesi Tengah ini.
Tapi buku Melukis Pelangi di Bumi Banggai lebih dari sekadar kumpulan puisi. Ia sebuah dokumen kultural.
Lebih dari 30 penulis ikut menyumbangkan suara—dari guru, siswa, penulis lokal, hingga penulis tamu seperti Hamri Manoppo.
Tema-temanya melingkupi enam spektrum besar:
1. Alam dan lingkungan — hutan yang ditebang, air yang merintih, maleo sebagai simbol adat Banggai.
2. Pendidikan dan guru — dari lilin guru honorer hingga cahaya era digital.
3. Budaya lokal — onyop, tari Umapos, adat Tumpe.
4. Cinta keluarga — rindu ibu, doa ayah, kasih yang tak pernah habis.
5. Religiusitas — doa, cinta kepada Tuhan, refleksi iman.
6. Identitas dan kebangsaan — merah putih, generasi emas, cinta tanah air.
Membaca buku ini seperti berjalan di jalan desa Banggai: melewati sawah, hutan, teluk, rumah panggung, dan ruang kelas sederhana.
Tiap puisi adalah fragmen realitas, potongan jiwa, dan nyanyian tanah yang menolak dilupakan.
-000-
Kekuatan buku adalah kolaborasi lintas usia dan profesi, menjadikan buku ini kaya perspektif.
Ia menjadi arsip budaya Banggai: makanan, tarian, tradisi, hingga lanskap alam.
Membaca buku ini terasa kejujuran emosional: meski banyak puisi sederhana, semuanya tulus.
Apa kelemahannya? Kualitas estetika tidak merata. Beberapa puisi lebih deskriptif daripada reflektif.
Namun kelemahan ini justru memperkuat posisi buku sebagai suara kolektif, bukan sekadar karya individu. Ia penting karena merekam—bukan hanya menghibur.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani bercermin pada ruang kelasnya sendiri. Di sana, kita melihat wajah guru honorer—lelah, renta, tapi tetap tersenyum.
Kita melihat pula wajah anak-anak Banggai yang menatap penuh mimpi.
Puisi-puisi dalam buku ini adalah pelangi: tiap warna mewakili kisah. Ada warna luka, ada warna rindu, ada warna harapan.
Bila disatukan, mereka membentuk lengkung cahaya di langit Banggai—miniatur Indonesia yang lebih luas.
Maka, membaca buku ini adalah membaca diri kita sendiri. Menyadari bahwa penghormatan pada guru dan pada budaya lokal bukanlah romantisme, melainkan kewajiban moral untuk menjaga peradaban.
Selama lilin masih menyala di ruang kelas terpencil. Selama pelangi masih dilukis di langit Banggai, selama itu pula harapan bangsa ini tidak akan padam.***
Jakarta, 18 Agustus 2025
Referensi
Paulo Freire. Pedagogy of the Oppressed. Continuum International Publishing Group, 1970.
-000-
Ratusan esai Denny JA soal filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, politik demokrasi, sejarah, positive psychology, catatan perjalanan, review buku, film dan lagu, bisa dilihat di FaceBook Denny JA’s World