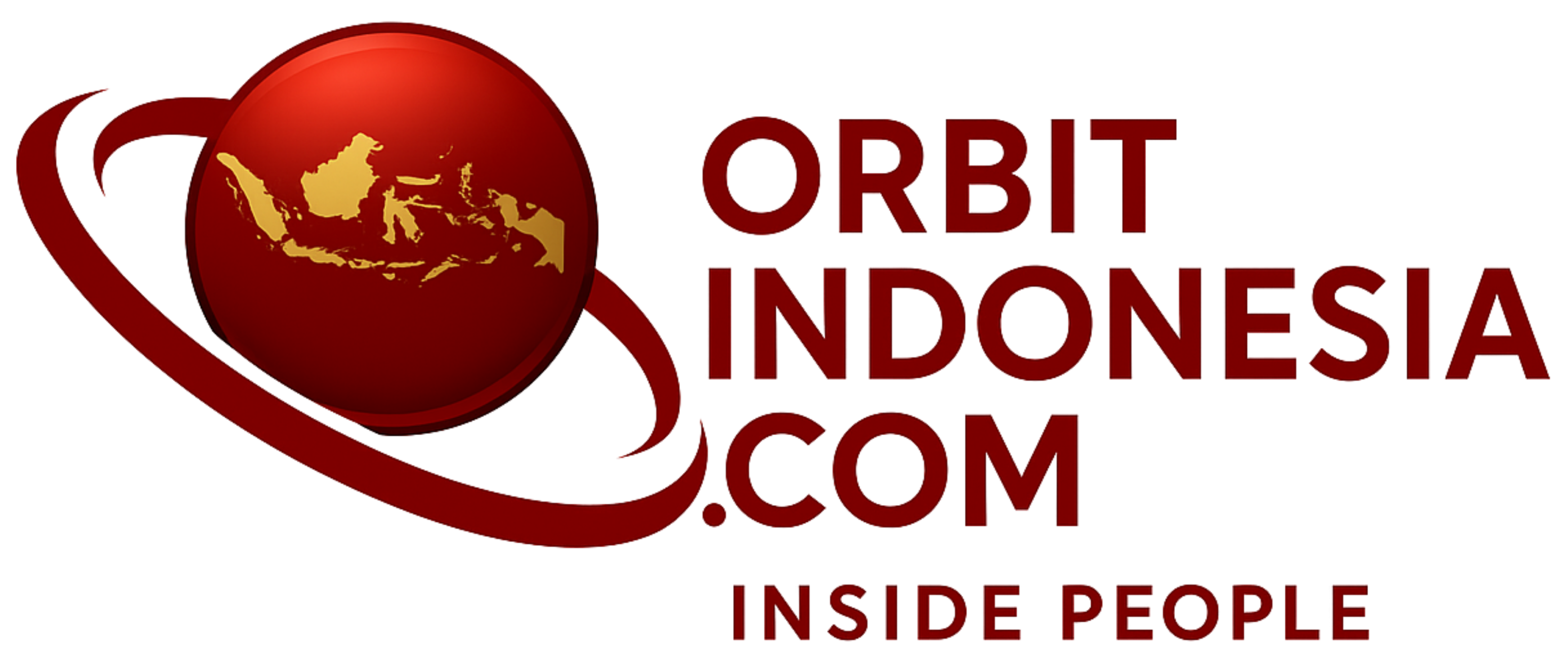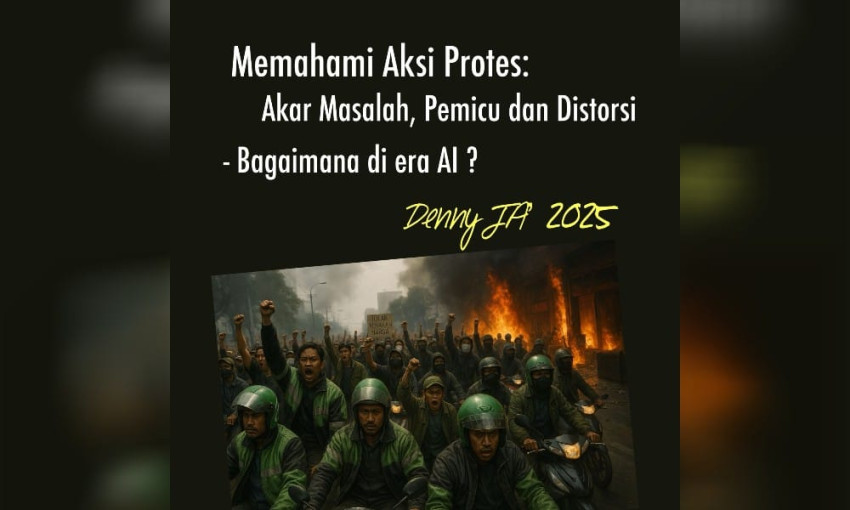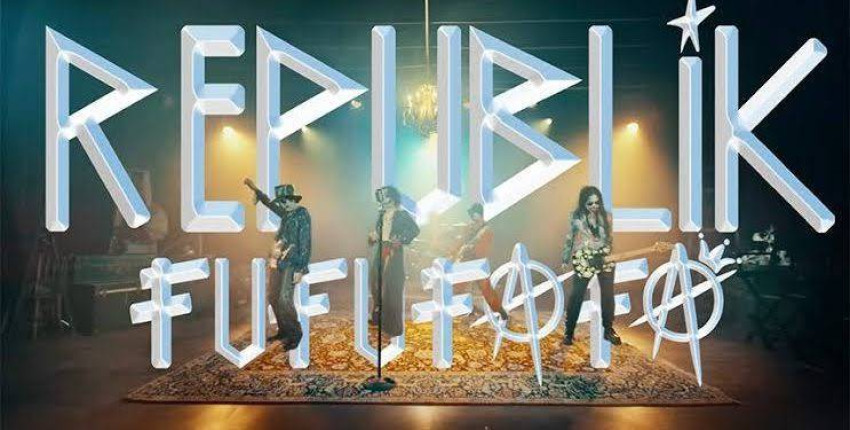Catatan Denny JA: Mamahami Aksi Protes, Akar Masalah, Pemicu, dan Distorsi
ORBITINDONESIA.COM - Riset besar berjudul World Protests 2006–2013 dilakukan Isabel Ortiz dkk. Mereka menganalisis lebih dari 840 kasus aksi protes di 84 negara.
Dari sana lahir pola universal: setiap protes berskala nasional selalu bisa dibedah dalam tiga kategori—akar masalah, pemicu, dan distorsi.
-000-
Akar masalah adalah lapisan terdalam, alasan yang menghimpun massa dalam kegelisahan kolektif.
Dalam 55–60% kasus, faktor utamanya adalah kegelisahan ekonomi: daya beli runtuh, harga pangan melonjak, lapangan kerja menyempit.
Ekonomi memukul langsung perut rakyat. Dan perut lapar selalu lebih jujur daripada jargon politik.
Pemicu adalah percikan sesaat yang membuat bara menyala.
Ia bisa berupa kenaikan harga bahan bakar, ucapan arogan pejabat, atau peristiwa tragis yang menyentuh hati publik.
Korban nyawa acapkali menjadi pemicu yang paling emosional. Ketika ada darah rakyat tumpah, kualitas kegelisahan melompat berkali lipat.
Namun pemicu bukanlah akar. Tetapi tanpanya, protes tak akan membesar menjadi arus nasional.
Distorsi adalah fase ketika energi murni rakyat dibelokkan.
Di sinilah kelompok kepentingan menunggangi amarah. Provokasi menyusup, hingga protes damai berubah menjadi kerusuhan.
Pesan rakyat—tentang harga beras, tentang pajak, tentang pekerjaan—tenggelam dalam asap, kaca pecah, dan api yang melahap gedung.
-000-
Pola ini tampak jelas pada aksi protes Agustus–September 2025 di 32 provinsi Indonesia.
Kisahnya berawal dari dapur-dapur sederhana. Harga pangan meroket. Pekerja di Bekasi dan Karawang, dan aneka wilayah lainnya, menerima surat PHK. Startup digital tumbang, hotel-hotel merumahkan karyawan.
Pajak bumi dan bangunan malah dinaikan. Surat penagihan berdatangan. Rekening rakyat diblokir.
Semua ini adalah rumput kering. Ia bisa diam, tapi menunggu percikan api.
Dan datanglah pemicu itu.
Pertama, tunjangan DPR naik. Slip gaji anggota dewan beredar di media sosial. Rakyat yang lapar merasa para wakilnya di pemerintahan tidak peka.
Kedua, gaya komunikasi politisi yang arogan. Rakyat yang protes dihina “paling tolol sedunia.”
Kata-kata, yang seharusnya menjadi air penyejuk, justru menjadi bensin yang membakar kemarahan.
Lalu tragedi: Affan Kurniawan, pengemudi ojek online, tewas terlindas (dilindas) mobil aparat.
Ia bukan aktivis garis depan, hanya rakyat kecil yang ingin pulang. Tetapi tubuhnya yang tergeletak di jalan menjelma simbol penderitaan nasional.
Gelombang protes pun menjelma tsunami.
-000-
Namun protes murni itu rapuh.
Awalnya damai—ojol meniup klakson, mahasiswa berorasi, buruh membawa obor. Ada nuansa ritual solidaritas.
Tapi provokasi masuk. Batu melayang, api menyala, kantor DPRD Makassar terbakar. Kantor pejabat dijarah. Aparat membalas dengan gas air mata.
Di titik itulah distorsi terjadi. Suara rakyat soal beras, PHK, dan pajak, lenyap di balik asap. Kamera hanya merekam kekerasan, bukan pesan.
-000-
Apa yang terjadi di Indonesia 2025 hanyalah pola lama.
* Revolusi Prancis 1789 meletus karena roti mahal. Dari antrian roti, lahir semboyan “Liberté, Égalité, Fraternité.”
* Arab Spring 2010–2011 dimulai ketika Mohamed Bouazizi membakar diri karena frustrasi ekonomi. Api tubuhnya menjalar ke Timur Tengah.
* Solidarność Polandia 1980-an lahir dari buruh yang mogok karena harga kebutuhan pokok melonjak. Dari Gdańsk, gelombang itu mengguncang Uni Soviet.
Semua berangkat dari perut lapar. Politik bisa ditunda. Korupsi bisa ditoleransi sementara. Tapi perut kosong memaksa rakyat turun ke jalan.
-000-
Dalam budaya Jawa ada pepatah: “Mangan ora mangan kumpul.” Namun jika mangan terganggu, kumpul berubah menjadi protes.
Dalam falsafah Bugis, ada konsep siri’ na pacce—harga diri dan solidaritas. Ketika rakyat lapar dan diinjak, solidaritas berubah menjadi badai.
Filosofi utama: perut rakyat adalah fondasi legitimasi negara. Tanpa itu, stabilitas hanyalah fatamorgana.
-000-
Prabowo sudah mampu meredam gelombang protes yang sempat membara di 32 provinsi.
Penyusup yang mendistorsikan aksi sudah ditangani. Pemicu yang membakar bara berhasil didinginkan.
Namun bagaimana dengan rumput kering di ladang rakyat? Bagaimana dengan akar masalah: perut yang lapar, dompet yang menipis, dan pekerjaan yang hilang?
Untuk itu, sebenarnya Prabowo sudah datang terlebih dahulu dengan sebelas program besar—program populis yang ingin menjangkau rakyat kecil.
Ada makan siang gratis untuk anak-anak sekolah. Ada Koperasi Merah Putih untuk menghidupkan ekonomi desa.
Ada Sekolah Rakyat, Rumah Rakyat, rehabilitasi sekolah, penuntasan tuberkulosis, cek kesehatan gratis, hingga pembangunan irigasi dan infrastruktur pangan.
Semua itu bagai oase yang dijanjikan di tengah padang gersang.
Dana yang disiapkan bukan kecil: lebih dari Rp 446 triliun. Angka raksasa yang, bila benar sampai ke meja makan rakyat, bisa mengubah wajah keseharian.
Masalahnya di tingkat eksekusi. Di lapangan, berkah itu belum mengalir deras. Hingga September 2025, serapan anggaran masih di bawah 20 persen.
Alasannya bisa dipahami: program baru, skala raksasa, birokrasi yang masih canggung.
Namun rakyat yang menanti tak bisa hanya diberi penjelasan. Perut tak kenyang oleh laporan teknis.
Kenaikan pajak fantastis PBB sebaiknya ditunda dulu karena ekonomi rakyat sedang tidak baik- baik saja. Percepat aneka program yang mengalirkam dana ke masyarakat, agar ekonomi bergerak kembali.
Hal ini juga perlu diberikan perhatian ekstra. Tanpa reformasi birokrasi yang radikal, dana raksasa program populis akan macet atau bocor di jalan.
Transparansi eksekusi, pemangkasan rente, dan digitalisasi distribusi dengan dukungan AI harus segera ditempuh.
Hanya dengan itu, program populis berubah menjadi realitas di meja makan rakyat.
-000-
Di era AI, apakah aksi protes ini akan lebih mudah digerakkan?
Di tahun 2025, protes tidak lagi hanya berbentuk kerumunan fisik di jalan. Kini, protes juga berlangsung di layar ponsel kita.
Hashtag di Twitter atau Instagram bisa menjelma petisi raksasa. Satu kalimat pendek, diberi tanda pagar, bisa menyatukan jutaan orang.
#KeadilanUntukAffan, misalnya, dapat bergerak lebih cepat daripada selebaran atau poster fisik.
Livestream di TikTok atau YouTube membuat kekerasan aparat tidak bisa lagi disembunyikan.
Jika ada seorang demonstran dipukul, dalam hitungan detik, jutaan mata bisa menyaksikan. Rekaman itu hidup abadi di internet, menjadi saksi sekaligus bukti.
Kecerdasan buatan (AI) pun kini ikut terlibat. AI bisa menganalisis pola kerusuhan: siapa yang memulai, bagaimana massa bergerak, bahkan memprediksi lokasi bentrokan berikutnya.
Namun di balik semua itu, teknologi bukan malaikat. Ia adalah pedang bermata dua.
Algoritma media sosial bisa memperparah perpecahan. Ia menciptakan echo chamber—ruang gema di mana orang hanya mendengar pendapat yang sama dengan kelompoknya.
Akibatnya, yang moderat jadi radikal, dan yang radikal bisa makin keras.
Lebih berbahaya lagi, muncul deepfake: video palsu yang sangat meyakinkan. Seseorang bisa terlihat seolah-olah mengucapkan kata-kata yang tidak pernah ia ucapkan.
Atau aparat terlihat menembak massa padahal rekaman itu buatan. Deepfake bisa menyesatkan, menyalakan api kebencian yang salah arah.
Aksi protes dan kerusuhannya di akhir Agustus 2025 hanyalah satu bab. Semoga ia menjadi pelajaran, bukan sekadar luka.
Semoga ia bukan api yang bersembunyi menunggu untuk meledak lagi. Ini hanya terjadi jika kegelisahan ekonomi masyarakat terobati.
Sejarah selalu menulis dengan tinta merah: rakyat yang gelisah secara ekonomi tak bisa dibungkam. Dari Bastille di Paris hingga Tahrir Square di Kairo, dari Gdańsk hingga jalanan Jakarta, suara mereka selalu menemukan jalannya.
Pada akhirnya, legitimasi sebuah negara tidak hanya ditopang oleh gedung megah, jargon politik, atau laporan ekonomi yang indah di atas kertas.
Legitimasi itu harus juga berdiri di atas meja makan rakyat. Selama nasi tersaji, harapan terjaga, dan perut tak lagi kosong, rakyat akan memilih untuk percaya.
Namun bila meja makan itu kosong, sejarah membuktikan: rakyat akan bangkit, dan suara mereka akan lebih keras daripada segala barikade kekuasaan. *
Jakarta, 4 September 2025
Referensi:
1. Isabel Ortiz, Sara Burke, Mohamed Berrada, Hernán Cortés Saenz. World Protests 2006–2013. Initiative for Policy Dialogue & Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013.
2. James C. Davies. When Men Revolt and Why. Free Press, 1971.
-000-
Ratusan esai Denny JA soal filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, politik demokrasi, sejarah, positive psychology, catatan perjalanan, review buku, film dan lagu, bisa dilihat di FaceBook Denny JA’s World
https://www.facebook.com/share/p/1C1GBy2Cet/?mibextid=wwXIfr