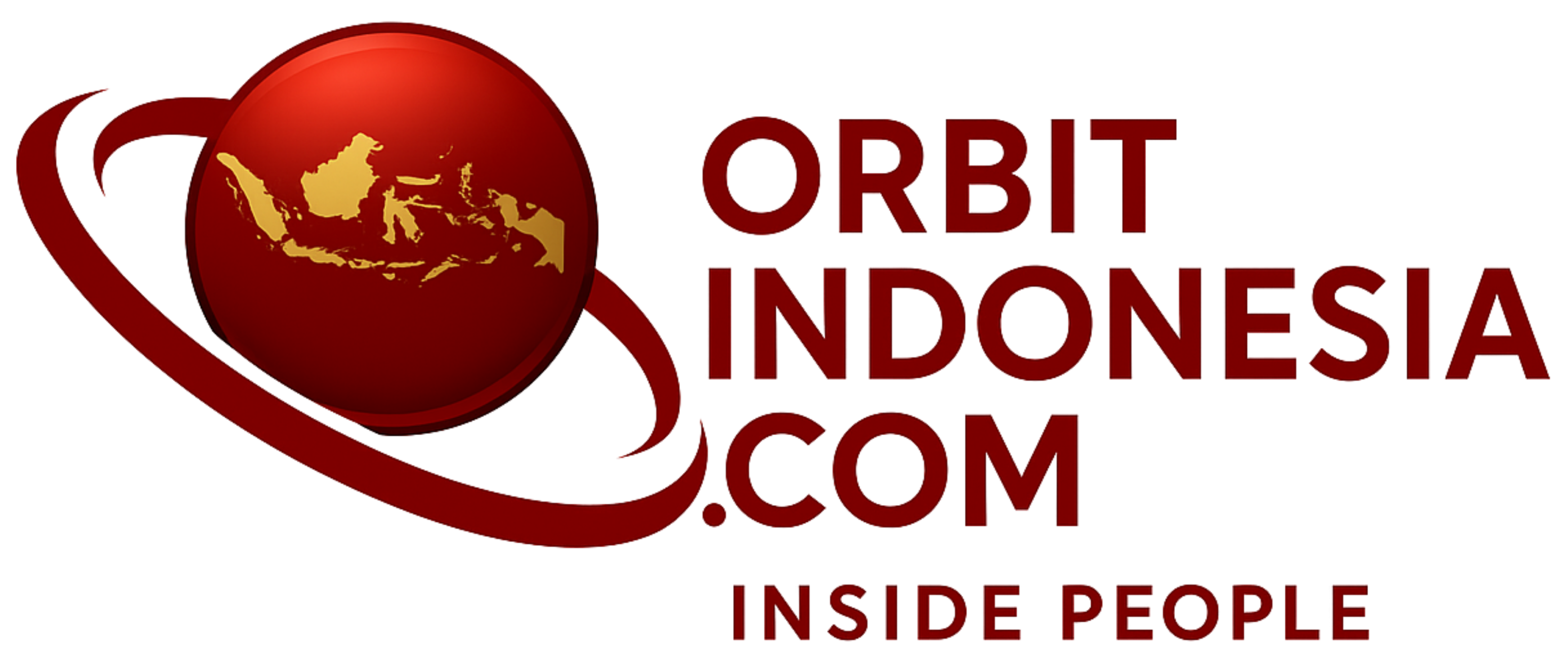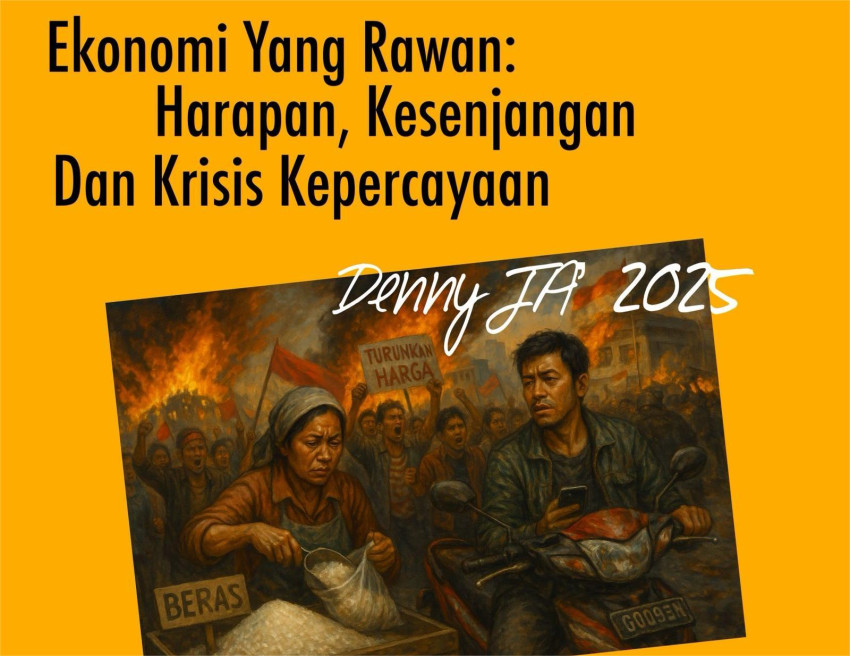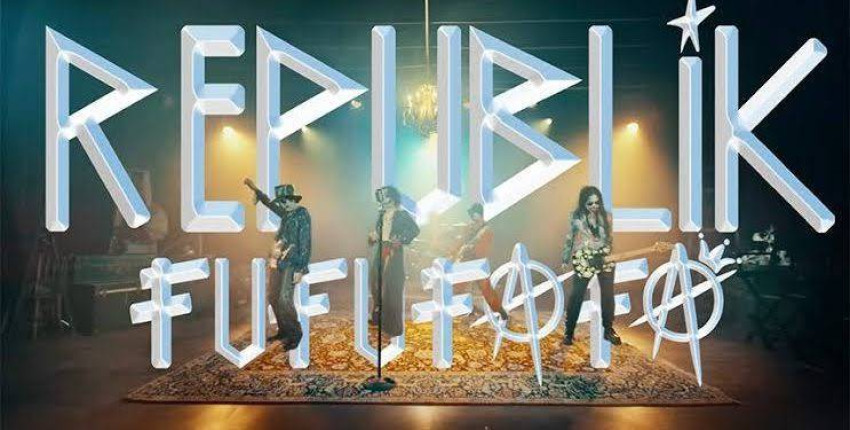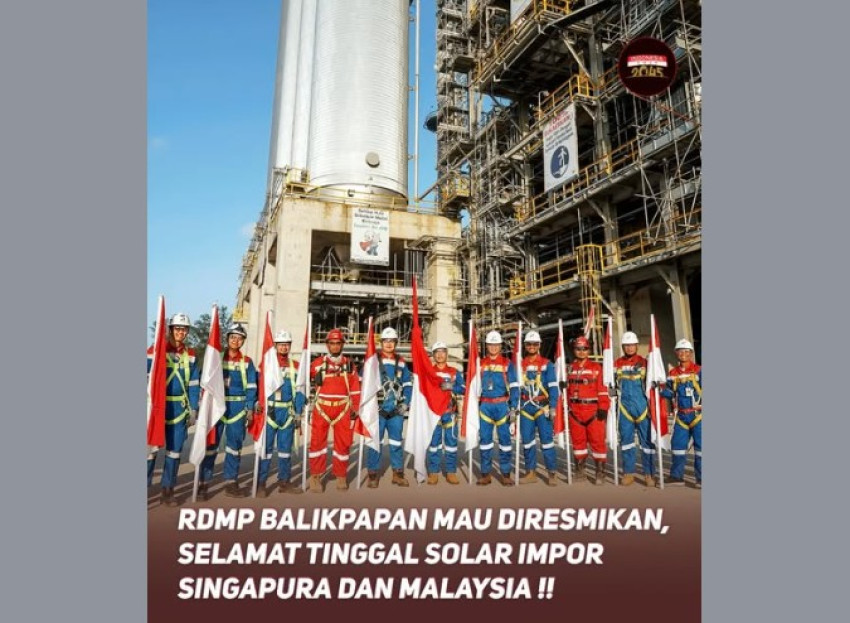Catatan Denny JA: Ekonomi yang Rawan, Kesenjangan, dan Krisis Kepercayaan
Oleh Denny JA
ORBITINDONESIA.COM - Pukul lima pagi di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, seorang ibu bernama Lasmi mengatur dagangan berasnya.
Tangannya lincah menuang butiran padi putih ke dalam takaran literan yang sudah berkarat. Di sampingnya, anak bungsunya yang masih duduk di bangku SD membantu membungkus.
Hari itu Lasmi menahan air mata. Harga beras melonjak dalam hitungan bulan. “Yang biasanya bisa beli lima liter, sekarang hanya tiga."
“Mereka (pembeli) marah ke saya. Padahal saya juga bingung harus jual berapa,” katanya lirih.
Di seberang jalan, seorang pengemudi ojek daring yang baru selesai 15 order menghitung penghasilan bersihnya.
Setelah dipotong ongkos bensin dan cicilan motor lewat aplikasi pay later, sisa uangnya nyaris tak cukup membeli kebutuhan pokok.
“Saya kerja keras, tapi rasanya makin miskin,” ia bergumam, menyalakan kembali aplikasinya.
Dua wajah ini—ibu pedagang dan anak muda pekerja informal—adalah potret sebagian Indonesia 2025.
Inflasi bukan lagi sekadar angka statistik, tetapi pisau yang mengiris piring makan, menipiskan jatah lauk, dan menunda uang jajan sekolah.
-000-
Data BPS Agustus 2025 mencatat inflasi pangan 3,99 persen, dengan kenaikan beras sebagai pendorong utama.
Sementara itu, laporan Global Wealth Report (2025) menyebut 40 persen kekayaan nasional dikuasai oleh 1 persen populasi.
Ketika televisi dan media sosial memamerkan pesta pernikahan mewah, liburan selebritas, atau pejabat yang memamerkan harta, rakyat kecil semakin merasa terpinggirkan di tanah sendiri.
Mereka bukan sekadar miskin; mereka miskin di tengah tontonan kemewahan.
Rasio Gini Indonesia (0,375–0,38) menjadi angka sunyi yang menyimpan jerit, jurang kaya–miskin yang makin lebar.
Dari sinilah lahir rasa sakit sosial: orang merasa tidak adil bukan hanya karena sedikitnya pendapatan, tapi karena menyaksikan betapa jauhnya jarak dari yang mereka anggap “semestinya bisa dicapai.”
-000-
Dalam bukunya Why Men Rebel (1970), Ted Robert Gurr menjelaskan bahwa akar protes sosial bukan sekadar kemiskinan absolut, melainkan relative deprivation (RD – Rasa Tidak Adil).
Ini jarak antara harapan dan kenyataan.
Ketika harapan tumbuh lebih cepat daripada kenyataan yang bisa diraih, frustrasi mengendap menjadi bara.
Bara itu, ketika disulut oleh peristiwa pemicu—seperti tragedi seorang pengemudi ojol yang tewas dalam demonstrasi Agustus 2025—meledak menjadi api kerusuhan.
Gurr menunjukkan dalam berbagai studi sejarah: masyarakat yang merasa harapannya dikhianati cenderung lebih cepat memberontak.
Fenomena Arab Spring 2010–2011, krisis 1998 di Indonesia, atau bahkan jatuhnya Orde Lama 1966 semuanya punya pola sama: inflasi tinggi, kesenjangan mencolok, dan hilangnya rasa keadilan.
-000-
Ted Robert Gurr menulis Why Men Rebel pada 1970, di tengah gelombang protes global: perang Vietnam, gerakan hak sipil di Amerika, hingga revolusi mahasiswa di Eropa.
Ia bertanya: mengapa manusia, yang sejatinya mencari ketertiban, bisa tiba-tiba memilih jalan pemberontakan?
Jawaban Gurr terletak pada konsep relative deprivation (RD – Rasa Tidak Adil) —perasaan subjektif bahwa seseorang atau kelompok tidak memperoleh apa yang mereka yakini layak mereka dapatkan.
RD (Rasa Tidak Adil) bukan soal absolut; orang miskin tidak selalu memberontak. Tetapi orang yang merasa diperlakukan tidak adil, atau merasa tertinggal dari standar harapan mereka, cenderung marah dan mencari pelampiasan.
Gurr membedakan tiga tipe RD (Rasa Tidak Adil):
1. Decremental deprivation – ketika standar hidup menurun tajam (misalnya akibat inflasi atau krisis ekonomi).
2. Aspirational deprivation – ketika harapan tumbuh pesat (karena modernisasi, pendidikan, media) tapi realitas tak mengikutinya.
3. Progressive deprivation – ketika keadaan sempat membaik lalu memburuk, menimbulkan rasa dikhianati.
Ketiga tipe ini menciptakan frustrasi kolektif. Menurut Gurr, frustrasi itu jarang tetap pasif; ia mencari saluran.
Jika institusi formal gagal menyalurkannya, frustrasi meledak menjadi protes, kerusuhan, bahkan revolusi.
Buku ini juga membedakan antara intensitas dan lingkup RD (Rasa Tidak Adil).
Semakin banyak orang yang merasa terpinggirkan, semakin luas protesnya. Semakin dalam rasa ketidakadilan yang dialami, semakin keras pula ledakan kemarahannya.
Gurr menggunakan sejarah untuk memperkuat analisisnya: dari Revolusi Prancis, Revolusi Rusia, hingga gerakan pembebasan di dunia kolonial.
Ia menemukan pola konsisten: krisis ekonomi, kesenjangan sosial, dan runtuhnya legitimasi politik adalah “triad maut” yang melahirkan pemberontakan.
Namun, Gurr juga menekankan peran pemicu (triggers). RD (Rasa Tidak Adil) bisa berlangsung lama tanpa protes.
Tetapi ketika ada peristiwa simbolik—seorang pemuda dibunuh polisi, seorang buruh diperlakukan semena-mena, atau harga pangan melambung drastis—maka RD (Rasa Tidak Adil) berubah menjadi mobilisasi massa.
Pesan filosofis Gurr jelas: stabilitas politik bergantung bukan pada kemakmuran absolut, tetapi pada kemampuan negara mengelola harapan rakyatnya.
Jika jurang antara harapan dan kenyataan dibiarkan melebar, negara sedang menabur bibit pemberontakan.
-000-
Krisis Kepercayaan
Kerusuhan 2025 adalah gejala lebih dalam: krisis kepercayaan. Rakyat bukan hanya kecewa pada harga pangan atau gaji yang tak cukup, tapi juga pada pejabat negara yang dianggap abai.
Ketika aparat dipandang lebih sigap melindungi kepentingan elite daripada rakyat, kepercayaan runtuh.
Di titik ini, statistik makroekonomi berhenti bermakna; yang berbicara adalah tubuh-tubuh lelah yang turun ke jalan.
Pasar modal jatuh, rupiah tertekan, modal asing keluar. Namun lebih berbahaya dari semua itu adalah runtuhnya ikatan psikologis antara rakyat dan negara.
Tanpa kepercayaan, kontrak sosial pecah, dan dari pecahan itulah lahir kekacauan.
-000-
Pelajaran Sejarah
Kita pernah mengalaminya. Tahun 1966, inflasi beras dan minyak goreng meroket, legitimasi politik runtuh, rezim berganti.
Tahun 1998, krisis moneter membuat harga melesat, pengangguran meningkat, dan rakyat marah. Kerusuhan meledak, Soeharto turun.
Hari ini, 2025, pola itu bergema kembali. Inflasi, kesenjangan, dan kekecewaan berbaris dalam satu pawai sejarah.
Sejarah berulang kali memberi pesan: dapur rakyat yang kosong lebih berbahaya daripada senjata.
-000-
Filosofi yang Bisa Direnungkan
Apa pelajaran terdalam dari semua ini? Bahwa negara bukan sekadar mesin birokrasi atau angka PDB. Negara adalah kepercayaan yang dijalin dari pengalaman sehari-hari rakyatnya.
Inflasi, kesenjangan, dan utang rumah tangga bukan sekadar problem ekonomi, tetapi luka budaya, luka psikologis. Ia merusak rasa adil, memicu rasa malu, dan menumbuhkan marah kolektif.
Ted Gurr mengingatkan kita: yang berbahaya bukanlah kemiskinan itu sendiri, melainkan kemiskinan yang dirasakan di tengah janji dan harapan yang tidak terpenuhi.
Maka, yang paling penting bukan hanya menjaga angka makro, tapi menjaga janji sosial: bahwa kerja keras memberi hasil, bahwa anak-anak bisa makan cukup, bahwa masa depan tetap terbuka.
-000-
Penutup: Bara di Dapur Rakyat
Kisah Lasmi dan pengemudi ojol adalah metafora bangsa. Dapur rakyat adalah dapur negara.
Jika api di tungku rakyat padam, negara pun kehilangan tenaganya. Jika bara di dapur rakyat menyala terlalu besar, ia bisa membakar sendi-sendi politik dan tatanan sosial.
Pilihan ada di tangan pemimpin: apakah menjadikan bara itu sebagai cahaya reformasi atau membiarkannya menjadi kobaran api kerusuhan?
Untuk menghentikan siklus kerusuhan yang berulang, kita butuh langkah berani. Pertama, pajak kekayaan progresif: yang kaya membayar lebih besar agar jurang dengan si miskin tak makin lebar.
Kedua, platform digital partisipatif: rakyat bisa mengawasi birokrasi secara langsung, sehingga pejabat tak bisa lagi bersembunyi di balik meja.
Ketiga, pendidikan kritis: sejak dini masyarakat diajari memahami rasa “tidak adil” (relative deprivation) agar sadar bahwa keadilan bukan hadiah dari penguasa, melainkan hak yang wajib diperjuangkan.
Tiga langkah ini sederhana untuk dipahami, namun dampaknya bisa mengubah wajah bangsa.
Sejarah berulang kali memperingatkan: yang menentukan masa depan bukan sekadar kebijakan fiskal, tetapi bagaimana janji keadilan sosial diwujudkan di meja makan setiap keluarga.*
Jakarta, 16 September 2025
Referensi
• Gurr, Ted Robert. Why Men Rebel. Princeton University Press, 1970.
• Piketty, Thomas. Capital in the Twenty-First Century. Harvard University Press, 2014.
• Data resmi: BPS, Bank Indonesia, Global Wealth Report, Trading Economics, media nasional.
-000-
Ratusan esai Denny JA soal filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, politik demokrasi, sejarah, positive psychology, catatan perjalanan, review buku, film dan lagu, bisa dilihat di FaceBook Denny JA’s World
https://www.facebook.com/share/p/1BPgojGjzB/?mibextid=wwXIfr ***