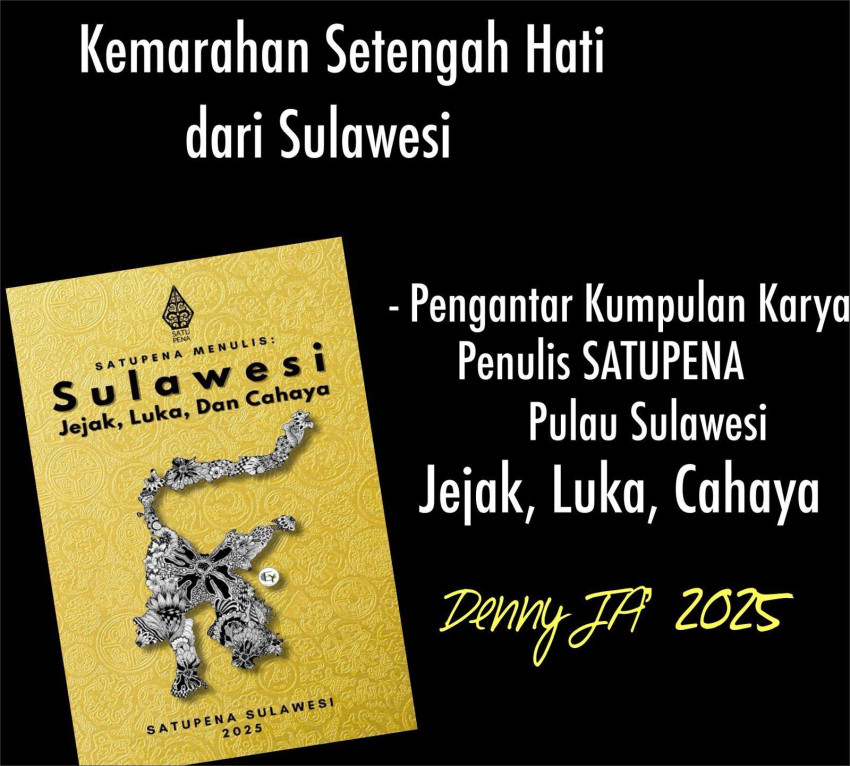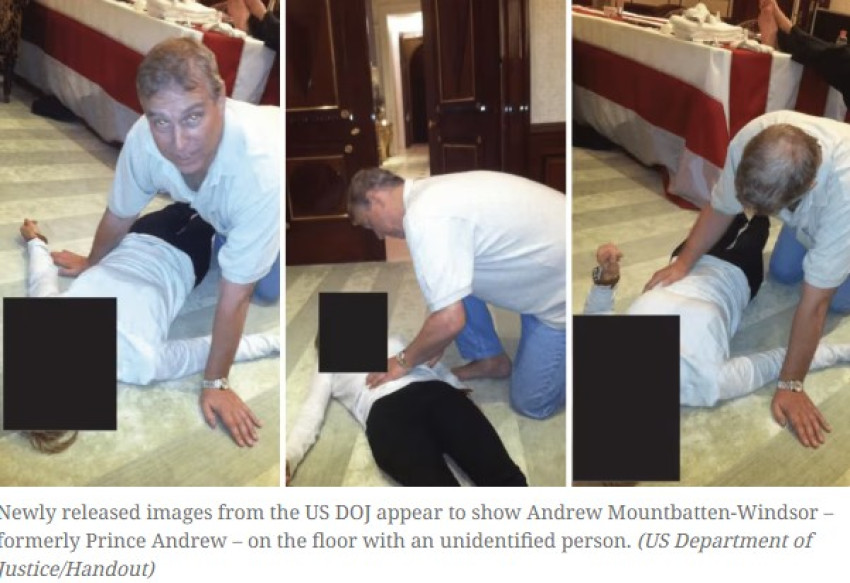Denny JA: Kemarahan Setengah Hati Dari Sulawesi
- Pengantar buku Kumpulan Penulis Satupena Sulawesi: Jejak, Luka, Cahaya
Oleh Denny JA
“Apakah kau pernah melihat Ismail, ayahku?”
— Hamri Manoppo, Yang Tercecer di Perang Permesta
Puisi esai Hamri Manoppo membuka jendela pada satu wajah sejarah. Anak itu bernama Amir yang bertanya tanpa henti tentang ayahnya yang hilang di hutan Permesta.
Sejarah resmi hanya mencatatnya sebagai “pemberontakan,” sebuah catatan kaki dari Republik muda.
Namun bagi Amir, Permesta bukanlah sekadar peristiwa politik. Ia adalah momen kehilangan ayah. Ia adalah sepi yang diwariskan turun-temurun.
Pertanyaan anak itu—di manakah ayahku?—lebih tajam dari desingan peluru.
Ia melubangi dinding kokoh narasi negara dan menghadirkan wajah manusia dari sebuah konflik.
-000-
Membaca puisi esai Hamri Manoppo tentang drama kemanusiaan Permesta di Sulawesi, saya teringat sebuah buku sejarah.
Barbara S. Harvey, dalam karyanya Permesta: Half a Rebellion, menuliskan Permesta dengan ketelitian riset akademis.
Ia menyingkap lapisan-lapisan politik, militer, dan rasa kecewa daerah terhadap pusat.
Permesta lahir dari Piagam Perjuangan Semesta, dibacakan 2 Maret 1957 di Makassar.
Kolonel Alex Kawilarang bersama Ventje Sumual dan tokoh militer lain menuntut reformasi: pemerataan pembangunan, restrukturisasi angkatan bersenjata, dan penghentian komunisme.
Mereka tidak mengangkat bendera separatisme; mereka masih menyebut diri bagian dari Indonesia.
Namun, Jakarta menilai sikap itu sebagai pembangkangan. Dari sinilah percikan berubah menjadi api.
Harvey menuliskan dengan detail: bagaimana pangkalan udara darurat dibangun di Manado, bagaimana logistik dikelola dari pelabuhan-pelabuhan kecil, hingga bagaimana kontak senjata memporakporandakan desa-desa di Minahasa.
Tahun 1958 menjadi titik balik. Ketika operasi militer pusat berhasil merebut Manado, Permesta terdesak ke pedalaman.
Pertempuran kemudian menyebar ke Tomohon, Tondano, Bolaang Mongondow. Di balik peta strategi, Harvey menyisipkan catatan kecil namun memilukan.
Ibu-ibu berlarian menyembunyikan anak di lubang tanah, pasar sepi karena malam hanya diisi desingan mortir, dan para pemuda desa menghilang ke hutan tanpa kabar kembali.
Salah satu bab yang menggugah adalah ketika Harvey mencatat dimensi internasional. CIA terlibat mendukung PRRI/Permesta lewat suplai senjata dan pilot bayaran.
Namun ketika pesawat yang diterbangkan Allen Pope jatuh dan ia ditangkap hidup-hidup (1958), wajah asing itu membuka borok dukungan luar negeri.
Dukungan pada PRRI/Permesta pun menguap, sementara pemerintah pusat semakin menguat. Sejak itu, gerilya Permesta semakin terjepit.
-000-
Tetapi Harvey tidak berhenti pada statistik perang. Ia menuliskan wajah manusia yang tersisa.
Itu deskripsi desa-desa yang tinggal puing, anak-anak yatim yang menjadi gelandangan kecil di pasar, para istri yang menunggu kabar suami dari hutan.
Buku ini merekam bahwa Permesta bukan sekadar episode politik, melainkan tragedi sosial yang merenggut ribuan kehidupan.
Mengapa disebut “setengah pemberontakan”? Karena pada intinya, para pemimpin Permesta tidak ingin merobohkan Republik, hanya ingin memperbaikinya.
Tetapi idealisme itu pecah di lapangan: terbelah oleh perbedaan strategi, kepentingan personal, dan situasi internasional.
Setengah kesetiaan dan setengah perlawanan itu menjadikan Permesta tak pernah sepenuhnya revolusi, tetapi juga tak lagi sekadar kritik.
Akhirnya, jalur damai yang membuka pintu pulang. Pada 1961, melalui amnesti dan abolisi, banyak tokoh Permesta menyerahkan diri. Ventje Sumual, figur sentralnya, pun turun dari hutan.
Namun luka telah terlanjur dalam. Di Minahasa, di Kotamobagu, di Bolaang Mongondow, masih tersisa keluarga-keluarga yang tak pernah tahu di mana suami, ayah, atau anak mereka terkubur.
Itulah yang membuat buku Harvey penting: ia memberi kita pandangan ganda. Di satu sisi, sejarah militer yang faktual dan presisi.
Di sisi lain, kesadaran bahwa di balik istilah “pemberontakan” selalu ada wajah-wajah manusia yang hilang, menangis, dan terluka.
-000-
Namun, puisi Hamri hanyalah satu dari sekian banyak suara yang terangkum dalam buku Sulawesi: Jejak, Luka, Cahaya.
Buku ini adalah mozaik karya puluhan penulis Satupena Sulawesi. Ada esai, puisi esai, puisi, dan cerpen yang bersama-sama melukis wajah Sulawesi dengan warna luka sekaligus cahaya.
Di dalamnya, esai mengurai sejarah dan budaya: dari Dato Tiro di Bulukumba, aksara Wolio di Buton, hingga Gusung Tallang di Makassar.
Puisi esai merajut tragedi nyata: anak-anak yang kehilangan ayah di perang saudara, istri yang ditinggal suami di lubang tambang, remaja yang kakinya terputus oleh tsunami Palu.
Puisi menyalakan ingatan tentang pahlawan: Sultan Hasanuddin, Nani Wartabone, dan suara alam yang kian redup.
Cerpen menyelipkan drama harian: cinta di Danau Paisupok, atau guru pedalaman yang bertarung dengan sepi.
Inilah peta emosional Sulawesi: luka yang berdarah, jejak yang tertinggal, cahaya yang menyala.
Di antara retakan sejarah, ada kisah Lontara' yang tak terbaca: seorang guru di pegunungan Maros mengajar anak-anak mengeja aksara kuno di atas pasir.
Sementara truk-truk tambang melintas membawa emas dari perut bumi. Di sini, cahaya bukan sekadar harap—ia adalah perlawanan diam-diam.
Tiap goresan huruf di tanah adalah janji bahwa ingatan tak akan mati, bahkan ketika hujan mengikisnya setiap musim.
-000-
Permesta di Sulawesi Utara, tambang emas yang runtuh di Bolaang Mongondow, tsunami Palu 2018—semua peristiwa ini saling bersahut.
Seakan Sulawesi adalah tubuh yang terus diuji: oleh politik yang menorehkan luka, oleh ekonomi yang timpang, oleh bencana alam yang mengguncang.
Namun dari tubuh yang luka itu, selalu ada cahaya. Amir tumbuh tanpa ayah, tapi ia menulis.
Aisyah kehilangan suami, tapi ia tetap bertahan.
Nurul kehilangan kakinya, tapi ia kembali ke sekolah dengan kursi roda, membawa wajah harapan bagi bangsa.
Sejarah sering ditulis dengan angka—tahun, korban, operasi militer.
Tetapi buku ini mengingatkan: sejarah sejati adalah air mata yang jatuh di tikar bambu, doa ibu yang menggema di malam sunyi, dan tawa anak yang kembali bersekolah di tanah yang retak.
Sulawesi adalah Indonesia dalam miniatur: setengah pemberontakan, setengah rekonsiliasi; setengah luka, setengah cahaya.
Dan dari setiap setengah itu, lahirlah keutuhan:
keutuhan sebuah bangsa yang belajar dari luka.
Ini keutuhan sebuah manusia yang tetap mencari ayahnya,
keutuhan sebuah pulau yang berbisik kepada kita semua:
“Jagalah aku, karena di setiap denyutku ada jiwa Indonesia.”**
Singapura, 1 Oktober 2025
Referensi
1. Barbara S. Harvey, Permesta: Half a Rebellion. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1977 (repr. Equinox, 2009).
2. Hamri Manoppo dkk., Sulawesi: Jejak, Luka, Cahaya. Perkumpulan Penulis Satupena Sulawesi, 2025.
-000-
Ratusan esai Denny JA soal filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, politik demokrasi, sejarah, positive psychology, catatan perjalanan, review buku, film dan lagu, bisa dilihat di FaceBook Denny JA’s World
https://www.facebook.com/share/p/1CDYYAd5qu/?mibextid=wwXIfr ***