Populisme: Janji yang Tak Pernah Mati
Oleh Sudarsono Soedomo, dosen IPB Bogor
ORBITINDONESIA.COM - Populisme selalu datang dengan wajah ramah dan bahasa rakyat. Katanya ingin membela wong cilik, melawan elite, dan memberantas korupsi. Setiap lima tahun, populisme seperti film lama yang diputar ulang dengan judul baru, aktor baru, tetapi naskahnya sama: “Saya akan berpihak pada rakyat.”
Masalahnya, setelah menang, rakyat yang katanya diperjuangkan itu sering hilang dari naskah. Yang tersisa hanya spanduk usang dan jargon kosong yang menggantung di pinggir jalan. Populisme akhirnya menjadi semacam agama politik: penuh janji keselamatan, tetapi umatnya dibiarkan beribadah dalam kemiskinan yang sama.
Apakah populisme sungguh peduli pada rakyat, atau hanya mencintai suaranya? Apakah ia ingin mengangkat rakyat, atau sekadar memanjat di atas pundak mereka menuju kekuasaan?
Populisme mengaku anti-elit, tetapi begitu berkuasa langsung membentuk elit baru yang lebih rakus, lebih bising, tetapi tetap memakai bahasa kerakyatan. Katanya pro-rakyat, tetapi kebijakan tetap pro-kekuasaan. Katanya merakyat, tetapi jarang kelihatan di pasar - kecuali saat kampanye.
Populisme hidup dari kekecewaan rakyat, tetapi juga membuat rakyat semakin kecewa. Ia menjanjikan perubahan, tetapi justru membuat status quo semakin kuat.
Semakin sering berjanji untuk “kembali ke rakyat”, semakin jauh ia melangkah dari rakyat. Populisme itu seperti api unggun di tengah dinginnya sistem: hangat di awal, tetapi meninggalkan abu yang sama setelah pesta selesai.
Populisme bukan penyakit, tetapi gejala dari politik yang kehilangan makna. Ia lahir ketika rakyat putus asa mencari pemimpin yang tulus. Namun kalau dibiarkan tanpa akal sehat, populisme dapat berubah menjadi candu kolektif - meninabobokan kita dengan harapan palsu.
Mungkin yang kita butuhkan bukan pemimpin yang “merakyat”, tetapi rakyat yang sadar bahwa tidak semua yang berteriak “rakyat!” itu benar-benar di pihak rakyat.***








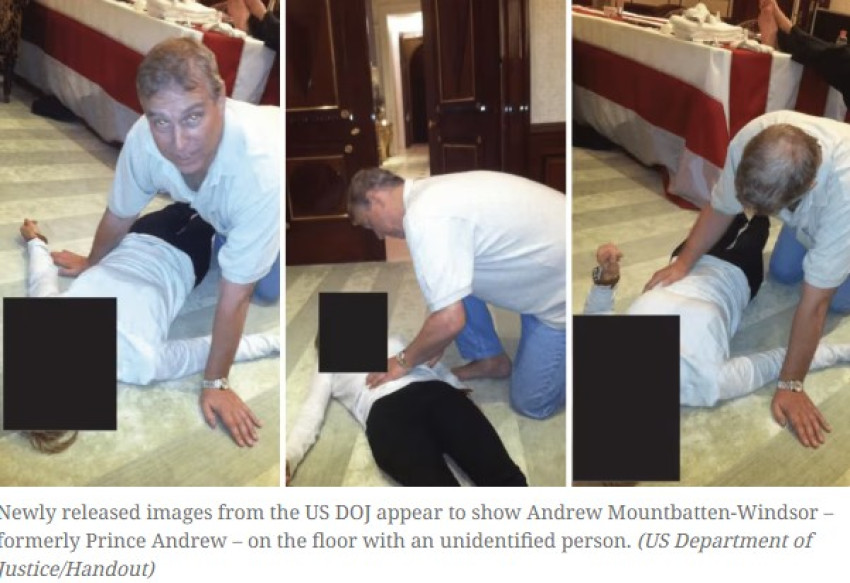
.jpeg)


