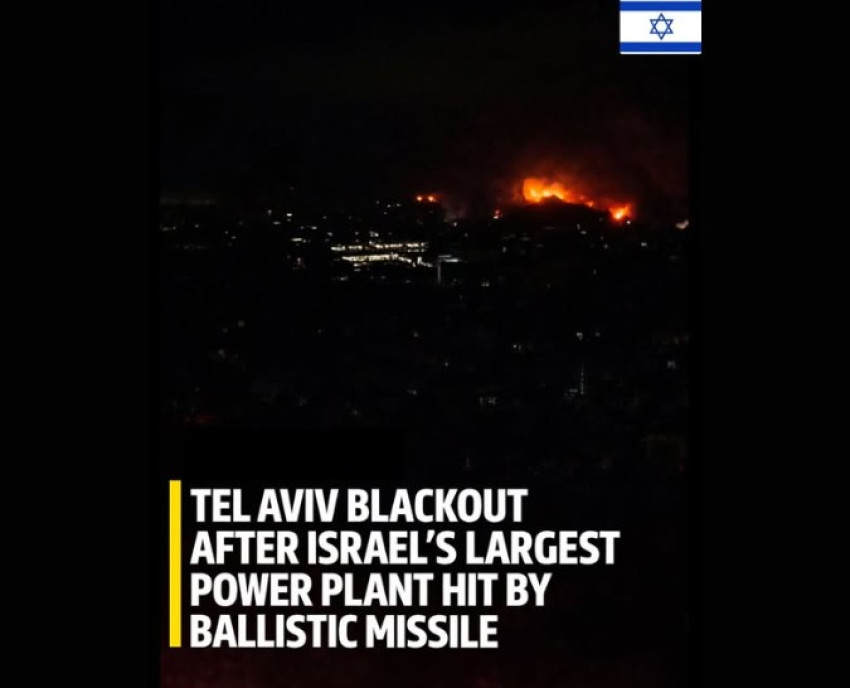Abdul Aziz: Fiqih Islam dan Keadilan
Oleh Dr. Abdul Aziz, M.Ag.
Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta
ORBITINDONESIA.COM – Perkara hukum yang menimpa Ira Puspadewi, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, beserta dua direktur lainnya, sempat menyita ruang pemberitaan nasional. Dari pemberitaan media sampai perbincangan publik, kasus ini mengundang banyak pertanyaan: tentang niat, tentang bukti, tentang proses hukum, dan tentang makna keadilan itu sendiri.
Vonis 4,5 tahun penjara sempat dijatuhkan untuk Ira. Namun kemudian, Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi, yang efeknya bukan hanya membuat Ira dan dua terdakwa (direktur ASDP lain yang dituduh korupsi) keluar dari penjara, tapi juga memulihkan harkat dan martabat mereka sebagaimana sebelum kasus ini bergulir.
Keputusan ini kembali menghidupkan diskusi publik mengenai prinsip keadilan substantif dalam sistem hukum dan dalam perspektif Islam.
Artikel ini tidak mengulas benar-salah sebuah perkara, tetapi menggali kaidah fikih dan ushul fikih yang relevan dengan polemik yang muncul, khususnya menyangkut persoalan niat, beban pembuktian, dan tuduhan tanpa dasar.
1. Kaidah Amal Bergantung pada Niat
Hadis Nabi yang sangat dikenal menyatakan: “Sesungguhnya amal itu bergantung pada niatnya.” (HR. Bukhari-Muslim).
Dalam ushul fikih, kaidah al-a‘mālu bin-niyyāt menjadi dasar bahwa nilai dan konsekuensi hukum suatu tindakan sangat ditentukan oleh motif pelaku. Ulama seperti Imam al-Ghazali dalam al-Mustashfā menegaskan bahwa suatu tindakan yang secara lahir tampak keliru tidak otomatis dihukumi sebagai maksiat tanpa niat jahat di baliknya.
Imam al-Qarafi dalam al-Furūq bahkan menyatakan bahwa niat adalah pemisah antara kesalahan administratif, kekeliruan teknis, dan kejahatan yang disengaja. Dalam konteks perkara publik, jika seseorang tidak terbukti memiliki niat memperkaya diri atau merugikan negara, fikih memandang hal itu sebagai unsur krusial yang tidak boleh diabaikan.
2. Beban Pembuktian dalam Syariat
Nabi SAW bersabda: “Bukti itu kewajiban pihak yang menuduh.”
Hadis ini menjadi landasan kaidah besar ushul fikih: “Al-bayyinah ‘alā al-mudda‘ī wa al-yamīn ‘alā man ankar.”
Imam Ibn Qudāmah dalam al-Mughnī menegaskan bahwa sanksi tidak boleh dijatuhkan kecuali atas dasar bukti yang kuat, konsisten, dan tidak menimbulkan syubhat (keraguan).
Dalam hukum Islam, keraguan sekecil apa pun dapat menggugurkan hukuman. Kaidah ini dikenal sebagai: “Idra‘ū al-hudūd bisy-syubuhāt.”
“Gugurkanlah hukuman ketika ada keraguan.”
Oleh karena itu, bila tidak ada bukti bahwa seseorang menerima uang atau keuntungan pribadi, maka dari sudut pandang fikih, proses penetapan kesalahan harus ekstra hati-hati. Islam tidak mengenal vonis berdasarkan asumsi, persepsi, atau tekanan publik.
3. Tuduhan Tanpa Dasar dalam Fikih Islam
Fikih memberi perhatian besar pada kehormatan manusia. Tuduhan tanpa bukti yang kuat termasuk dalam kategori al-buhtān (tuduhan dusta). Para ulama sepakat bahwa ini merupakan dosa besar.
Al-Qur’an memperingatkan: “Wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa.” (QS. al-Hujurat: 12).
Imam al-Māwardi dalam al-Ahkām as-Sulthāniyyah menyebutkan bahwa pejabat negara, termasuk aparat penegak hukum, wajib menjauhkan diri dari tuduhan yang tidak terverifikasi karena hal itu merupakan bentuk zulm— kezaliman yang mencoreng keadilan.
Dalam fikih, orang yang menuduh tanpa bukti sah dapat dikenai sanksi ta‘zīr, yakni hukuman pendisiplinan yang ditentukan pemerintah.
Prinsipnya jelas: menjaga nama baik seseorang adalah kewajiban moral dan hukum dalam Islam.
4. Maqashid Syariah: Keadilan Sebagai Tujuan Utama
Imam asy-Syathibi menjelaskan bahwa salah satu tujuan syariah adalah tegaknya keadilan dan hilangnya kezaliman. Keadilan tidak hanya terkait memberi hukuman berat bagi pelanggar, tetapi juga menjaga agar orang yang tidak bersalah tidak diperlakukan secara tidak adil.
Dalam banyak literatur klasik fikih, ditegaskan bahwa kekuasaan paling utama bukanlah menghukum, tetapi menegakkan kebenaran dan memulihkan yang terzalimi.
Negara berkewajiban mengoreksi apabila terbukti ada kekeliruan dalam proses hukum.
5. Rehabilitasi dan Makna Keadilan Substantif
Ketika vonis sudah dijatuhkan namun kemudian muncul keputusan rehabilitasi dari Presiden Prabowo, hal itu memunculkan makna lain tentang keadilan. Rehabilitasi adalah bentuk pemulihan nama baik, sebuah tindakan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga aspek moral, sosial, dan kemanusiaan.
Dalam kacamata fikih, tindakan pemulihan seperti ini sejalan dengan prinsip raf‘ al-mazhālim — menghapus kezaliman dan memulihkan hak orang yang dirugikan. Tindakan pemimpin yang memulihkan martabat seseorang ketika bukti-bukti tidak kokoh atau ketika terjadi kekeliruan prosedural merupakan bagian dari siyasah syar‘iyyah (kebijakan kepemimpinan demi kemaslahatan).
Penutup
Di tengah hiruk-pikuk kasus hukum yang menguras energi publik, keputusan rehabilitasi dari Presiden Prabowo tersebut di atas dapat dipandang sebagai upaya mengembalikan keadilan ke titik keseimbangannya. Bila proses hukum menimbulkan ruang-ruang keraguan, maka tugas pemimpin adalah memastikan bahwa keadilan bukan hanya tegak secara formal, tetapi juga secara substantif.
Keadilan dalam Islam tidak pernah semata-mata tentang menghukum; ia juga tentang memuliakan manusia, menjaga nama baik mereka, dan memperbaiki bila ada yang goyah.
Dalam konteks itu, keputusan rehabilitasi menjadi pengingat bahwa kekuasaan yang benar bukanlah kekuasaan yang menghukum tanpa ampun, melainkan kekuasaan yang berani mengoreksi, berani memulihkan, dan berani menegakkan kebenaran di atas kepastian, bukan prasangka.
Semoga langkah ini menjadi teladan, bahwa keadilan yang sejati adalah keadilan yang tidak hanya dibacakan di ruang sidang, tetapi juga dirasakan oleh hati nurani umat. ***