Syaefudin Simon: Pilkada Langsung Mahal? Mana Lebih Mahal: Suara Rakyat atau Suara Anggota Dewan?
Oleh Syaefudin Simon, Kolumnis Satupena Jakarta
ORBITINDONESIA.COM - Setiap lima tahun sekali, kalimat itu selalu diulang dengan nada prihatin yang sama: pilkada langsung itu mahal. Terlalu mahal, kata mereka.
Terlalu boros, terlalu ribut, terlalu banyak konflik, terlalu banyak amplop.
Maka muncullah solusi yang katanya rasional dan beradab: kembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan anggota dewan. Lebih murah. Lebih tertib. Lebih elitis—eh, efisien.
Pertanyaannya sederhana, tapi jarang dijawab jujur: yang mahal itu pilkadanya, atau demokrasinya?
Dalam logika para pengkritik pilkada langsung, biaya dicatat seperti laporan keuangan perusahaan. Spanduk, baliho, iklan, logistik, honor KPPS, pengamanan, sengketa. Semua dihitung. Semua dijumlah. Lalu disimpulkan: rakyat terlalu mahal untuk diberi hak memilih.
Demokrasi langsung dianggap kemewahan yang tak cocok bagi negara berkembang.
Namun ada satu pos biaya yang selalu hilang dari perhitungan: harga suara di ruang tertutup.
Jika pilkada langsung dinilai mahal karena melibatkan jutaan rakyat, lalu berapa biaya untuk “meyakinkan” puluhan atau ratusan anggota dewan? Apakah lebih murah? Atau justru lebih mahal, karena tarif suara naik drastis ketika pemilihnya sedikit dan kekuasaannya besar?
Dalam pemilihan oleh dewan, suara rakyat dipadatkan menjadi suara elite. Dari jutaan kepala menjadi puluhan kursi. Dari kampanye terbuka menjadi lobi tertutup. Dari janji program menjadi transaksi politik. Efisien, memang. Tapi efisiensi siapa?
Sejarah kita memberi pelajaran pahit. Saat kepala daerah dipilih oleh dewan, yang tumbuh bukan kepemimpinan, melainkan persekutuan. Kepala daerah terpilih bukan karena gagasan, tapi karena kesanggupan “berterima kasih”.
Maka APBD berubah fungsi: dari anggaran publik menjadi anggaran balas budi. Korupsi bukan anomali, melainkan sistem.
Ironisnya, biaya korupsi pasca-pemilihan hampir tak pernah dihitung sebagai “ongkos demokrasi”. Padahal, satu kepala daerah yang terjerat korupsi bisa menghabiskan ratusan miliar rupiah uang publik.
Jauh lebih mahal dibanding biaya satu pilkada langsung. Tapi karena kerugiannya tersebar dan tak kasatmata, ia tak masuk neraca.
Pilkada langsung memang gaduh. Rakyat berisik. Media sosial ribut. Hoaks berseliweran. Tapi kegaduhan itu justru tanda kehidupan politik. Demokrasi memang tidak rapi. Ia berisik karena melibatkan banyak suara—termasuk suara yang tak disukai elite.
Yang benar-benar mahal bagi sebagian orang bukan biaya logistik, melainkan ketidakpastian. Dalam pilkada langsung, rakyat bisa membangkang. Bisa memilih di luar skenario. Bisa menghukum petahana. Bisa salah—dan itu hak mereka. Ketidakpastian inilah yang dianggap risiko tinggi.
Sebaliknya, pemilihan oleh dewan menawarkan kepastian. Lebih mudah diprediksi. Lebih mudah diatur. Lebih mudah diamankan. Dan tentu saja, lebih mudah “dikondisikan”.
Maka wacana “pilkada langsung mahal” sesungguhnya bukan soal anggaran, melainkan soal siapa yang dipercaya. Apakah kita percaya rakyat—yang suaranya murah tapi jumlahnya banyak? Atau kita percaya segelintir anggota dewan—yang suaranya sedikit tapi harganya mahal?
Jika demokrasi diukur hanya dari biaya, maka yang termurah adalah diktator. Tak perlu pemilu. Tak perlu kampanye. Tak perlu suara rakyat. Tapi kita tahu, harga yang harus dibayar setelahnya jauh lebih mahal: kebebasan, keadilan, dan masa depan.
Jadi, mari jujur. Yang dipersoalkan bukan pilkada langsungnya, melainkan keberanian untuk menerima pilihan rakyat. Dan bagi sebagian elite, suara rakyat memang terlalu mahal—bukan secara uang, tapi secara kekuasaan.
So, benarlah adagium yg menyatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara Tuhan jelas amat mahal. Dan yang memanipulasi suara Tuhan bersiaplah menerima azab yang mengerikan. Dari kurap di muka yang menjalar kemana-mana yang tak bisa disembuhkan, sampai gila memikirkan nasib anak yang akan diseret rakyat! ***





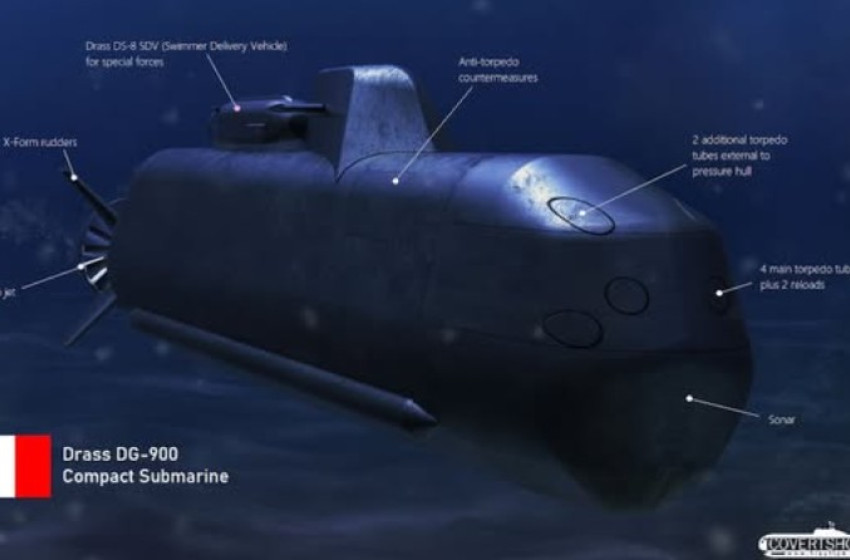



.jpeg)


