Menyuarakan Luka Sosial Lewat Puisi Esai
(Catatan Koordinator Lomba Menulis Esai – Festival Puisi Esai ke-3)
Oleh Mila Muzakkar
Selepas sahur, saya membuka Instagram. Niat hati mencari hiburan sejenak, namun yang muncul adalah video seorang anak laki-laki dengan pakaian lusuh mengais beras dari truk beras. Beberapa orang terlihat lalu-lalang menurunkan karung beras dari truk, dan anak itu “nyempil” di antaranya, menyapu sisa beras yang terjatuh dari karung ke tanah, lalu ia masukkan ke sebuah wadah.
Anak itu biasa saja. Tak ada kesedihan yang tampak di wajahnya. Bisa jadi, ini sesuatu yang memang biasa ia lakukan. Bisa jadi bukan hanya dia, tapi masih banyak anak-anak lainnya yang melakukan hal serupa. Tapi mereka tak tercatat, tak terdata, tak terhitung.
Catatan yang kita baca mengatakan tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami tren penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2025 turun menjadi 8,25 persen (BPS, 2025). Atau berita lainnya, Kementerian Kesehatan memamerkan prevalensi stunting di Indonesia berhasil turun menjadi 19,8% di tahun 2024, dari sebelumnya 21,5% pada 2023.
Sayangnya, data-data itu gagal membaca, alih-alih memahami, fakta di lapangan. Di negeri yang konon kaya sumber daya alam, negara yang berdasarkan survei adalah paling dermawan, masih ada anak-anak yang harus menutup mata: berpura-pura membedakan mana beras, mana tanah. Keduanya ia makan bersamaan, demi harapan hidup yang lebih baik.
Pada titik itulah puisi esai hadir. Sebuah cara mengekspresikan kegelisahan yang sangat dalam dan emosional terhadap masalah-masalah sosial yang melukai. Jika anak itu harus makan nasi campur tanah, semata-mata bukan kesalahan orang tuanya, apalagi anak itu sendiri. Tapi ini kerja sistem yang tidak berpihak, tidak adil, dan hilang empati.
Puisi esai adalah jalan perjuangan lewat kata-kata yang estetik. Ia bukan kata-kata kosong, bukan sekadar opini yang netral, tapi memiliki posisi yang jelas. Puisi esai dengan tegas berdiri di samping kelompok rentan, yang paling sering menjadi korban: orang-orang yang didiskriminasi, dipinggirkan, dikerasi, dihilangkan, bahkan dibunuh, karena status sosialnya lebih rendah dari mereka yang berkuasa. Karena itu, puisi esai adalah jalan perjuangan isu-isu kemanusiaan.
Atas dasar itulah, Festival Puisi Esai ketiga—yang baru saja selesai digelar—mengadakan lomba menulis esai dengan tema “Mengapa Puisi Esai Tepat Suarakan Luka Sosial”. Saya bersyukur diamanahkan menjadi koordinator lomba ini, sebab itu berarti saya diminta mengajak sebanyak-banyaknya orang, terutama generasi muda, untuk ikut menyuarakan dan memperjuangkan isu-isu sosial-kemanusiaan.
Namun, itu bukan pekerjaan mudah. Harus saya akui, puisi esai belum banyak dikenal di kalangan luas, apalagi anak-anak muda. Tapi bukankah sesuatu yang besar memang perlu perjuangan yang besar pula? Selama kurang lebih satu bulan, saya dan tim panitia lainnya berupaya cukup keras, melakukan macam-macam cara untuk mengajak orang-orang mengikuti lomba menulis esai ini. Dari mengadakan serial live Instagram untuk menjelaskan tentang lomba ini sedetail mungkin, mengadakan Zoom untuk briefing teknis kepada calon peserta lomba, hingga “jemput bola” ke ruang-ruang publik.
Saya jadi membayangkan bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW saat menyebarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Penuh liku dan caci. Tapi setelahnya, Islam berjaya dan hidup dalam hati setiap umat Muslim.
Tantangan lomba ini memang cukup berlapis. Berbeda dengan menulis esai pada umumnya, menulis esai dengan tema mengapa puisi esai tepat untuk menyuarakan luka sosial, membutuhkan beberapa tahap. Tahap pertama, calon peserta lomba harus memahami apa itu puisi esai dan bagaimana cara menuliskannya. Kedua, calon peserta harus memahami apa dan bagaimana yang dimaksud dengan luka sosial. Setelah itu, barulah mereka bisa menulis esai dengan tema tersebut.
Tantangan lainnya, di saat yang sama—masih dalam rangkaian Festival Puisi Esai ke-3—juga sedang berlangsung lomba menulis puisi esai dengan tema Kembali Mencintai Bumi Setelah Sumatera Terluka. Alhasil, banyak peserta yang mengalami kebingungan antara kedua lomba itu. Beberapa peserta mengirim tulisan puisi esai ke panitia lomba menulis esai. Pun sebaliknya.
Namun perjuangan itu terbayar juga. Sebanyak 819 orang dari berbagai daerah di Indonesia telah mengirimkan naskah esai. Sekarang, giliran panitia dan juri yang bingung dan capek menyeleksi banyaknya naskah yang masuk, hehe…
Proses seleksi berlangsung tiga lapis. Dimulai dari seleksi administrasi oleh admin, lalu dilanjutkan oleh penilaian juri. Setelah melalui rapat-rapat dan perenungan para juri (Nia Samsihono, Elza Peldi Taher, dan Rosadi Jamani), terpilihlah juara 1, 2, 3 (dengan hadiah masing-masing 10.000.000, 5.000.000, dan 3.000.000) dan 24 pemenang pilihan lainnya (masing-masing mendapatkan hadiah 500.000).
Juara 1 diraih oleh Hening Nugroho, S.Fil., dari Yogyakarta, dengan judul tulisan: “Puisi Esai sebagai Bahasa Luka Sosial: Antara Afek, Ingatan, dan Etika Representasi”. Juara 2 adalah Dr. Tamrin, M.Pd., dari Sulawesi Selatan, dengan judul tulisan: “Dialektika Fakta dan Emosi: Verifikasi Penderitaan dan Audit Moral dalam Puitika Puisi Esai”. Sementara juara 3 datang dari Cimahi, Erni Hernawati, dengan judul tulisan: “Representasi Penderitaan Perempuan dalam Krisis Bencana: Analisis Potensi Puisi Esai sebagai Bahasa Kemanusiaan”.
Saya bersyukur hampir 1000 orang mengikuti lomba menulis esai ini. Ini bukan hanya tentang lomba dan hadiah, tapi tentang seberapa banyak dan seberapa luas luka sosial itu disuarakan, sehingga mampu menembus dinding-dinding hati yang lama tertutup oleh keserakahan, untuk terbuka lebih berempati pada kemanusiaan.

.jpg)







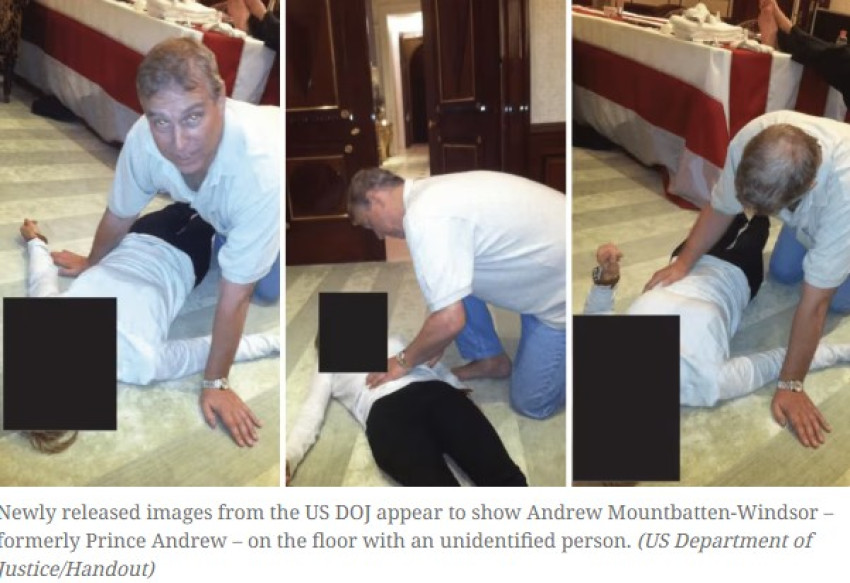
.jpeg)

