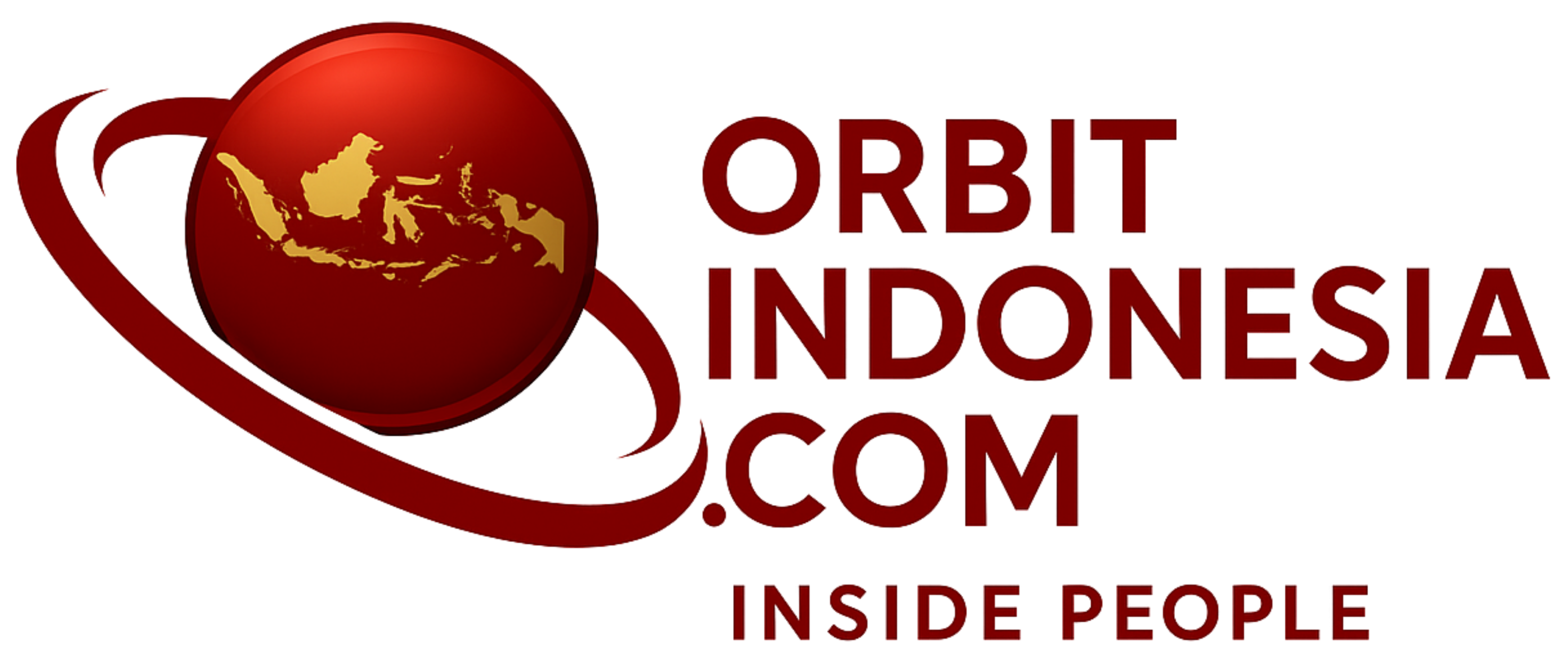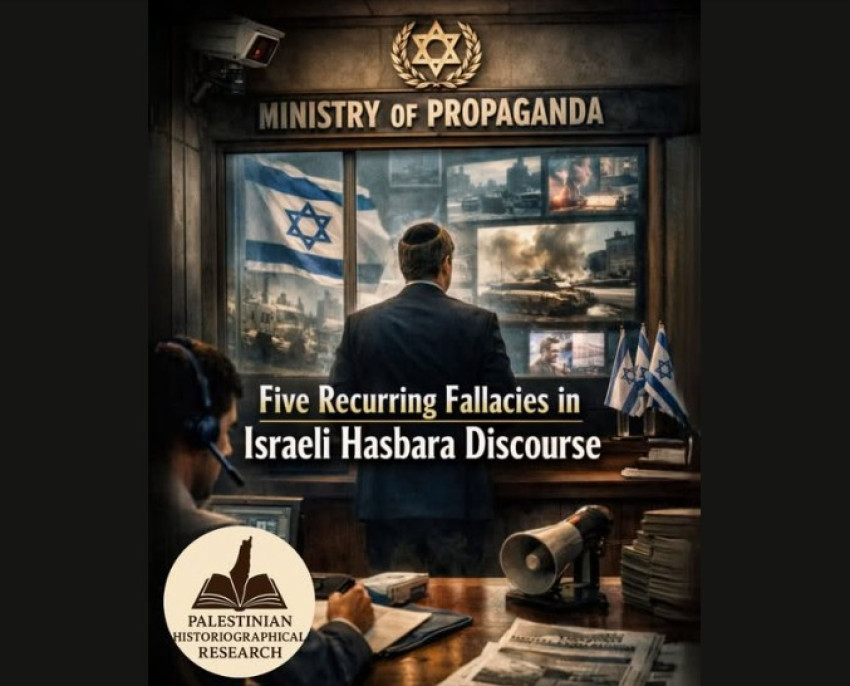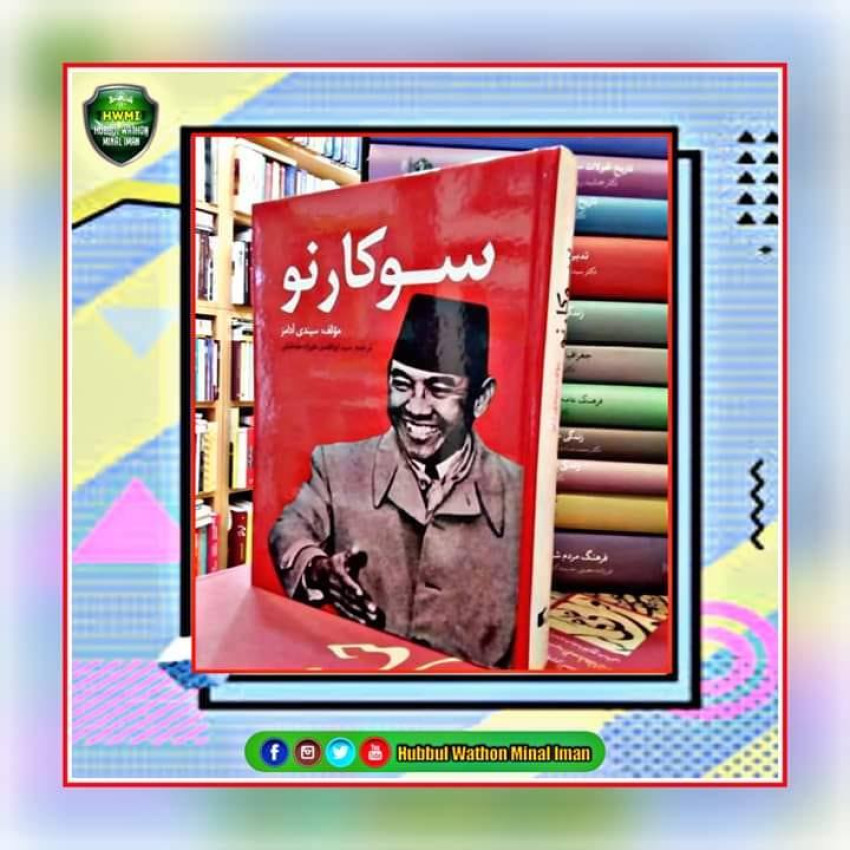Patahnya Tangan Kartini yang Memegang Obor
ORBITINDONESIA.COM - Pengantar dari Denny JA untuk Buku Puisi Esai Gol A Gong: Tentang Perempuan, Surat Berdarah untuk Kartini.
“Patungmu sudah berdiri 50 tahun di sana.
Obor menyala di tangan kanan, pertanda
semangatmu menyuarakan hak perempuan.
Dan gadis kecil di tangan kirimu,
mengantarkan ke masa depan.
Hujan menggila. Kulihat tangan kananmu
yang memegang obor patah. Aku merasa itu sebagai
guratan nasib perempuan yang kau perjuangkan
juga patah, tak kuasa melawan kekuatan para lelaki.”
Kutipan puisi Gol A Gong tentang patahnya tangan Kartini yang memegang obor adalah undangan imajinasi yang getir.
Kita seakan dibawa ke ruang potret sedih kaum perempuan.
Fakta sosial menegaskan kengerian itu: Data Komnas Perempuan mencatat, sepanjang tahun 2024 terdapat 34.682 perempuan menjadi korban kekerasan.
Dari jumlah itu, kekerasan seksual menempati posisi tertinggi dengan 15.621 kasus, disusul kekerasan psikis (12.878 kasus) dan kekerasan fisik (11.099 kasus).
Apakah pendidikan di rumah dan sekolah telah gagal? Atau agama belum berhasil memberikan pemahaman?
Kuat sekali kalimat yang dijadikan tagline buku ini:
“Kita menyakiti perempuan yang akan melahirkan ibu.”
Kalimat ini bukan sekadar seruan, melainkan vonis moral atas wajah bangsa.
-000-
Buku berjudul: Tentang Perempuan: Surat Berdarah untuk Kartini karya Gol A Gong memuat 15 puisi esai.
Setiap puisi berbentuk surat kepada Kartini. Namun sesungguhnya itu adalah jeritan bagi perempuan Indonesia yang menjadi korban kekerasan.
Bukan kumpulan karya fiksi belaka, buku ini mosaik luka bangsa. Isinya lahir dari kisah nyata yang pernah menggemparkan media: Marsinah, buruh pabrik yang disiksa dan dibunuh.
Juga kisah Renata, sarjana cum laude yang tewas di perjalanan pulang. Soal santriwati korban kiai.
Diceritakan juga kisah penjual gorengan yang cita-citanya terkubur; hingga gadis kecil yang diperkosa lalu jasadnya dimasukkan ke karung sawit.
Benang merahnya: tubuh perempuan masih terus menjadi medan kekerasan, baik di ruang publik, di rumah sendiri, bahkan di bawah naungan agama.
Gol A Gong mengolah tragedi itu menjadi puisi esai dengan gaya kontemplatif, penuh darah-darah metaforis. Seolah berita kriminal yang dingin diubah menjadi ratapan puitis yang membakar nurani.
-000-
Tiga Gagasan Utama Buku
1. Kekerasan terhadap Perempuan adalah Luka Kolektif Bangsa
Ketika seorang perempuan diperkosa, dipukul, atau dibunuh, tragedi itu sering dianggap sekadar urusan personal atau kriminal semata.
Padahal, luka itu tidak berhenti pada tubuh sang korban. Luka itu menjalar ke jantung bangsa.
Marsinah, misalnya, bukan hanya seorang buruh jam; ia adalah lambang dari suara yang dibungkam karena keberaniannya menuntut keadilan.
Saat tubuhnya diperkosa dan dihancurkan, yang sebenarnya tercabik bukan hanya jasad seorang buruh, melainkan moral seluruh masyarakat yang membiarkannya.
Gol A Gong melalui puisinya mengingatkan kita: setiap kekerasan terhadap perempuan adalah pengkhianatan terhadap rahim peradaban.
Perempuan itu sumber kehidupan. Mereka yang mengandung, melahirkan, membesarkan. Ketika mereka dibiarkan menderita, bangsa ini menorehkan luka pada masa depannya sendiri.
Itulah sebabnya gagasan ini penting: ia memaksa kita berhenti menormalisasi kekerasan sebagai “kasus biasa.”
Ia mengajak melihat bahwa membiarkan perempuan disakiti sama dengan membiarkan bangsa menulis nisan bagi dirinya sendiri.
Setiap darah perempuan yang tumpah, adalah darah sejarah yang menodai bendera kita.
2. Suara Ibu dan Anak Perempuan sebagai Kesaksian Moral
Ada kekuatan lembut yang sering kita abaikan: suara seorang ibu, doa yang sederhana, nasihat yang lahir dari cinta.
Dalam puisi Nasihat Ammak Terbawa Mati, Renata mengabaikan kata-kata ibunya. Ia pulang dengan travel, dan di sanalah maut menjemputnya.
Tragisnya, yang tersisa bukan hanya tubuh yang tak bernyawa, tetapi gema suara sang ibu: “Jangan lupa hati-hati, Nak.” Nasihat itu berubah menjadi ratapan terakhir, cahaya yang justru makin terasa saat sudah terlambat.
Kearifan Bugis—sipakatau (saling memanusiakan), sipakalebbi (saling menghormati), dan sipakainge (saling mengingatkan)—dihadirkan Gol A Gong sebagai akar budaya yang seharusnya menjadi pagar moral.
Tetapi pagar itu runtuh oleh kebiadaban. Dari situlah kita belajar: doa dan suara perempuan, baik ibu maupun anaknya, adalah kesaksian moral bangsa.
Ia menunjukkan bahwa di balik darah yang tumpah, selalu ada cinta yang lebih besar. Itu cinta seorang ibu, atau harapan seorang anak.
Jika bangsa ini terus menutup telinga dari suara-suara itu, maka ia sedang kehilangan arah moralnya sendiri.
3. Patriarki sebagai Neraka yang Menyamar
Patriarki tidak selalu datang dalam bentuk kekerasan fisik di jalanan. Kadang ia datang dalam rupa yang jauh lebih menakutkan: wajah seorang kiai, guru, atau suami yang seharusnya melindungi.
Puisi Kiai dan Surga Santriwati adalah contoh paling jelas. Di sana, seorang figur suci, yang seharusnya menuntun ke jalan Tuhan, justru memanfaatkan otoritas untuk merusak tubuh dan jiwa santriwati.
Di balik jubah agama, ternyata ada sorot mata iblis.
Inilah mengapa patriarki disebut “neraka yang menyamar.” Ia tidak selalu ditandai dengan amarah atau ancaman; kadang ia datang dengan janji surga.
Rumah pun, yang seharusnya menjadi tempat aman, bisa menjelma penjara ketika seorang anak diperkosa oleh saudaranya sendiri.
Puisi esai ini membongkar akar terdalam dari kekerasan: struktur yang timpang. Selama patriarki masih hidup, perempuan tidak pernah benar-benar aman—di jalan, di rumah, bahkan di masjid.
Gol A Gong menuliskan ini dengan murka yang jernih, agar kita sadar. Membiarkan patriarki itu sama dengan membiarkan api neraka berkeliaran di dunia, menghanguskan generasi demi generasi.
-000-
Membaca Gol A Gong, Terbayang The World’s Wife
Membaca Tentang Perempuan, saya teringat The World’s Wife karya Carol Ann Duffy (Picador, 1999). Duffy menuliskan kembali mitologi dan sejarah dari perspektif perempuan yang selama ini dibisukan: istri Midas, istri Sigmun Freud, hingga istri Charles Darwin.
Jika Duffy menggunakan ironi dan satire, Gol A Gong memilih darah dan air mata.
Namun keduanya bertemu dalam kesadaran yang sama: sejarah tidak pernah lengkap tanpa suara perempuan.
Duffy menulis:
“Gagang pintu berubah emas. Aku duduk dalam kegelapan.” (Mrs. Midas)
Itu ejekan getir tentang kerakusan laki-laki yang menjerat istri dalam kesepian.
Gol A Gong menulis:
“Pisau, obeng, tali rapia… adalah ritual terakhir setelah menikmati tubuh perempuan.”
Itu tuduhan telak pada budaya yang membiarkan perempuan terus ditindas.
Kedua karya ini, meski lahir dari belahan dunia berbeda, sama-sama menegaskan bahwa sastra adalah ruang di mana suara yang bisu bisa hidup kembali.
Selain Duffy, karya Sylvia Plath dalam Ariel (Faber and Faber, 1965) juga relevan. Plath menulis dengan intensitas emosional yang menelanjangi luka batin perempuan modern.
Jika Plath mengisahkan perang internal seorang perempuan melawan depresi dan patriarki domestik, Gol A Gong mengisahkan perang eksternal perempuan Indonesia melawan kekerasan yang nyata di jalanan, rumah, bahkan pesantren.
-000-
Buku Gol A Gong Surat Berdarah untuk Kartini, sesungguhnya adalah surat untuk kita semua.
Tangan Kartini yang patah memegang obor di tengah hujan adalah simbol zaman kita. Itu metafor perjuangan emansipasi yang belum selesai.
Kumpulan puisi esai ini Gol A Gong, adalah doa, jeritan, sekaligus tamparan. Ia menuntut kita bertanya: sampai kapan kita membiarkan obor Kartini tetap patah?
Apakah kita akan membiarkan patung itu sekadar monumen mati? Ataukah kita berani menyambung kembali obornya—dengan keberanian, cinta, dan keadilan—agar cahaya Kartini kembali menyala, menerangi jalan bangsa?
Selama darah perempuan masih tumpah di tanah ini, sejatinya bangsa kita sedang menulis catatan untuk kuburnya sendiri.
Tetapi jika kita berani menjahit luka itu, maka puisi, sejarah, dan aksi nyata bisa menjadi obor baru: obor yang tak lagi patah, obor yang menyala untuk peradaban.
Gol A Gong tidak hanya menulis puisi esai, tetapi merajut counter-narrative terhadap sejarah yang dibungkam.
Dengan menggabungkan data statistik, narasi korban, dan refleksi filosofis, karyanya menjadi testimonio-bentuk sastra perlawanan yang mengubah korban menjadi subjek pencerita.
Di sini, estetika bukan sekadar alat, melainkan senjata: setiap metafor adalah serpihan cermin yang memantulkan wajah kolektif kita yang retak.
Dengan menolak dikotomi "fiksi vs fakta," ia menciptakan ruang di mana puisi esai menjadi pengadilan moral, dan setiap pembaca adalah juri yang terdakwanya: keadilan itu sendiri.***
Jakarta, 16 Agustus 2025
Referensi
• Carol Ann Duffy, The World’s Wife, Picador, 1999.
-000-
Ratusan esai Denny JA soal filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, politik demokrasi, sejarah, positive psychology, catatan perjalanan, review buku, film dan lagu, bisa dilihat di FaceBook Denny JA’s World