Refleksi Buku 'The Bottom Line' Karya Georgie Lee, Split Faith Syndrome
Oleh Albertus M. Patty
ORBITINDONESIA.COM - Di tengah kesibukan kota-kota besar Indonesia, kita menyaksikan realitas yang ambigu. Pada satu sisi, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang sangat religius, dengan doa di mana-mana, rumah ibadah di setiap sudut, dan ritual keagamaan yang megah. Pada sisi lain, tingkat korupsi di Indonesia termasuk tinggi.
Transparansi Internasional menyebutkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mendapat skor 37. Peringkat Indonesia 99 dari 180 negara. Peringkat korupsi kita di Asean bahkan lebih buruk dari Timor Timur. Artinya, kita rajin beribadah, tetapi lalai menegakkan kejujuran dan keadilan. Kita tekun berdoa, tetapi doyan kompromi terhadap kebenaran.
Split Faith Syndrome
Fenomena ambiguitas di atas menunjukkan bahwa banyak orang Indonesia, termasuk para pebisnis dan politisi, sedang mengalami Split Faith Syndrome, yaitu sebuah kondisi di mana iman dan kehidupan berjalan di dua jalur yang tak bersinggungan.
Istilah “Split Faith Syndrome” dipopulerkan oleh Lausanne Movement, sebuah gerakan global yang lahir pada tahun 1974. Gerakan ini diprakarsai oleh Billy Graham dan John Stott. Tujuannya untuk menjalin kembali hubungan antara injil dan kehidupan publik.
Dualisme
Dalam buku 'The Bottom Line', Georgie Lee menegaskan bahwa bisnis bukanlah wilayah sekuler yang terpisah dari iman. Ia menulis bahwa “profit is not evil, but profit without purpose is.”
Pernyataan ini menembus ke jantung persoalan spiritualitas modern: manusia sering menempatkan Tuhan di gereja, tetapi tidak di kantor; dalam doa, tetapi tidak di rapat dewan direksi; di liturgi, tetapi tidak dalam strategi bisnis.
Kita hidup dalam dualisme, membagi dunia menjadi “yang rohani” dan “yang duniawi.” inilah penyebab Split Faith Syndrome. Padahal, baik yang rohani maupun yang jasmani harus saling menjiwai. Dunia bisnis seharusnya menjadi vocation, bukan occupation. Bisnis adalah panggilan untuk melayani dan menjadi berkat, bukan hanya alat memperkaya diri.
Persoalannya lebih complicated di Indonesia. Kesadaran membangun bisnis sebagai vocation sering tergerus oleh sistem ekonomi yang dikuasai oleh relasi patronase, kekuatan oligarki yang mencengkram sendi ekonomi, ketakutan kehilangan posisi, dan budaya kompromi moral.
Iman menjadi privat, sementara urusan bisnis dijalankan dengan logika “asal untung” atau “asal aman.” Inilah penyebab mengapa korupsi terus meninggi, dan mengapa Gini ratio Indonesia sebesar 0,381, artinya tingkat kesenjangan yang kaya dan yang miskin cukup lebar. Distribusi pendapatan tidak merata. Politik dan bisnis berjalan tanpa moral, tanpa tanggungjawab kemanusiaan.
Inilah yang menjelaskan mengapa kita bisa sangat religius secara ritual, tetapi tidak etis secara sosial. Iman berhenti di altar, tidak pernah melangkah ke pasar.
Padahal, seperti ditunjukkan Lee, the true bottom line bukanlah laba finansial, melainkan keberhasilan moral, yakni sejauh mana bisnis, kekuasaan, dan kerja kita menghadirkan nilai-nilai Kerajaan Allah: kejujuran, keadilan, kasih, dan kesejahteraan bersama.
Butuh Spiritualitas Sosial
Split Faith Syndrome membuat iman kita kehilangan kekuatan transformasinya. Kita berdoa untuk bangsa yang lebih adil, tetapi menutup mata terhadap praktik ketidakadilan di sekitar kita. Kita memuji Tuhan dengan bibir, tetapi menolak menerapkan nilai kebenaran dalam transaksi. Kita ingin berkat, tetapi lupa bahwa berkat sejati tidak pernah datang melalui ketidakjujuran.
Yang dibutuhkan Indonesia bukan hanya personal spirituality, ekspresi iman yang emosional, mistik, dan pribadi, tetapi juga social spirituality, yaitu spiritualitas yang mengintegrasikan iman dengan seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Iman yang tidak hanya membuat seseorang lebih saleh di hadapan Tuhan, tetapi juga lebih adil, jujur, dan bertanggung jawab di hadapan sesama.
Ketika iman dan bisnis bersatu, pekerjaan menjadi ibadah, perusahaan menjadi ladang pelayanan, dan keputusan bisnis menjadi kesempatan untuk menghadirkan nilai-nilai Kerajaan Allah di bumi. Dunia bisnis pun berubah menjadi arena kesaksian iman. Avodah, dalam bahasa Ibrani, yang artinya bekerja menjadi ibadah, tempat di mana kebenaran, kasih, dan keadilan bertemu.
Panggilan kita bukanlah untuk semakin banyak beragama secara ritual, tetapi semakin beriman secara integral. Sebab iman sejati bukanlah yang terpisah dari dunia, melainkan yang menerangi dunia. Dan mungkin di situlah, di meja kerja, di ruang rapat, di pasar, di kebijakan publik, Tuhan sedang menunggu kita untuk menyembahNya dengan cara yang baru: melalui integritas, keadilan, dan kasih yang hidup.
Bandung, 31 Oktober 2025.***

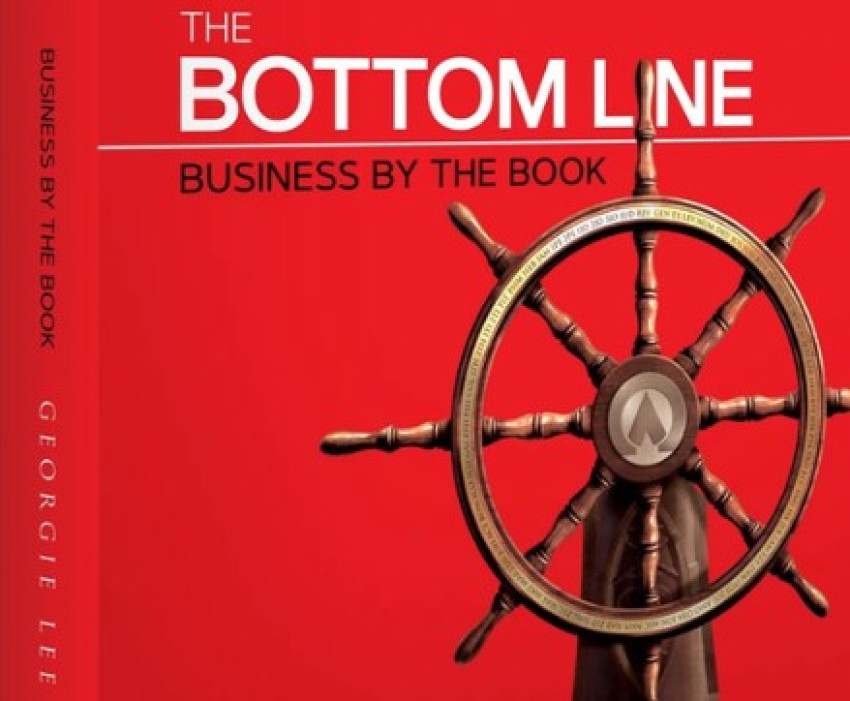

.jpg)








