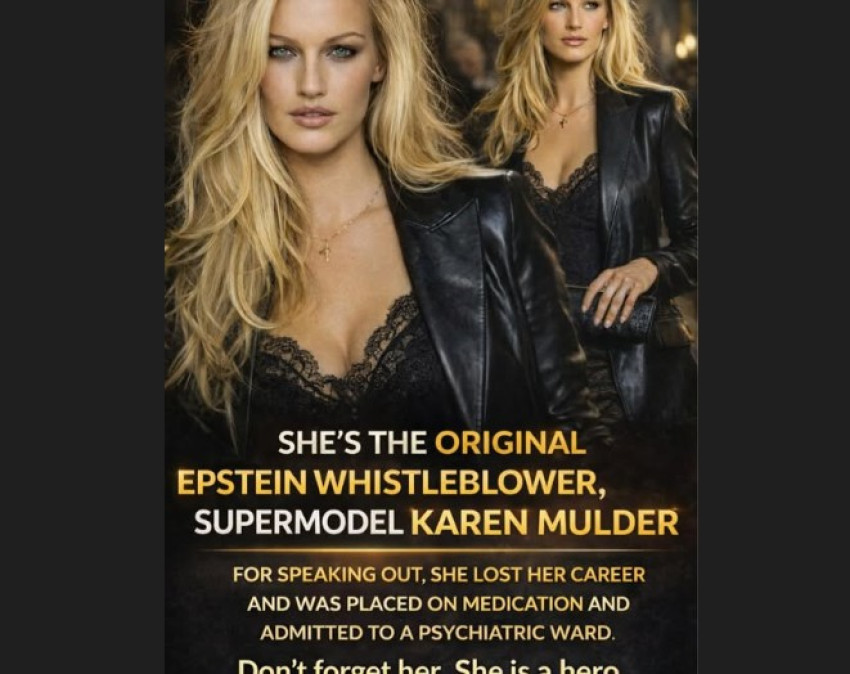Sherly Tjoanda, Kepemimpinan Perempuan yang Membumi
Tidak semua pemimpin lahir dari ambisi politik. Sebagian justru tumbuh dari keputusan sederhana: untuk tetap hadir ketika keadaan tidak mudah. Sherly Tjoanda menjalani kepemimpinannya dengan cara itu, pelan, terukur, dan berpijak pada pengalaman hidup yang membentuk empatinya.
Nama Sherly Tjoanda dikenal publik luas setelah Pilkada 2024. Ia maju menggantikan mendiang suaminya, Benny Laos, yang wafat dalam kecelakaan saat masa kampanye. Keputusan itu datang di tengah duka, pada waktu ketika sebagian orang memilih berhenti. Sherly memilih sebaliknya: melanjutkan. Bukan dengan retorika emosional, tetapi dengan keyakinan yang pelan dan konsisten bahwa amanah yang telah disematkan pada sebuah perjuangan tidak boleh terhenti oleh tragedi.
Latar belakangnya bukan politisi karier. Sherly tumbuh dari dunia usaha dan kerja sosial. Ia terbiasa mengelola organisasi, mendengar kebutuhan masyarakat, dan bekerja di balik layar. Pengalaman itu membentuk cara pandangnya: kepemimpinan bukan tentang sorotan, melainkan tentang sistem yang bekerja. Ketika ia akhirnya dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara periode 2025–2030, publik melihat sosok yang tenang, terukur, dan tidak tergesa-gesa membangun citra.
Yang membuat Sherly menarik bukan semata statusnya sebagai gubernur perempuan pertama di Maluku Utara, tetapi cara ia menempatkan diri. Ia tidak menjadikan identitas sebagai panggung, melainkan sebagai tanggung jawab.
Dalam banyak kesempatan, Sherly berbicara tentang pendidikan yang lebih mudah diakses, layanan kesehatan yang manusiawi, dan pembangunan yang menyentuh pulau-pulau kecil wilayah yang kerap tertinggal dalam narasi besar pembangunan.
Di mata banyak warga, gaya kepemimpinan Sherly Tjoanda kerap disebut “slay” bukan dalam arti glamor atau penuh sensasi, melainkan sebagai simbol kepercayaan diri yang tenang dan elegan. Ia hadir tanpa sikap menggurui, berbicara tanpa meninggikan suara, dan memimpin tanpa jarak yang kaku. Cara Sherly bertemu masyarakat duduk sejajar, mendengar lebih dulu, dan merespons dengan bahasa yang sederhana, membuatnya terasa dekat. Kedekatan itu bukan dibangun lewat pencitraan, melainkan tumbuh dari kebiasaan panjangnya bekerja di ruang sosial. Di tengah lanskap politik yang sering riuh, pendekatan ini memberi kesan kuat: kepemimpinan tidak selalu harus lantang untuk bisa dirasakan.
Sherly juga hadir sebagai simbol kepemimpinan inklusif. Di provinsi yang beragam secara agama dan budaya, ia menekankan kerja sama lintas batas. Tidak ada diksi berlebihan, tidak ada janji yang terdengar muluk. Yang ada adalah bahasa kerja: tentang tata kelola, kolaborasi, dan keberlanjutan. Ia memahami bahwa Maluku Utara bukan sekadar potensi sumber daya, tetapi rumah bagi masyarakat yang ingin didengar.
Dalam keseharian, Sherly dikenal tidak berjarak. Ia datang ke masyarakat dengan sikap mendengar lebih dulu. Barangkali karena ia tahu, kehilangan mengajarkan satu hal penting: manusia tidak selalu membutuhkan pemimpin yang paling lantang, tetapi yang paling hadir. Kepemimpinannya tumbuh dari empati yang nyata, bukan yang diproduksi untuk kamera.
Di tengah politik yang sering penuh sorotan, Sherly Tjoanda menawarkan nada lain. Tenang, fokus, dan bekerja. Ia menginspirasi bukan karena dramanya, melainkan karena keberaniannya mengambil tanggung jawab pada saat yang tidak mudah. Dari Maluku Utara, Sherly menunjukkan bahwa kepemimpinan bisa lahir dari keteguhan hati, dan bahwa melanjutkan, dalam sunyi sekalipun, adalah bentuk keberanian yang paling dewasa.

.jpeg)