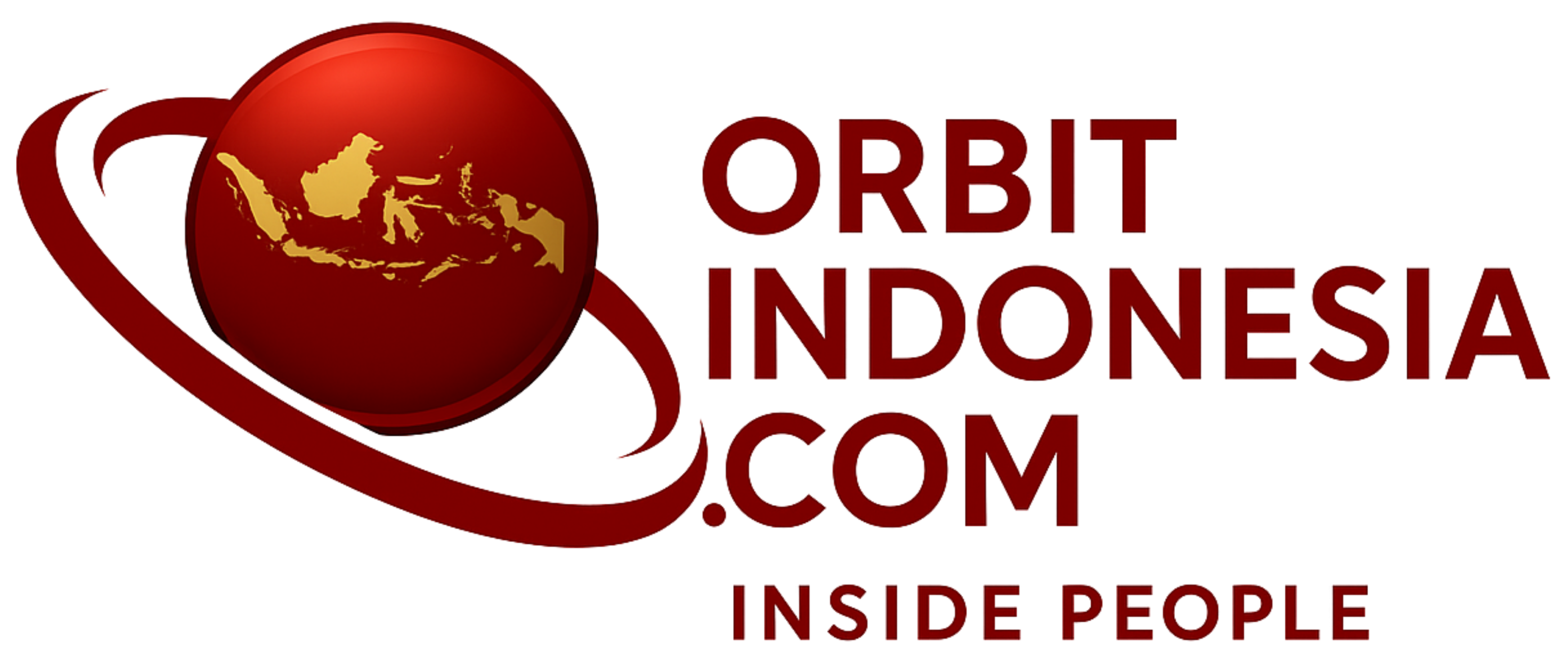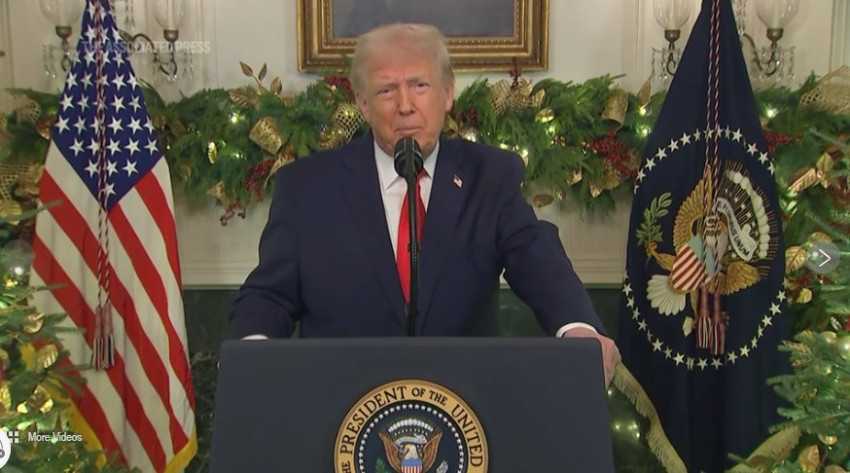Satrio Arismunandar: Industri Hulu Migas, Ketahanan Energi, dan Dilema SKK Migas
Oleh Satrio Arismunandar
ORBITINDONESIA.COM - Di tengah gempuran wacana transisi energi bersih dan ambisi Net Zero Emission, industri hulu minyak dan gas bumi Indonesia masih bekerja dalam diam, menopang kebutuhan energi harian negeri ini. Faktanya, saat ini dari dapur rumah tangga hingga pabrik baja, denyut hidup Indonesia masih banyak bergantung pada energi fosil.
Namun di balik konsistensi itu, terhampar tantangan besar: produksi menurun, cadangan menipis, investasi melemah, dan birokrasi belum lincah. Di titik genting itulah SKK Migas—lembaga pengelola kegiatan hulu migas—berdiri di garis depan menjaga ketahanan energi nasional.
Masalah paling mendasar adalah produksi minyak bumi Indonesia terus menurun. Jika pada tahun 1995 Indonesia masih mampu memompa lebih dari 1,5 juta barel per hari, kini angka itu menyusut drastis menjadi sekitar 560 ribu barel per hari. Sementara konsumsi domestik, terutama bahan bakar transportasi dan industri, terus meningkat.
Artinya, setiap tahun Indonesia harus menambal kebutuhan energi lewat impor minyak mentah dan BBM—sebuah kondisi yang menekan neraca perdagangan dan nilai tukar.
“Masalah utamanya bukan sekadar produksi turun, tapi eksplorasi baru yang stagnan,” ujar seorang pejabat SKK Migas dalam satu forum di Jakarta. “Kita sudah terlalu lama hidup dari lapangan tua.”
SKK Migas menghadapi tantangan besar karena cadangan migas baru jarang ditemukan. Rasio penggantian cadangan migas (Reserve Replacement Ratio / RRR) yang idealnya di atas 100%, kini kerap berada di bawah angka itu. Setiap barel yang diproduksi tidak segera tergantikan oleh penemuan cadangan baru.
Eksplorasi sumur baru minim akibat biaya tinggi, risiko besar, dan regulasi rumit. Kaitannya dengan ketahanan energi jelas: semakin kecil produksi domestik, semakin tinggi ketergantungan impor minyak dan BBM. Ini membuat neraca energi dan neraca perdagangan Indonesia rawan gejolak harga global.
Investasi yang Tertahan
Di tengah situasi ini, tantangan lain datang dari dunia investasi. Banyak kontraktor asing meninggalkan blok-blok tua karena keekonomiannya menipis. Untuk menahan penurunan produksi, SKK Migas perlu menarik investasi besar. Tapi minat investor cenderung menurun.
Menarik minat investor untuk masuk ke hulu migas kini bukan perkara mudah. Transisi energi global membuat banyak perusahaan migas multinasional menyusun ulang portofolio mereka, mengurangi belanja untuk eksplorasi minyak, dan beralih ke gas atau energi rendah karbon. Migas kini bukan prioritas utama.
Bagi Indonesia, yang wilayahnya masih menyimpan potensi besar—dari Cekungan Seram, Natuna, hingga Papua—kondisi ini menjadi pukulan ganda. Biaya eksplorasi di wilayah baru tinggi, risikonya besar, dan sistem fiskal yang rumit sering membuat investor ragu.
SKK Migas berupaya merespons dengan memperkenalkan skema Gross Split dan memangkas rantai birokrasi. SKK Migas juga melakukan promosi agresif dalam Indonesian Petroleum Association (IPA) Convex, tapi hasilnya masih terbatas.
Dalam banyak kasus, persepsi “kurang menarik” masih melekat dibanding negara tetangga seperti Malaysia atau Vietnam. Rezim fiskal dan perizinan di Indonesia dianggap kurang menarik dibanding negara lain.
Padahal, tanpa investasi baru, Indonesia akan sulit menahan laju penurunan produksi. Dan ketika produksi melemah, ketahanan energi menjadi rapuh—negara kehilangan kendali atas pasokan dan harga.
Transisi Energi, Antara Ideal dan Realitas
Dalam tataran global, semua negara berbicara tentang decarbonization. Banyak pihak menekan agar investasi energi fosil dikurangi. Indonesia pun menetapkan target ambisius: mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060.
Tapi di lapangan, realitasnya tak sesederhana itu. Lebih dari 40% energi primer nasional masih berasal dari minyak dan gas, sementara energi baru terbarukan (EBT) belum siap menanggung beban konsumsi nasional. SKK Migas pun terjepit di antara dua agenda: menjaga produksi migas dan mendukung target Net Zero Emission 2060.
Di satu sisi, SKK Migas dituntut mendukung transisi energi; di sisi lain, harus menjaga produksi migas agar ekonomi tetap berdenyut. Dilema ini membuat SKK Migas harus menggeser peran: dari sekadar pengelola produksi menjadi arsitek energi transisi—mendorong carbon capture, efisiensi, dan pemanfaatan gas bumi sebagai “batu loncatan” menuju energi bersih.
Kaitannya dengan ketahanan energi: jika transisi dilakukan tanpa menjaga pasokan migas, Indonesia bisa menghadapi energy shortfall di masa peralihan.
Langkah kompromi mulai muncul: pengembangan carbon capture and storage (CCS/CCUS) di lapangan migas, pemanfaatan gas bumi sebagai “batu loncatan” menuju energi bersih, dan efisiensi operasional yang lebih ramah lingkungan.
Bagi ketahanan energi, pendekatan ini penting. Indonesia tidak bisa menutup kran migas begitu saja tanpa memastikan fondasi energi pengganti yang kokoh.
Birokrasi dan Fragmentasi Regulasi
Masalah klasik lain ada di ranah institusional. Kerumitan birokrasi lintas kementerian masih jadi batu sandungan. SKK Migas bukan operator langsung, melainkan pengelola kontrak kerja sama (Production Sharing Contract/PSC). Banyak keputusan strategis harus melibatkan Kementerian ESDM, BUMN, dan lembaga fiskal lain, seperti Kemenkeu.
Akibatnya, proses eksplorasi—dari izin pengeboran, AMDAL, hingga pengadaan lahan—bisa berlarut. Investor sering mengeluh bahwa time to market proyek migas di Indonesia terlalu panjang dibanding negara pesaing.
Bagi sektor yang bergantung pada momentum ekonomi dan harga global, kelambatan semacam ini bisa berujung pada kehilangan peluang. Dalam konteks ketahanan energi, hambatan birokrasi adalah ancaman senyap yang memperlambat suplai energi domestik. Ia juga meningkatkan risiko defisit pasokan jangka menengah, memperpanjang ketergantungan impor, dan menekan stabilitas nasional.
Meski begitu, tak semua kabar suram. SKK Migas kini mulai menaruh harapan besar pada gas bumi sebagai energi transisi strategis. Cadangan gas Indonesia relatif lebih besar dari minyak, dan permintaan gas domestik terus meningkat—terutama untuk pembangkit listrik dan industri petrokimia.
Proyek-proyek besar seperti Tangguh Train 3 (Papua Barat) dan pengembangan Lapangan Masela (Maluku) diharapkan bisa memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen gas regional dalam beberapa tahun mendatang. Gas juga memiliki nilai geopolitik: sumber daya ini bisa memperkuat diplomasi energi Indonesia di Asia Tenggara.
Target Ambisius dan Strategi Operasional SKK Migas
SKK Migas sendiri telah menetapkan target ambisius: produksi minyak 1 juta barel per hari dan gas 12 miliar kaki kubik standar per hari pada 2030. Namun, data internal menunjukkan bahwa tanpa percepatan eksplorasi dan investasi, produksi minyak mungkin hanya akan mencapai sekitar 888.000 bopd pada tahun itu.
Untuk mewujudkan angka tersebut, SKK Migas memperkirakan dibutuhkan investasi sektor hulu migas hingga USD 186,7 miliar. Realisasi terbaru hingga Agustus 2025 menunjukkan investasi baru mencapai USD 9,38 miliar, masih jauh dari target tahunan sebesar USD 16,5-16,9 miliar.
Dalam hal strategi operasional, SKK Migas menyebut akan melakukan kegiatan pengeboran hingga 1.000 sumur untuk menjaga produksi minyak agar tidak terus menurun, sebagai bagian dari upaya mencapai target 2030.
SKK Migas juga menekankan pentingnya penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR), pengaktifan lapangan tidak aktif, dan pemanfaatan “reserve-to-production” (R2P) untuk memperkuat cadangan.
Tentang tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan kapasitas nasional, dalam program IOG Transformation, SKK Migas menargetkan TKDN yang tinggi — hingga mencapai 63% pada semester I 2022 dalam industri hulu migas.
SKK Migas juga mencatat bahwa terdapat 301 struktur migas dengan potensi 1,8 miliar barel minyak (Bbo) dan 13,4 triliun kaki kubik gas belum dikembangkan, yang menjadi bagian dari strategi jangka panjang.
Peran Strategis SKK Migas
Industri hulu migas kini ibarat penyeimbang di papan jungkat-jungkit: di satu sisi menopang stabilitas energi hari ini, di sisi lain harus menyiapkan ruang bagi energi masa depan.
SKK Migas memegang peran strategis di tengah transisi ini—tidak lagi sekadar operator ekonomi, tapi arsitek ketahanan energi nasional. SKK Migas punya tugas ganda: menjaga produksi agar ekonomi tetap hidup, sekaligus memastikan sektor ini beradaptasi dengan paradigma energi masa depan.
Kunci keberhasilan bukan hanya seberapa banyak barel yang diproduksi, melainkan seberapa cepat Indonesia bisa memanfaatkan sisa momentum migas untuk membangun infrastruktur, inovasi, dan diversifikasi energi jangka panjang.
Ketahanan energi tidak lahir dari idealisme semata, melainkan dari realitas yang dikelola dengan cerdas.Dan dalam realitas hari ini, industri hulu migas masih menjadi pilar yang menahan tubuh besar bernama Indonesia agar tetap tegak menghadapi masa depan energi yang belum pasti.
Indonesia sedang berada di simpang jalan antara ketergantungan pada migas lama dan impian energi baru terbarukan. Selama transisi belum sepenuhnya siap, industri hulu migas tetap menjadi pilar utama ketahanan energi nasional.
Depok, 19 Oktober 2025
*Satrio Arismunandar adalah Pemimpin Redaksi OrbitIndonesia.com. Email: sawitriarismunandar@gmail.com. Mobile/WA: 081286299061. ***