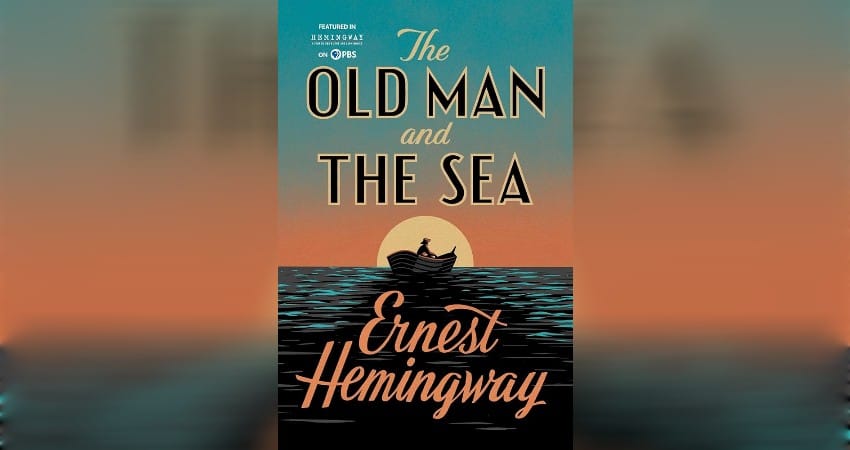Resensi Buku The Old Man and the Sea Karya Ernest Hemingway: Ketabahan Manusia di Hadapan Laut dan Takdir
ORBITINDONESIA.COM- Di antara semua karya besar Ernest Hemingway, tidak ada yang lebih jernih sekaligus mendalam daripada The Old Man and the Sea (1952). Novel ini adalah puncak dari seluruh estetika Hemingway—kesederhanaan, kejujuran, dan kehormatan manusia dalam menghadapi penderitaan.
Dengan hanya dua tokoh utama dan bentangan laut Kuba yang sunyi, Hemingway berhasil menciptakan kisah tentang keberanian eksistensial: seorang nelayan tua bernama Santiago yang berjuang sendirian menangkap seekor ikan marlin raksasa, melawan alam, waktu, dan dirinya sendiri.
Karya ini terbit ketika Hemingway mulai dianggap “selesai” oleh banyak kritikus. Namun justru melalui kisah sederhana ini, ia merebut kembali reputasinya—dan meraih Hadiah Pulitzer tahun 1953, diikuti Hadiah Nobel Sastra tahun 1954.
Hemingway menulis bukan untuk memamerkan gaya, melainkan untuk mengembalikan sastra pada kejujuran yang paling dasar: pergulatan manusia dengan nasib.
Isi dan Struktur Novel: Pertarungan di Laut, Pertarungan dengan Diri Sendiri
Novel ini terbagi menjadi tiga bagian besar yang berputar di sekitar satu peristiwa sentral: perjuangan Santiago melawan seekor marlin raksasa di Teluk Meksiko.
Bagian pertama memperkenalkan Santiago—seorang nelayan tua yang selama 84 hari tidak menangkap seekor ikan pun. Ia hidup miskin di sebuah pondok kecil, ditemani muridnya, Manolin, yang sangat mencintainya namun dilarang orang tuanya melaut bersama si tua karena dianggap sial. Hari ke-85 menjadi simbol harapan terakhir. Santiago berlayar sendirian ke laut yang lebih jauh, menantang takdir dan rasa tuanya sendiri.
Bagian kedua adalah inti kisah: pergulatan epik antara manusia dan alam. Setelah berhari-hari di laut, umpannya disambar seekor marlin yang begitu besar hingga perahu kecilnya terseret berkilometer jauhnya. Santiago tidak memotong tali, tidak menyerah.
Ia menahan rasa sakit di tangan, lapar, dan kelelahan, sambil berbicara kepada dirinya sendiri dan kepada ikan, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sesama makhluk yang terhormat. Ia berkata: “Kau adalah saudaraku, ikan. Tapi aku harus membunuhmu.” Kalimat itu menjadi inti moral novel ini: pertarungan bukanlah kebencian, melainkan ujian martabat.
Bagian ketiga menutup dengan nada tragis: setelah berhasil membunuh marlin, Santiago mengikat ikan itu di sisi perahunya untuk dibawa pulang. Namun di perjalanan, kawanan hiu mencium darah dan menyerang.
Santiago berjuang dengan tombak dan dayung, tapi pada akhirnya yang tersisa hanyalah kerangka marlin—sebuah kemenangan yang berubah menjadi kekalahan simbolis.
Ia kembali ke desanya, rebah di pondoknya, sementara anak laki-laki itu menangis melihat tangan gurunya yang luka parah. Di akhir kisah, Santiago tertidur dan bermimpi tentang singa-singa di pantai Afrika — lambang kekuatan dan masa mudanya yang abadi dalam kenangan.
Makna Filsafatnya: Manusia, Martabat, dan Batas Takdir
Secara lahiriah, The Old Man and the Sea adalah kisah tentang nelayan. Namun di balik permukaan, Hemingway menulis sebuah alegori eksistensialis: manusia hidup untuk berjuang, bukan untuk menang.
Santiago tidak menolak kekalahan, tetapi menolak kehilangan makna. Ia tahu laut bisa membunuhnya, ikan bisa membuatnya hancur, hiu bisa merampas hasil tangkapannya—namun selama ia melawan, martabatnya tetap utuh.
Dalam prinsip Hemingway yang dikenal sebagai kode “grace under pressure”, Santiago adalah perwujudan manusia yang anggun dalam penderitaan. Ia tidak mengeluh, tidak mencari simpati, dan tidak menyerah bahkan ketika takdirnya jelas.
Hemingway menulis dengan kalimat pendek, ritmis, seolah setiap kata ditempa dari baja moral. Santiago tidak hanya melawan ikan, ia melawan nihilisme—rasa kosong bahwa hidup tak berarti. Ia menunjukkan bahwa makna bukanlah hasil, tetapi cara bertahan.
Novel ini juga menampilkan pandangan metafisik Hemingway tentang hubungan manusia dengan alam. Laut bukan musuh, tetapi cermin eksistensi: luas, kejam, indah, dan tak peduli.
Santiago menyebut laut “la mar” — dalam bentuk feminin — karena ia menganggapnya seperti seorang kekasih yang kadang lembut, kadang murka. Di sinilah muncul nuansa spiritual tersembunyi: dalam kesepian dan penderitaan, manusia justru menemukan kehadiran yang lebih besar dari dirinya sendiri.
Santiago sebagai Simbol: Heroisme yang Sunyi
Santiago bukan pahlawan besar dalam pengertian klasik. Ia miskin, tua, dan sendirian. Tapi Hemingway menjadikannya archetype hero baru — pahlawan yang menemukan kemuliaan justru dalam kegagalan.
Ia seperti Prometheus yang mencuri api dari dewa dan dihukum tanpa ampun, atau seperti Sisyphus dalam tafsir Albert Camus: terus mendorong batu ke puncak meski tahu akan jatuh lagi. Dalam hal ini, Santiago adalah alegori tentang absurditas hidup manusia, namun dengan nada yang hangat dan penuh kasih.
Kegigihannya melampaui logika ekonomi (ia tidak melaut demi uang), melampaui ego (ia memuji marlin yang hendak ia bunuh), bahkan melampaui agama (ia berdoa, tapi tahu hasilnya tergantung dirinya sendiri).
Ia adalah manusia yang berdamai dengan kekalahan tanpa berhenti berjuang — semacam spiritualitas sekuler yang menjadi inti etika Hemingway.
Relevansi dan Nilai Kontemporer: Di Tengah Dunia yang Serba Cepat
Membaca The Old Man and the Sea di abad ke-21 terasa seperti menemukan air jernih di tengah kebisingan digital. Di zaman yang mengukur kesuksesan dari hasil dan citra, Hemingway menegaskan nilai keteguhan batin dan kerja sunyi.
Santiago mengingatkan bahwa kemenangan sejati adalah tetap berpegang pada nilai-nilai kita ketika dunia tampak tidak adil.
Bagi pembaca modern, novel ini bisa dibaca sebagai metafora ketahanan psikologis — tentang melawan depresi, ketidakpastian, dan kegagalan tanpa kehilangan arah.
Hemingway, yang sendiri pernah bergulat dengan trauma perang dan alkoholisme, menulis kisah ini sebagai bentuk penyembuhan batin. Laut menjadi ruang terapi, dan ikan menjadi simbol makna yang harus diraih walau akhirnya hilang.
Lebih luas lagi, karya ini juga mengandung kritik terhadap pandangan utilitarian modern: bahwa hidup hanya bernilai jika menghasilkan sesuatu yang konkret. Santiago membuktikan sebaliknya — bahwa hasil bisa hilang, tapi makna dari perjuangan akan tetap hidup.
Penutup: Keheningan, Keindahan, dan Martabat Manusia
The Old Man and the Sea bukan hanya novel tentang nelayan; ia adalah doa panjang tentang keberanian yang tidak perlu disaksikan siapa pun. Hemingway, dengan bahasa yang jernih dan tanpa hiasan, mengembalikan sastra ke esensinya: menyingkap martabat manusia di bawah cahaya penderitaan.
Santiago akhirnya tidur, bermimpi tentang singa-singa muda di pantai Afrika—bukan karena ia kembali muda, tetapi karena semangat itu tidak pernah mati. Dalam mimpi itu, Hemingway menutup novel dengan keheningan yang menggema: manusia boleh kalah dalam tubuh, tapi tidak dalam jiwa.
Bagi siapa pun yang pernah berjuang sendirian melawan kehidupan, Hemingway berbicara tanpa kata-kata:
“Man can be destroyed but not defeated.”
Manusia bisa dihancurkan, tapi tidak bisa dikalahkan.
Itulah inti abadi dari The Old Man and the Sea — sebuah puisi tentang martabat yang tak lekang oleh waktu.***