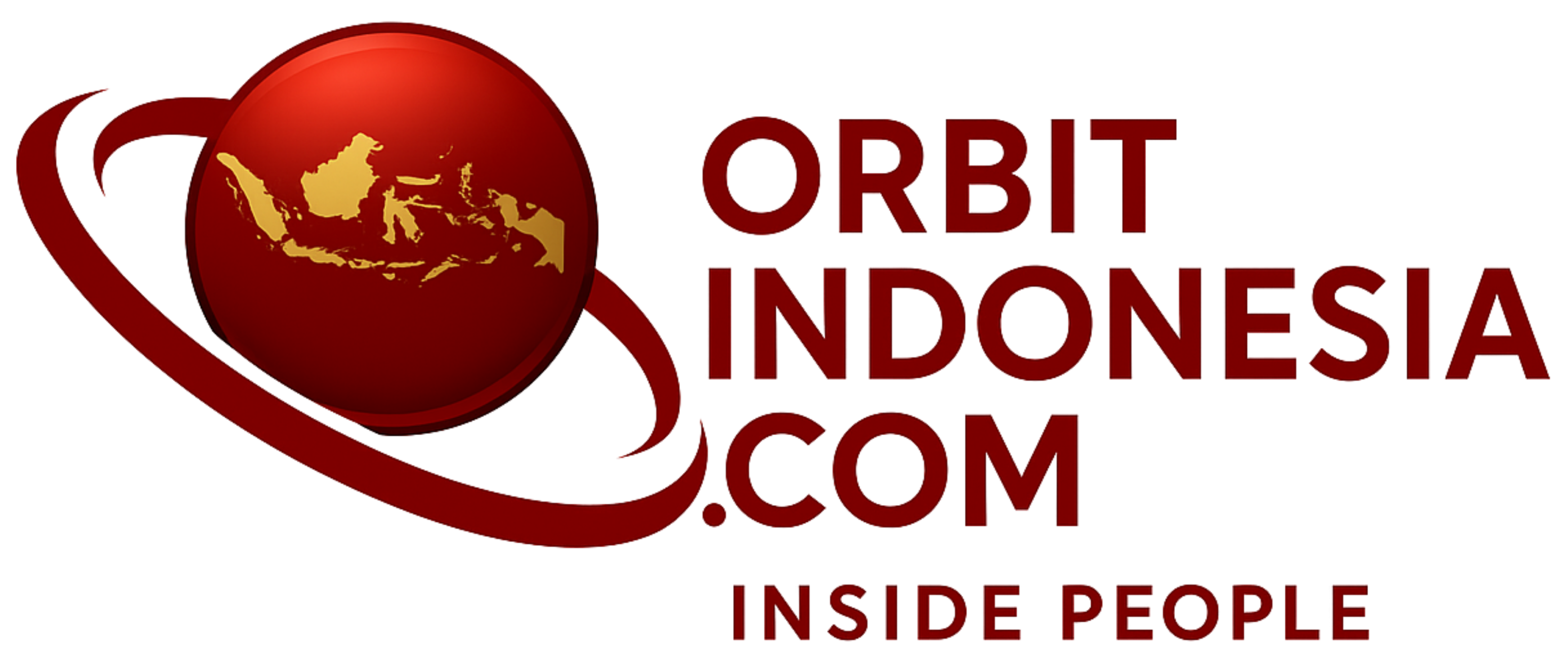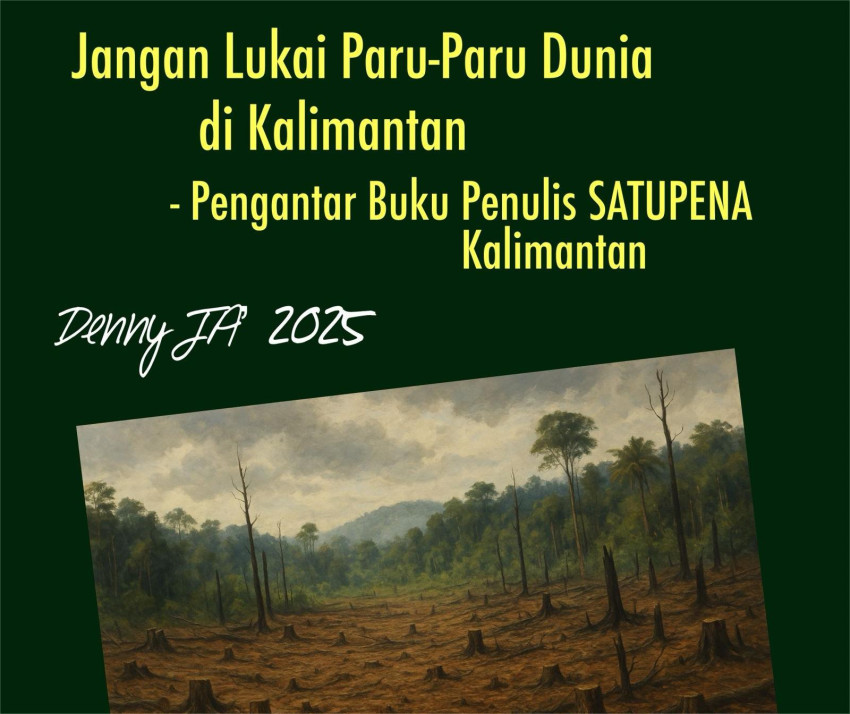Catatan Denny JA: Jangan Lukai Paru-Paru Dunia di Kalimantan
- Pengantar Buku Perkumpulan Penulis SATUPENA Kalimantan, “Kalimantan Bukan Tanah Kuburan,” (2025)
Oleh Denny JA
Pagi di tepian Sungai Mahakam kini sunyi. Dulu, suara burung enggang memecah kabut, kini hanya deru mesin gergaji yang terdengar.
Air sungai yang dulu jernih, tempat anak-anak mandi dan ibu mencuci, kini berubah keruh, meninggalkan bekas minyak di permukaan. Di kampung Long Iram, petani rotan kehilangan hutan tempat mereka menggantung hidup.
“Dulu satu hari cukup panen rotan buat makan seminggu,” kata Pak Iwan lirih, “sekarang rotan pun hilang, air pun sakit.” Hutan yang lenyap bukan hanya pepohonan, tapi juga napas, cerita, dan doa manusia yang bergantung padanya.
Kalimantan pernah disebut paru-paru dunia. Itu bukan metafora kosong, melainkan pengakuan atas peran ekologisnya bagi seluruh umat manusia.
Namun kini, paru-paru itu tersengal, tercekik oleh manusia yang tega. Dalam epilog, Dr. Urotul Aliyah, S. Pd., M.Pd mencatat dengan getir bahwa lebih dari tiga juta hektar hutan telah hilang dalam dua dekade terakhir.
Angka itu bukan sekadar statistik, melainkan epitaf bagi pepohonan yang ditebang, sungai yang menghitam, dan nyanyian alam yang kini terhenti.
“Ketika hutan dan sungai rusak,” tulisnya, “mereka tidak hanya kehilangan mata pencaharian, tetapi juga kehilangan makna hidup.”
Kalimat ini menembus batas data ilmiah; ia menyentuh dimensi spiritual masyarakat Dayak dan Banjar yang memandang hutan sebagai ibu, bukan sumber daya.
Inilah ecological grief—duka ekologis yang sunyi namun dalam, ketika manusia meratap bukan karena lapar, melainkan karena kehilangan rumah bagi jiwanya.
Di balik gegap gempita pembangunan, Kalimantan justru menanggung beban terberat: air tercemar tambang, udara sesak oleh debu batu bara, dan anak-anak tumbuh tanpa mengenal aroma rimba.
Duka ekologis berubah menjadi trauma sosial, karena hilangnya hutan berarti juga hilangnya sejarah dan doa yang diwariskan leluhur.
-000-
Kita, bangsa Indonesia, tidak bisa membiarkan paru-paru dunia ini terus berdarah. Hutan Kalimantan bukan hanya milik Kalimantan, tetapi milik peradaban itu sendiri.
Setiap pohon yang ditebang tanpa hati adalah pengkhianatan terhadap masa depan anak manusia. Maka, saatnya kita berhenti memperlakukan bumi sebagai tambang keuntungan.
Saatnya kita mendengar kembali napas hutan—yang melemah, tapi masih memanggil: “Jangan lukai aku lagi.”
-000-
Membaca epilog buku ini, “Kalimantan Menulis: Perspektif Psikologi Konseling,” oleh editor buku Dr. Urotul Aliyah, soal luka paru- paru dunia di kalimantan, saya teringat hal serupa di hutan Amazon, Brazil. Sebuah buku riset menulis soal ini.
Judul bukunya: The Decade of Destruction: The Crusade to Save the Amazon Rain Forest, terbit tahun 1990.
Ada kalimat yang menghantui setelah membaca The Decade of Destruction: “The forest was not silent—it screamed, but the world did not listen.” Hutan tidak diam. Ia berteriak. Tapi dunia tak ingin mendengar.
Kalimat itu menggambarkan tragedi terbesar abad ini: bagaimana Amazon, paru-paru dunia yang dulu hijau dan luas bagai samudra daun, perlahan mati. Itu karena tangan manusia yang rakus dan tuli terhadap jeritan alam.
Peter Matthiessen menulis kisah ini bukan sebagai laporan jurnalistik semata, tetapi sebagai elegi bagi kehidupan yang hilang.
Ia menuturkan bagaimana hutan Amazon dijarah oleh pembalak liar, dibakar untuk peternakan dan kebun kedelai, serta dibelah oleh sungai-sungai yang kini keruh oleh lumpur tambang.
Di balik kepulan asap dan deru mesin, ada air mata penduduk pribumi Yanomami dan Kayapo yang kehilangan rumah spiritual mereka. Hutan, yang dulu menjadi ibu dan guru bagi manusia, kini menjadi kuburannya sendiri.
Namun yang membuat buku ini bergetar bukan hanya kisah kehancuran ekologis, melainkan ironi moralnya: peradaban modern yang merasa beradab justru menjadi algojo bagi bumi yang melahirkannya.
Dalam setiap hektar yang terbakar, tersisa abu yang membawa aroma penyesalan umat manusia.
Kisah Amazon adalah cermin bagi Kalimantan. Di kedua belahan dunia ini, sejarah berjalan dengan pola yang sama: hutan dibuka atas nama pembangunan.
Tambang dibenarkan atas nama kemajuan, dan masyarakat adat disingkirkan atas nama nasionalisme ekonomi.
Dulu di Amazon, kini di Mahakam dan Barito. Dulu bagi suku Kayapo, kini bagi Dayak dan Banjar. Luka ekologis itu bersifat universal. Ia menembus bahasa, agama, dan bendera.
Kalimantan, seperti Amazon, bukan sekadar hamparan pepohonan. Ia adalah paru-paru dunia yang menghidupi jutaan jiwa.
Ketika pohon terakhir tumbang, bukan hanya udara yang hilang, melainkan ingatan tentang bagaimana manusia seharusnya hidup selaras dengan bumi.
Kita mungkin tak bisa menyelamatkan seluruh hutan yang telah rubuh, tapi kita masih bisa menyelamatkan hati kita dari sikap apatis.
Isu ini penting karena ia menolak keheningan. Ia memaksa kita mendengar kembali napas bumi—lemah, tersengal, tapi belum padam.
Dan dari Kalimantan, dari tanah yang dulu disebut “tanah kuburan,” kita bisa memulai kebangkitan baru: menjadikan hutan bukan sebagai korban pembangunan, tetapi sebagai jantung peradaban.
Sebab ketika paru-paru dunia mati, tak ada bangsa yang bisa bernapas lagi.
-000-
Epilog yang juga mengupas paru- paru dunia di Kalimantan hanya salah satu tulisan di kumpulan karya di buku ini.
Ada satu kalimat dari pengantar Muhammad Thobroni yang mengguncang kesadaran kita: “Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga konstruksi sosial yang membentuk realitas.”
Di sinilah tesis besar buku Antologi Kalimantan Bukan Tanah Kuburan (2025) berdiri. Ini sebuah perlawanan terhadap narasi Jawa-sentris.
Selama ini kita membekukan Kalimantan dalam bayang-bayang “tanah pembuangan”, “tempat mati”, atau “daerah pinggiran.”
Melalui pena para penulis Satupena Kalimantan, mitos itu diretas, dan suara Kalimantan kembali berdenyut sebagai pusat kehidupan, bukan kuburan sejarah.
Buku ini merupakan karya kolektif dari banyak penulis Satupena Kalimantan yang mengekspresikan lebih dari 70 karya. Ia terdiri dari cerpen, monolog, puisi, dan esai.
Masing-masing tulisan memantulkan denyut sosial, kultural, dan spiritual masyarakat Kalimantan yang selama ini luput dari wacana nasional.
Dari kisah perempuan yang bertahan di tepi hutan, guru yang melawan ketimpangan pendidikan di pedalaman, hingga anak muda yang kehilangan identitas di tengah tambang batu bara.
Di setiap kisah adalah fragmen dari tubuh besar bernama Borneo. Di luar isu lingkungan, buku ini juga menyoroti tiga tema besar lain.
Pertama, isu identitas dan sejarah lokal. Para penulisnya menuntut agar peran Kalimantan dalam sejarah nasional—seperti Kesultanan Banjar dan Kutai—tidak lagi direduksi menjadi catatan kaki.
Kedua, isu perempuan dan kemiskinan struktural. Ini diekspresikan dalam kisah pekerja rumah tangga, istri tambang, dan guru-guru desa yang berjuang menembus keterbatasan.
Ketiga, isu pendidikan dan literasi, yang menjadi benang merah dari semangat Satupena: menulis untuk menghidupkan kesadaran.
Buku ini penting karena ia bukan sekadar antologi sastra dan esai, melainkan peta moral dan ekologis bagi Indonesia.
Dari setiap halaman, kita diajak menatap Kalimantan bukan sebagai ruang asing di peta, tetapi sebagai cermin nasib bangsa. Ketika satu paru-paru dunia terluka, seluruh tubuh Indonesia ikut sesak.
Karya ini mengingatkan bahwa pusat peradaban tidak pernah tunggal. Ia bisa lahir dari tepi sungai Mahakam, dari desa di Barito, atau dari suara perempuan yang menulis di bawah cahaya redup di Pangkalan Bun.
Antologi Kalimantan Bukan Tanah Kuburan adalah bukti bahwa kehidupan, sekeras apa pun ditekan, selalu mencari cara untuk bernapas—dan kini, ia bernapas lewat kata.
-000-
Dari halaman terakhir buku Kalimantan Bukan Tanah Kuburan, kita tidak sedang membaca sekadar antologi.
Kita sedang menyimak napas bumi yang lemah, namun masih berdenyut. Setiap kata dari para penulis Satupena Kalimantan terasa seperti seruan terakhir hutan yang mencoba berbicara kepada kita.
Manusia modern terlalu sibuk menghitung laba hingga lupa mendengar desir angin dan degup sungai.
Kalimantan bukan kuburan, ia masih hidup. Tapi kehidupan itu kini berada di ambang antara napas dan sesak. Ia menunggu uluran tangan kita untuk memulihkan paru-paru yang telah robek, menenangkan sungai yang menangis, dan menanam kembali akar harapan di tanah yang telah lama kehilangan teduh.
Bila kita gagal melakukannya, sejarah akan mencatat bukan hanya punahnya hutan tropis, tetapi juga pudarnya kemanusiaan kita sendiri.
Mari kita dengar suara yang datang dari jantung hutan itu: lembut, tapi mendesak. Ia berkata, “Aku masih ingin hidup, tapi hanya bisa jika engkau berhenti membunuhku.”
Dari Kalimantan hingga Amazon, dari Borneo hingga bumi manusia, seruan itu satu: selamatkan paru-paru dunia, sebelum bumi ini kehabisan napas.*
Jakarta, 17 Oktober 2025
Referensi
1. Peter Matthiessen. The Decade of Destruction: The Crusade to Save the Amazon Rain Forest. Penguin Books, 1990.
2. Perkumpulan Penulis Satupena Kalimantan. Antologi Kalimantan Bukan Tanah Kuburan. Satupena Press, 2025.
-000-
Ratusan esai Denny JA soal filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, politik demokrasi, sejarah, positive psychology, catatan perjalanan, review buku, film dan lagu, bisa dilihat di FaceBook Denny JA’s World
https://www.facebook.com/share/p/1JDd4jJoxa/?mibextid=wwXIfr ***